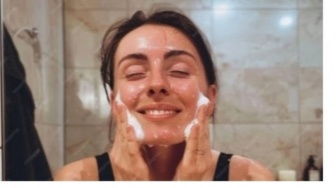Di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial sering dipuja sebagai ruang ekspresi tanpa batas. Setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, menyampaikan pendapat, bahkan menciptakan identitas baru yang mungkin berbeda dari kesehariannya.
Namun, di balik kebebasan itu, tumbuh subur praktik yang justru melukai: bullying di dunia maya. Fenomena ini kian mengkhawatirkan ketika para pelaku bersembunyi di balik akun anonim, menjadikan serangan verbal terasa aman bagi mereka, tetapi berbahaya bagi korban.
Bullying di media sosial tidak hanya soal ejekan sesaat. Ia bisa menjelma dalam bentuk perundungan berulang, penyebaran fitnah, pengucilan digital, hingga hujan komentar penuh kebencian. Di Indonesia, kasus semacam ini semakin sering muncul ke permukaan. Survei Microsoft pada 2021 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat paparan tidak sopan di ruang digital tertinggi di Asia Tenggara.
Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat bahwa aduan kasus perundungan, termasuk yang terjadi di media sosial, menduduki peringkat tiga besar setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan kenyataan bahwa ruang virtual yang semestinya memberi manfaat justru bisa menjadi sumber luka psikologis.
Keberadaan akun anonim memberi ruang aman bagi pelaku untuk merasa kebal dari konsekuensi. Nama samaran, foto profil palsu, dan identitas yang sulit dilacak menjadikan media sosial bagai panggung tanpa wajah.
Dari balik tirai anonimitas itu, kata-kata kasar mudah meluncur, fitnah bisa diciptakan, dan ajakan untuk mengucilkan seseorang bisa dengan cepat menyebar. Yang sering dilupakan, korban di balik layar bukan sekadar objek di dunia maya. Mereka manusia nyata dengan perasaan yang bisa terluka, kesehatan mental yang bisa terganggu, dan kehidupan sosial yang bisa terguncang.
Kita sering menyaksikan kasus artis, pejabat publik, atau figur terkenal menjadi sasaran serangan kolektif di media sosial. Mereka dianggap lebih tahan menghadapi komentar pedas karena sudah terbiasa berada di sorotan publik. Padahal, tidak ada manusia yang sepenuhnya kebal terhadap ujaran kebencian.
Bahkan individu dengan popularitas besar sekalipun bisa merasa terpojok dan mengalami tekanan berat. Lebih berbahaya lagi, praktik bullying di media sosial juga menimpa orang biasa, termasuk anak-anak dan remaja yang sedang mencari jati diri. Banyak kasus di mana korban akhirnya memilih mundur dari ruang digital, mengalami depresi, bahkan ada yang berujung pada tindakan tragis.
Fenomena ini tidak bisa dipandang sepele. Media sosial kini bukan sekadar ruang hiburan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sanalah relasi sosial dibangun, informasi dibagikan, dan identitas pribadi dikonstruksi. Ketika bullying dibiarkan tumbuh, ia akan menciptakan iklim interaksi yang penuh ketakutan dan memudarkan kepercayaan terhadap manfaat teknologi digital.
Tentu anonimitas tidak selalu buruk. Dalam banyak kasus, anonimitas justru melindungi kelompok rentan seperti korban kekerasan atau aktivis yang mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, ketika anonimitas digunakan untuk menyerang, merendahkan, dan merusak martabat orang lain, maka ia berubah menjadi senjata yang merusak. Di titik inilah pentingnya regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten.
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki aturan mengenai penyalahgunaan teknologi informasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penerapannya masih sering dianggap tidak konsisten.
Kasus-kasus besar mungkin mendapat perhatian, tetapi perundungan yang menimpa orang biasa sering terabaikan. Sementara itu, platform media sosial sebagai penyedia ruang interaksi masih lebih banyak berfokus pada aspek bisnis ketimbang perlindungan pengguna. Fitur pelaporan memang ada, tetapi jarang benar-benar efektif menghentikan perundungan yang sistematis.
Yang lebih mendesak adalah pembangunan kesadaran kolektif. Bullying di media sosial tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Masyarakat perlu menumbuhkan budaya saling menghormati, mengingatkan, dan tidak mudah ikut-ikutan dalam arus perundungan digital.
Literasi digital harus diperkuat, terutama bagi generasi muda, agar mereka memahami bahwa kata-kata di dunia maya sama nyatanya dengan tindakan di dunia nyata. Pendidikan karakter yang menekankan empati dan tanggung jawab sosial juga penting untuk menekan angka perundungan.
Akun anonim tidak semestinya menjadi topeng untuk menyakiti orang lain. Ia hanya akan menjadi sarana sehat apabila digunakan untuk melindungi kebebasan berekspresi tanpa menyinggung martabat sesama.
Demokrasi digital hanya bisa berjalan bila ruang interaksi di media sosial bebas dari intimidasi. Tugas kita bersama adalah menjadikan media sosial sebagai ruang aman, tempat perbedaan pendapat bisa diungkapkan tanpa harus menimbulkan luka bagi orang lain.