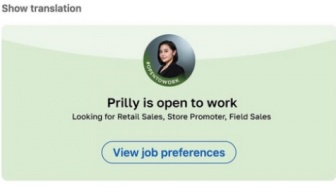Zaman sekarang, remaja bukan cuma akrab dengan buku pelajaran dan tugas sekolah, tapi juga dengan keranjang belanja online. Bangun tidur cek notifikasi, siang scroll media sosial, malamnya—entah sadar atau tidak—jari sudah refleks menekan tombol checkout. Bukan karena butuh, tapi karena “lagi diskon” atau “takut kehabisan”. Begitulah kira-kira potret perilaku konsumtif remaja di era digital: cepat, impulsif, dan sering kali tanpa mikir panjang.
Internet memang memberi banyak kemudahan, tapi juga membuka pintu godaan selebar-lebarnya. E-commerce berlomba-lomba memanjakan pengguna dengan gratis ongkir, potongan harga, dan pembayaran yang bisa dicicil nanti.
Semua dibuat sesederhana mungkin, bahkan sampai ada fitur “beli sekarang” yang rasanya lebih cepat dari proses mikir itu sendiri. Bagi remaja yang emosinya masih naik-turun kayak grafik saham, belanja impulsif jadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan.
Masalahnya bukan cuma soal uang, tapi soal dorongan untuk selalu ikut tren. Media sosial punya peran besar di sini.
Setiap hari, remaja disuguhi konten pamer barang baru: sepatu edisi terbaru, skincare yang katanya holy grail, sampai gawai yang “wajib punya biar nggak ketinggalan zaman”. Influencer tampil meyakinkan, visualnya estetik, narasinya persuasif. Lama-lama muncul perasaan, “Kalau aku nggak punya ini, apa aku kurang keren?”
Di titik inilah belanja berubah fungsi. Bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas. Barang yang dibeli jadi semacam alat untuk membangun citra diri: biar dianggap gaul, biar sejajar dengan teman-teman, atau sekadar biar nggak merasa asing di tongkrongan.
Lingkungan pertemanan ikut menyumbang tekanan halus. Ketika semua orang pakai barang yang sama, rasanya aneh kalau kita tidak ikut-ikutan. Akhirnya, belanja dilakukan demi validasi sosial, bukan kepuasan pribadi.
Sayangnya, kebiasaan ini punya efek samping yang nggak kelihatan di awal. Banyak remaja belum paham cara mengatur keuangan, apalagi soal prioritas.
Uang jajan habis sebelum akhir bulan, lalu mulai melirik pinjaman kecil, paylater, atau minta tambahan dengan alasan yang terdengar “masuk akal”. Kebutuhan penting kadang dikorbankan demi keinginan sesaat. Padahal, pola seperti ini kalau dibiarkan bisa jadi kebiasaan buruk yang terbawa sampai dewasa.
Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsep diri remaja berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mereka. Artinya, semakin besar kebutuhan untuk diakui, semakin besar pula dorongan untuk membeli barang sebagai simbol nilai diri.
Belanja jadi cara cepat untuk merasa “cukup”, meski efeknya sering kali cuma sementara. Setelah euforia datang paket reda, yang tersisa justru rasa menyesal, dan saldo yang makin menipis.
Di sinilah peran orang tua dan sekolah jadi penting, meski sering terdengar klise. Keluarga bukan cuma tempat minta uang, tapi juga ruang belajar soal nilai dan prioritas. Cara orang tua mengelola keuangan, bersikap terhadap barang, dan mengambil keputusan belanja diam-diam ditiru oleh anak.
Sementara itu, sekolah bisa jadi tempat strategis untuk mengenalkan literasi keuangan dengan cara yang relevan dan nggak membosankan.
Bayangkan kalau remaja diajak simulasi mengatur uang bulanan, belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, atau diajak diskusi kritis soal iklan dan budaya konsumsi. Setidaknya, mereka jadi lebih sadar bahwa tidak semua diskon itu perlu dikejar, dan tidak semua tren harus diikuti.
Pada akhirnya, perilaku konsumtif remaja bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari kombinasi teknologi yang memanjakan, media yang merayu, lingkungan yang menekan, dan minimnya bekal literasi keuangan.
Mengubahnya memang tidak instan. Tapi dengan kesadaran, pendampingan, dan edukasi yang tepat, remaja bisa belajar satu hal penting: bahagia itu bukan soal seberapa sering checkout, tapi seberapa bijak kita mengatur apa yang kita punya.