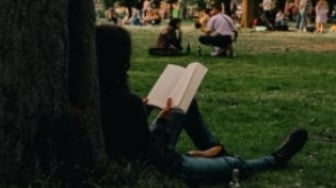Culture Meets Market kolaborasi CORE Indonesia dan Urban Culture Lab, Tokyo City University, Senin (08/9/25), membedah fenomena cute economy—ekonomi berbasis “imut”. Materi ini dipaparkan Prof. Riela Provi Drianda, Associate Professor sekaligus Kepala Urban Culture Lab, Tokyo City University.
Menurut Prof. Riela, cute economy mulai muncul sekitar 2014 ketika tren berbagi konten hewan lucu seperti kucing atau kelinci di media sosial meledak. Komentar sederhana seperti “aww” ternyata bisa berkembang jadi komunitas, lalu melahirkan pasar baru bernilai tinggi.
Jepang menjadi contoh suksesnya. Karakter Rilakkuma dan Chikawa bukan sekadar hiburan anak-anak, tapi juga menempel pada generasi yang kini punya daya beli besar. Loyalitas masa kecil itu bertransformasi menjadi konsumsi.

Rilakkuma bahkan dijadikan ikon resmi Kota Chiyoda, hadir dalam bentuk souvenir, restoran tematik, hingga dekorasi museum. Dampaknya, retail market size karakter ini bisa menembus 250 juta yen.
Sementara lisensi Chikawa menyeberang hingga Hong Kong, dipakai untuk menghias stasiun dan kereta, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif.
“Bagi orang Jepang, superhero bukanlah sosok besar dan berotot, tapi karakter kecil, muda, dan imut,” jelas Prof. Riela, menyinggung dominasi Detective Conan atas film Marvel di box office Jepang.
Ia mengingatkan, persepsi “imut” berbeda di tiap budaya. Produk yang laku di Indonesia bisa gagal di Jepang, begitu pula sebaliknya. Artinya, strategi desain dan kemasan harus menyesuaikan pasar.
Tren lintas negara pun makin terlihat. Di Indonesia, anak muda mengadopsi street fashion ala Jepang, sementara generasi muda Jepang makin serius dalam perawatan kulit. Riset kecil mahasiswa Jepang menemukan, 70 persen responden berminat membeli bath bomb dengan aroma khas Indonesia, bahkan menilainya cocok jadi souvenir.
Temuan ini menegaskan: kombinasi estetika kawaii Jepang dengan kekayaan lokal Indonesia berpotensi besar menembus pasar Asia Timur.
Kini cute economy bukan sekadar estetika, tapi strategi ekonomi berbasis emosi dan identitas—sekaligus jalan baru bagi diplomasi budaya Indonesia.
Penulis: Muhammad Ryan Sabiti