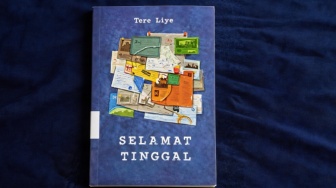Sebuah kota, terlebih ibu kota tentu membutuhkan pondasi yng menjadi dasar apapun yang berada di dalamnya. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memunculkan nilai-nilai baru, seperti semangat motivasi, kreativitas, dan disiplin.
Seperti yang disampaikan Presiden, kehadiran IKN dibarengi dengan upaya membangun kota baru sebagai bentuk reformasi. Dalam konteks IKN, reformasi ini mengakar pada struktur ruang kota, menjadi kunci utama yang membentuk kekuatannya.
Struktur kota yang kuat didukung oleh pemukiman yang kokoh, serta diperkuat oleh jaringan pelayanan yang berfungsi optimal.
Pertumbuhan IKN tentu tidak bisa berkembang sesuai target dan harapan tanpa adanya akses jaringan yang terintegrasi seperti jalan, air bersih, pengelolaan sampah, serta ketersediaan layanan telekomunikasi dan digital.
Segala hal negatif dari ibu kota sebelumnya harus bisa ditinggalkan dan mengambil sisi positifnya. Jakarta, sekali setiap enam bulan saya pergi ke kota ini, bisa disebut sebagai kota modern.
Sayangnya, kota ini belum mampu menciptakan sebuah nilai yang mendorong perkembangan kebiasaaan dan budaya baru. Struktur dan bentuk ruang yang ada akan membentuk "budaya kota" dan menciptakan nilai-nilai baru.
Sebagai contoh, mengapa budaya menggunakan transportasi publik atau berjalan kaki sulit berkembang di Jakarta? Ini karena struktur jaringan transportasinya lebih mengedepankan jalan daripada kereta rel. Jika manusia gagal membangun struktur kotanya, maka budayanya juga akan mengalami kegagalan.
Nusantara bisa belajar dari Singapura, untuk masalah akses transportasi publik. Luas Singapura sedikit lebih besar dari Jakarta, namun jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jabodetabek.
Keunikan Singapura tidak hanya kedisiplinan warganya, melainkan juga pada akses transportasi umum yang sangat prima. Salah satunya ada pada jaringan rel kereta api yang terhubung, menjangkau simpul-simpul aktivitas di seluruh wilayah, baik di pusat kota maupun di pinggiran.
Bayangkan betapa luar biasanya penggunaan transportasi melalui jaringan rel kereta api. Keuntungan-keuntungan meliputi efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, ketepatan waktu, kemudahan akses, dan keterhubungan dengan sistem modern. Struktur ini, dengan segala keunggulannya, menjadi kekuatan yang tak terbantahkan.
Jika kita menghadapi tugas membangun IKN, maka akan ada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang menjadi pedoman. Dalam konteks transportasi, IKN menetapkan batasan waktu tempuh maksimal 30 menit, yang pada hakikatnya membicarakan tentang fondasi, yaitu struktur jaringan pelayanan.
Penggambaran waktu tempuh maksimal 30 menit dalam IKN menciptakan gambaran kelancaran, ketepatan, kemudahan, kenyamanan, serta efisiensi. Pilihan yang muncul secara otomatis adalah implementasi jaringan kereta api, seperti LRT dan MRT.
Lantas, menarik disimak apakah nilai atau angka KPI 30 menit yang
Dengan kata lain, pertanyaan mendasar adalah apakah tersebut benar-benar berbicara tentang teknologi? Dan apakah IKN memiliki kapabilitas untuk mewujudkannya? Jika kita ingin merancang IKN sebagai kota modern dengan infrastruktur maju, maka bagaimana dengan nilai-nilai budaya yang melandasi kota tersebut?
Contohnya, Jakarta sering dianggap sebagai kota modern, namun dalam praktiknya masih terjebak dalam tradisi yang ketinggalan zaman. Tidak ada perubahan yang signifikan. Namun, jika kita melirik Singapura, kita akan menemukan perubahan besar, disiplin, efisiensi, dan ketaatan pada aturan.
Pertanyaannya adalah, apakah jika kita memindahkan fokus ke IKN, kita dapat membentuk budaya-budaya baru yang diinginkan? Oleh karena itu, kegagalan utama dalam membangun IKN adalah jika kita mengulang kesalahan sebelumnya, yaitu merencanakan moda transportasi utama dengan mengutamakan pembangunan jalan, angkutan darat, atau kendaraan pribadi.
Jika IKN tidak berhasil membangun fondasi transportasi yang kokoh, seperti mengandalkan angkutan massal sebagai landasan utama, maka desain kota yang menjanjikan jarak tempuh 10 menit untuk mencapai halte dengan integrasi antarmoda yang merentang ke berbagai destinasi —inilah inti permasalahannya.
Proses pembangunan MRT dan LRT membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, tantangan menantangnya adalah ketersediaan pasokan dan permintaan. Membangun infrastruktur seperti kereta api, MRT, dan LRT memiliki biaya pembangunan yang mahal, dengan perkiraan mencapai Rp1 triliun per kilometer untuk LRT dan Rp500 miliar untuk MRT.
Meskipun secara operasional terdapat pasokan dan permintaan, namun IKN sebagai kota yang masih jarang dihuni menyiratkan risiko bahwa pemerintah mungkin harus menghadapi biaya operasional yang besar untuk menutupi beban transportasi yang sebanding.
IKN juga seharusnya menjadi kota yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang tersedia. Melainkan mampu mendaur berbagai kebutuhan guna keberlangsungan di masa depan.
Sebagai contoh, Singapura, negara yang luasnya tidak lebih besar dari Jakarta namun mampu mengelola keterbatasan SDA jadi keunggulan.
Caranya, Singapura telah berhasil mengelola sumber air dengan efisien, salah satunya dengan mengubah air limbah domestik menjadi air bersih yang memenuhi standar kesehatan WHO. Salah satu lokasi pengelolaan air bersih yang menonjol adalah NEWater Visitor Centre (NVC), yang terletak di Public Utilities Board, Scotts Road, Singapura.
Dalam usahanya untuk memastikan pasokan air lebih dari 2 juta meter kubik per hari, Singapura telah menerapkan pendekatan empat keran nasional atau "four national taps". Keempat metode ini mencakup pengumpulan air hujan secara lokal, impor air bersih dari Malaysia, daur ulang air dengan menggunakan teknologi NEWater, dan desalinasi atau pengolahan air laut yang dilakukan sejak tahun 2005.
Proses pengumpulan air hujan melibatkan saluran air seperti sungai, kanal, dan drainase, kemudian disimpan di 17 waduk yang saling terhubung oleh jaringan pipa untuk menjaga debit air. Air hujan tersebut mengalami tahap penyaringan untuk memastikan kebersihan, kesterilan, dan keamanannya sebelum didistribusikan kepada konsumen.
Sementara itu, pabrik pengolahan air laut menjadi air tawar telah beroperasi sejak 2005 melalui skema kemitraan publik atau Private Public Partnership. Singapura juga telah mengimpor air bersih dari Johor, Malaysia, sejak tahun 2011 hingga 2061.
Kita dapat mengambil banyak pelajaran dari Singapura, yang mampu memaksimalkan semua potensi di sekitar negara mereka sangat efisien, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Sebagai contoh, sekitar 60 persen dari kebutuhan air di Singapura diperoleh dari air hujan, sebuah pencapaian luar biasa. Oleh karena itu, penting bagi IKN untuk belajar dan menerapkan praktik serupa, mungkin dengan memanfaatkan area yang tidak terpakai, seperti kolong bekas tambang atau wilayah konsesi yang dapat direklamasi menjadi retention pond.
Langkah awal yang harus diambil adalah membangun infrastruktur dasar yang kuat agar kelak, ketika pembangunan kawasan sudah dimulai, keberlanjutan air menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan agar ketika fasilitas seperti kantor-kantor kementerian dibangun, pasokan air dapat dijamin tanpa kendala. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, kita dapat menghindari situasi di mana kita harus mencari sumber air dengan kesulitan, yang dapat menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan.
Untuk memastikan IKN menjadi kota berkelanjutan, penting untuk membuka rencana induk secara transparan. Salah satu aspek kunci yang harus diperhatikan adalah penggunaan energi dalam bangunan. Para perancang bangunan harus mengintegrasikan desain yang memungkinkan penggunaan energi seefisien mungkin, dengan setidaknya 60 persen berasal dari sumber energi alam.
Selain itu, pertimbangan lain melibatkan perubahan mikro iklim di kawasan IKN, seperti bagaimana suhu di kawasan ini dapat dikurangi untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sejuk.
Para perancang urban harus mempertimbangkan pilihan vegetasi yang sesuai, tidak hanya dari segi estetika, tetapi juga untuk mendukung ekosistem yang sehat tanpa merugikan makhluk lain. Semua ini harus menjadi fokus utama agar IKN bisa menjadi kota yang berkelanjutan dan berdaya tahan.
Semua yang dijelaskan di atas adalah satu dari sekian juta teori yang beranggapan bahwa IKN bisa mencapai tujuan bahkan lebih baik dari rancangan para pemimpin negara, dengan berbagai cara. Tapi, terlepas dari itu semua, kuncinya hanya satu, yaitu manusia yang merencanakan, membangun, dan hidup di dalamnya.
Kesimpulannya, sumber daya manusia adalah struktur utama sekaligus paling penting, karena sumber daya lainnya bisa bermanfaat tanpa menyakiti makhluk lain jika SDM IKN bertanggung jawab atas semua tugasnya, tanpa niat mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya.