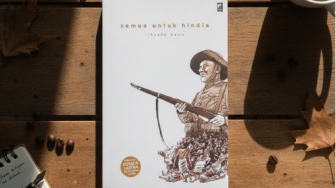Ada hal-hal dalam hidup yang begitu jelas, bahkan ketika dokumen resmi tidak pernah dibuat. Rumah yang terbakar, misalnya. Tidak perlu saksi mata atau surat keterangan untuk memahami bahwa tragedi itu benar-benar terjadi ketika puing-puing yang hangus dan bau asap masih tertinggal di udara.
Tetapi hari ini, ada kecenderungan aneh: kita diminta meragukan tragedi hanya karena negara tidak pernah menandatangani selembar kertas untuk mengakuinya.
Inilah yang terjadi ketika pernyataan Ribka Tjiptaning buru-buru dicap sebagai hoaks hanya karena “tidak ada putusan pengadilan” yang menyatakan Soeharto bersalah. Logika seperti ini, yang menyamakan ketiadaan putusan dengan ketiadaan peristiwa, adalah bentuk penyangkalan yang lembut namun mematikan.
Argumentum ad ignorantiam, sebuah kesesatan berpikir yang menganggap ketidaktahuan sebagai bukti.
Kita sering lupa bahwa sejarah tidak selalu lahir dari gedung pengadilan. Terkadang, ia justru lahir dari kegagalan sistem hukum untuk bekerja. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang seharusnya membuka ruang itu, dibatalkan bahkan sebelum sempat bekerja. Undang-undangnya cacat, tetapi pengingkaran terhadap fakta yang hendak ia ungkap jauh lebih fatal.
Sejak saat itu, kita memulai tradisi baru: mengukur kebenaran berdasarkan kelengkapan dokumen, bukan kekuatan bukti moral maupun historis.
Padahal, Komnas HAM telah menyampaikan laporan tebal pada 2012, memotret sembilan bentuk pelanggaran HAM pasca-1965. Angka korban yang mengerikan, setengah juta hingga jutaan jiwa, bukan sekadar statistik. Itu adalah jejak manusia, keluarga, dan kehidupan yang hilang.
Namun, dokumen resmi pun tidak punya kuasa ketika narasi yang dominan lebih memercayai kenyamanan daripada kenyataan.
Inilah tragedi sejarah kita: bukan karena masa lalu terlalu gelap, melainkan karena kebenaran yang setengah terbuka lebih menakutkan daripada kebohongan yang sudah mengakar.
Retorika yang Mengusik, Bukan Menyesatkan
Betul, retorika Ribka tidak rapi, bahkan mungkin kasar. Namun, dalam medan wacana yang sejak lama dikunci, retorika yang berlebihan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengetuk pintu yang tidak mau dibuka.
“Pembunuh jutaan rakyat” bukan laporan akademik; itu adalah metonimi, cara singkat untuk menunjuk struktur kekuasaan yang Soeharto pimpin selama 32 tahun.
Komnas HAM tidak pernah menyebut Soeharto sebagai pelaku tunggal, tetapi mereka menunjuk Kopkamtib sebagai institusi yang bertanggung jawab. Lantas, Kopkamtib berada di bawah komando siapa? Pertanyaan itu tidak memerlukan retorika tambahan.
Dalam hukum internasional, konsep command responsibility sudah jelas: seorang pemimpin bertanggung jawab atas tindak kejahatan bawahannya ketika ia tahu atau seharusnya tahu. Ini bukan perdebatan moral, melainkan standar hukum. Tidak ada negara yang memaafkan kapten kapal karena mengaku tidak memegang kemudi saat kapalnya tenggelam.
Selama puluhan tahun, narasi tentang 1965 dibentuk secara sistematis. Film diputar setiap tahun, buku-buku tertentu dilarang, dan suara korban dipinggirkan. Narasi semacam ini bukan sekadar propaganda; ia menjadi pengalaman kolektif. Maka, wajar jika suara tandingan dianggap sebagai ancaman.
Orang lebih suka tidur di bawah selimut mitos daripada bangun menghadapi udara dingin kebenaran. Namun, tidak ada bangsa yang maju dengan mematikan alarmnya sendiri.
Sejarah Bukan Ajang Sanitasi Moral
Dalam diskusi publik, pertanyaan tentang Soeharto selalu dibuat biner: apakah ia pahlawan atau pelanggar HAM? Seolah-olah sejarah hanya mengenal dua kotak. Padahal, hampir semua tokoh besar di dunia membawa jejak kebaikan dan keburukan sekaligus.
Kita boleh menghargai pembangunan jalan, tetapi bukan berarti kita harus menutup mata terhadap darah yang membasahi tanah tempat jalan itu dibangun.
Mencabut salah satu sisi bukan hanya pelecehan intelektual, tetapi juga kekerasan kedua terhadap para korban. Sejarah seharusnya dihormati, bukan dirias seperti foto keluarga yang hanya menampilkan senyum.
Rekonsiliasi sebagai Jalan Satu-satunya
Jika bangsa ini serius ingin sembuh, solusinya bukan saling melaporkan pendapat, bukan menuduh kritik sebagai ancaman, dan bukan merawat mitos demi kenyamanan emosional. Solusinya adalah menghidupkan kembali KKR dengan kesadaran bahwa keadilan bukan sekadar transaksi.
Kita butuh ruang resmi untuk mengungkap kebenaran, mendengar korban, mencatat kesalahan, dan mengakui luka. Tanpa itu, kita akan terus hidup dalam pola yang sama: masa lalu yang tidak selesai, masa kini yang rapuh, dan masa depan yang disandera oleh ketakutan.
Di ruang kelas, sejarah harus diajarkan bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai keberanian intelektual. Siswa harus diajak mempertanyakan, bukan sekadar mengulang. Karena bangsa yang dewasa bukanlah bangsa yang hafal sejarahnya, tetapi bangsa yang berani menatapnya.
Pada akhirnya, sejarah tidak menuntut kita untuk sempurna; ia hanya meminta kita untuk jujur. Kejujuran itulah yang paling sering menjadi korban pertama dari logika sesat.