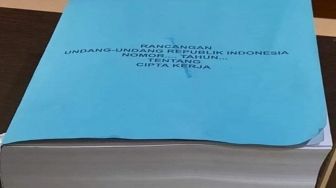News
Pajak Daerah di Indonesia: Antara Close List dan Open List System

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menemukan momentumnya pada masa reformasi, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan pintu gerbang reformasi di bidang birokrasi dan ekonomi. Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Alokasi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari desentralisasi sistem pemerintahan yang dipilih oleh pemerintah. Di mana dalam desentralisasi pemerintahan menghendaki adanya pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahan di daerah atau lokal untuk dapat mengelola sendiri sebagian urusannya.
Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otomatis akan diiringi dengan penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Oleh karenanya daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.
Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dalam skema pengelolaan pajak daerah di Indonesia, pengaturan induknya ada di tingkat undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Ini artinya, penetapan pajak berdasarkan undang-undang diselaraskan dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, pengaturan lebih lanjut dan lebih teknis mengenai pajak-pajak dan/atau pungutan lain akan diatur dengan undang-undang. Secara pemahaman otentik, konstitusi hanya menyebut kata “undang-undang”.
Hal ini bermakna bahwa timbulnya pajak-pajak dan/atau pungutan lain hanya boleh ditetapkan berdasarkan undang-undang saja, tidak boleh dengan peraturan lain. Ini sejalan dengan ungkapan terkenal dari Ricard Musgrave, "no taxation without representation", yang menyiratkan bahwa dalam negara demokrasi pemberlakuan pajak-pajak harus dengan seijin rakyat.
Adam Smith’s Canon telah memberikan panduan dalam menyusun perundang-undangan pajak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun undang-undang pajak, yaitu:
a. Syarat yuridis, syarat ini mengharuskan undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum dan keadilan di bawah prinsip equality dan equity.
b. Syarat ekonomis, pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dijadikan sebagai instrumen ekonomi negara yang harus dikelola secara hati-hati oleh pemerintah.
c. Syarat finansial, pajak dipungut untuk mengisi anggaran keuangan negara.
d. Syarat sosiologis, pajak adalah gejala sosial, hanya ada dalam masyarakat. Untuk itu pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat.
Sepanjang sejarah berlakunya pajak-pajak daerah di Indonesia, telah pernah dipraktikkan open list system maupun close list system secara bergantian. Apakah yang dimaksud dengan open list system dan close list system ini?
Open list system mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menetapkan dan memungut jenis pajak baru selain dari yang disebutkan oleh undang-undang bilamana diperlukan.
Sedangkan close list system bermakna sebaliknya, yakni pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Open list system memberikan kewenangan yang sangat besar dan luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan jenis pajak sesuai kondisi dan kemampuan daerahnya. Di satu sisi, sistem ini dapat lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun di sisi lain, sistem ini mengorbankan aspek kepastian hukum dan bisnis yang lebih luas.
Sementara close list system, akan membuat pemerintah daerah tampak kurang kreatif dan kemungkinan kehilangan peluang untuk berinovasi meningkatkan penerimaan daerahnya. Namun sistem ini memberikan kepastian hukum dan berusaha yang lebih besar karena ketundukannya kepada pemerintah pusat.
Pemerintah Indonesia tampaknya menyadari suatu paradigma besar dibalik euforia pemberian otonomi luas kepada daerah. Kesadaran ini adalah kepentingan nasional yang lebih besar harus lebih diutamakan daripada semangat kedaerahan yang cenderung partisan. Serta pada kenyataannya daerah-daerah tersebut eksis dan menyatu membentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini akan berarti bahwa apapun keadaan daerah-daerah itu akan merepresentasikan wajah Indonesia.
Kesadaran inilah yang menjadi spirit dari pemberlakuan UU PDRD, Undang-undang No. 28 Tahun 2009. UU PDRD dirancang sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pajak daerah di Indonesia. Undang-undang ini membatasi jenis-jenis pajak apa saja yang boleh berlaku di daerah otonom.
UU PDRD yang merombak prinsip-prinsip dalam ketentuan sebelumnya juga ingin memperluas objek pajak daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. UU PDRD menetapkan lima jenis pajak untuk propinsi dan 11 jenis pajak untuk kabupaten/ kota. Meningkat dari sebelumnya yang ada empat jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.
Namun, UU PDRD menutup sama sekali inovasi daerah untuk menambah sendiri jenis pajak yang baru. Dengan kata lain, pemerintah sekarang menerapkan close list system. UU hanya memberikan diskresi kepada daerah dalam hal menetapkan tarif pajak yang berlaku. Itupun dengan batasan ketat yang telah diatur oleh pemerintah.
Bahkan UU PDRD juga mengatur lebih lanjut detail substansi dan mekanisme pemungutan setiap jenis pajak daerah. Hal ini mudah dipahami mengingat aspek kepastian hukum dan harmonisasi berbagai pungutan di daerah harus menjadi prioritas dan tidak boleh menjadi faktor penghambat kegiatan ekonomi dan investasi di daerah yang notabene masih wilayah NKRI.
Pemerintah telah memperhitungkan dengan cermat perkembangan global dan posisi Indonesia saat ini. Sebagai negara yang sedang mengejar daya saing, Indonesia masih membutuhkan banyak investasi dari luar guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Oleh karena itu segala hal yang dapat menghambat masuknya investasi perlu dikurangi bahkan dihilangkan.
Salah satu dari hambatan investasi itu adalah kebijakan perpajakan yang berlaku. Penilaian dari investor luar mengenai faktor-faktor penentu kemudahan berusaha sekarang ini bukan lagi dilakukan dengan cara membandingkan negara per negara, tetapi sudah masuk sampai ke kota-kotanya. Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi di tingkat nasional tidak akan berarti apa-apa tanpa membenahi hambatan-hambatan yang ada di daerah.
Laporan Doing Business dari Bank Dunia (World Bank) mengenai profil ekonomi Indonesia tahun 2019 dan 2020 seolah mengonfirmasi argumentasi di atas. Disebutkan bahwa peringkat daya siang Indonesia dalam kemudahan bisnis tidak beranjak dari posisi 73 dari 190 negara.
Tetapi, perolehan skornya justru meningkat tipis dari 67,9 ke 69,6. Menariknya, aspek perpajakannya menunjukkan perbaikan peringkat, naik dari 112 menjadi 81 dari 190 negara. Tentu capaian ini tak terlepas dari upaya pemerintah dan segenap stakeholder yang telah bekerja keras memperbaiki regulasi dan sistem perpajakan, baik di pusat maupun daerah.
Dengan demikian apa yang ditetapkan oleh UU PDRD ini telah sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di mana kebijakan pajak daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia haruslah memperhatikan keseragaman, keselarasan, pembatasan, dan standardisasi baik dalam hal penentuan objek, subjek, wajib pajak, tarif dan dasar pengenaan pajaknya, serta dalam hal teknis pemungutan, pembayaran, pengawasan, pemberian sanksi, dan pemanfaatan/alokasinya.
Penulis: Tedy Iswahyudi, mahasiswa Program Pascasarjana Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, bekerja di Ditjen Pajak.
Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.
Komentar
Rekomendasi
Artikel Lainnya
Diskusi Geopolitik, UPN Veteran Jakarta Gelar Program Adjunct Professor Bersama Akademisi Malaysia
 Lintang Siltya Utami
Lintang Siltya Utami
Kerajinan Jogja Sukses Diekspor, Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi di Pasar Global
 Hikmawan Firdaus
Hikmawan Firdaus