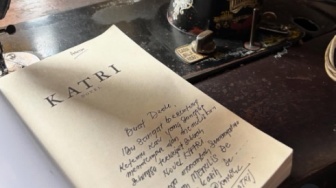Praktik Demokrasi di Indonesia telah memberikan banyak manfaat bagi sebagian besar rakyat di Indonesia. Jika dibandingkan dengan rezim otoritarian yang penuh dengan tekanan sosial dan politik, maka rezim demokrasi saat ini telah berkembang menuju kearah yang lebih baik.
Keterbukaan politik di era demokrasi telah memberikan kemerdekaan hidup bagi setiap warga negara, terbukanya ruang untuk berpartisipasi dalam bidang politik bagi publik, kekuasaan yang terkontrol dan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menikmati distribusi kesejahteraan secara adil.
Namun tumbuhnya demokrasi di Indonesia tersebut belum sepenuhnya selaras dengan asas keadilan sosial dan ekonomi, karena demokrasi kita tidak serta merta mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Ketidakmerataan kesejahteraan justru semakin meningkat pasca reformasi, yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks gini / koefisien gini pasca reformasi.
Indeks Gini Indonesia masa orde baru tidak pernah melebihi dari 0,37. Sementara kesenjangan ekonomi era demokrasi terus meningkat, dan bahkan pada 2020 telah mencapai angka 0,381. Lebih lanjut Indeks Gini Indonesia pada 2019 berada diangka 83,3 %. Jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dibawah USD 10.000 mencapai 82 %, dan hanya 1,1 % masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan diatas USD 100 ribu. Selain itu hanya 115 ribu orang Indonesia yang berada di top 1 % pemilik kekayaan dunia, jumlah yang sangat kecil untuk negara dengan total jumlah penduduknya mencapai 274 juta jiwa.
Melalui mekanisme Pemilu warga telah melimpahkan kewenangan yang besar pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat guna mewujudkan kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan yang diidam-idamkan tak kunjung datang, karena politik di Indonesia saat ini minus gagasan dan didominasi oleh pembentukan citra politik serta retorika dogmatis semata. Etika sebagai pejabat yang dibayar oleh pajak rakyat semakin tak bermoral. Hal terbaru adalah korupsi oleh Menteri Sosial Julian Batubara bersama dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dengan membentuk tim khusus untuk mengatur penunjukan vendor penyedia bantuan sosial Covid-19. Akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian hingga Rp 17 miliar, dan kerugian tak terhingga bagi para penerima bantuan sosial Covid-19 tersebut. Selain persoalan etika, politik Indonesia juga memiliki birokrasi yang sangat kaku, institusi politik formal yang didominasi oleh oligarki, maupun tidak seiringnya perjalanan antara aktor dengan sistem demokrasi. Padahal seharusnya gerak politik para elite tersebut harus bersandar pada upaya untuk menjawab permasalahan aktual.
Potret hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan warga secara mutakhir dipotret dalam buku Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus- Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal (2015). Buku ini memberikan gambaran dan hasil analisis mengenai praktik kontekstual upaya mewujudkan kesejahteraan sebagai isu politik dalam demokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal dan merangkainya ke tingkat nasional.
Buku ini hasil dari survei di 28 kabupaten/kota serta 2 daerah istimewa yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dan melibatkan 592 orang informan lokal dan 32 orang informan nasional. Penelitian ini menghasilkan temuan telah terjadinya dominasi oligarki pada praktik demokrasi awal pasca reformasi di mana demokrasi tidak benar-benar merepresentasikan keseluruhan lapisan masyarakat; representasi semu yang tidak mewakili minoritas, dan aktor-aktor pro-demokrasi yang terfragmentasi dan termarginalkan dari agenda demokratisasi.
Demokrasi sejauh ini dipahami hanya sebagai pengaturan metode untuk berkompetisi dan memperebutkan jabatan-jabatan politik (kepala negara, kepala daerah dll). Definisi ala Schumpeterian ini menyederhanakan makna dari sistem demokrasi hanya sebatas pada aspek elektoral.
Pemaknaan demokrasi ala Schumpeter ini memiliki keterbatasan, diantaranya : (1). Demokrasi hanya dimaknai sebagai arena kompetisi bagi para elit, sementara disisi lain publik tidak memiliki akses untuk mengontrol kekuasaan; (2). Definisi ini terlalu fokus pada institusi sebagai ukuran bekerjanya demokrasi, sementara prinsip dan tujuan yang ingin dicapai melalui sistem demokrasi cenderung terabaikan (Santoso, 2015).
Dari keterbatasan definisi tersebut, munculah tawaran definisi terkait demokrasi dari Beetham (1999). Menurutnya demokrasi adalah kontrol popular terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warga negara. Demokrasi menuntut adanya kontrol popular dari publik dan adanya persamaan hak setiap warga negara. Sehingga aspek terpenting dari demokrasi adalah menjamin agar masyarakat (publik) mampu melakukan kontrol atas setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Termasuk juga melakukan kontrol atas perilaku dan sikap dari para pembuat kebijakan tersebut. Kemampuan dari masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik tidak hanya bermakna adanya persamaan hak politik warga negara, tetapi juga menjadi penentu berjalannya demokrasi secara sehat.
Pemaknaan demokrasi sebagai kontrol publik dan persamaan politik akan mengarah pada pengelolaan kesejahteraan sebagai isu publik yang menjadi agenda besar pembuatan kebijakan di Indonesia. Namun nampaknya yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah demokrasi ala Schumpeterian, alih-alih demokrasi ala Beetham.
Hal ini semakin jelas dengan tidak pedulinya Presiden dan Wakil Presiden atas berbagai protes mahasiswa dalam menolak kebijakan-kebijakan yang tidak pro-publik. Dalam 2019-2020 saja terjadi protes dan penolakan dari masyarakat sipil terhadap serangkaian Undang-Undang kontroversial (UU KPK, UU Minerba, UU MK, UU Pertanahan dan UU Cipta Kerja). Catatan YLBHI dalam aksi unjuk rasa sepanjang 2019 terdapat 78 kasus pelanggaran yang menewaskan 51 orang, tetapi tidak sedikitpun mengubah keputusan pemerintah untuk menunda atau membatalkan UU tersebut.
Nampaknya tepat apa yang ditulis oleh Ben Bland dalam bukunya berjudul “Man of Contradictions: Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia” (2020). “Jokowi adalah seorang demokrat yang terjebak dalam otoritarianisme. Orientasi ekonominya liberal tapi praktiknya adalah proteksionisme. Dia mencitrakan diri sebagai rakyat, tapi dikelilingi elite. Jokowi terlihat menjunjung keberagaman, tapi dia berlindung di balik kelompok konservatif.”
Dalam menggambarkan Presiden Jokowi, Bland mengutip ungkapan Niccolo Machiavelli dalam buku The Prience, “it is much to be feared than loved.” Jokowi adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang ditakuti, sekaligus dicintai. Jokowi kerap dinilai sebagai orang yang diragukan kemampuannya. Tetapi disitulah keunggulan Jokowi, bahwa ekspektasi yang tidak berlebih menjadi nilai lebihnya. Kadang Jokowi dianggap sebagai “boneka” Megawati, kadang dia “menurunkan sedikit harga diri” demi merangkul Prabowo, oposisi yang kerap menjelek-jelekkannya ketika Pilpres.
Dengan dipilihnya Sandiaga Salahudin Uno menjadi Menteri dalam perombakan kabinet yang baru, menunjukkan bahwa tulisan Bland atas Presiden Jokowi mendekati kebenaran. Alih-alih kita berharap agar adanya kontrol popular dari publik atas setiap kebijakan pemerintah, bahkan kontrol dari kekuatan oposisi partai politik dalam sistem pemerintahan kitapun tak ada saat ini.
Dengan didukung oleh adanya 55 % pebisnis di DPR-RI, maka akan semakin mengukuhkan konsentrasi kekuasaan oligarki dalam setiap proses pembuatan kebijakan. di mana produk kebijakan tersebut akan menitikberatkan pada kepentingan ekonomi bisnis dan cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial, lingkungan serta partisipasi publik yang inklusif (Aidulsyah, dkk. 2020). Sehingga nampaknya kita harus menyambut tahun 2021 ini dengan sikap yang biasa-biasa saja, seperti yang sering diucapkan oleh Jokowi dan anak-anaknya. Karena negara saat ini sedang diurus dengan tidak serius.