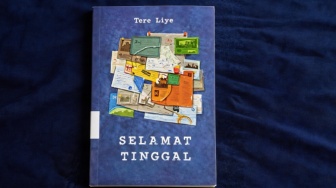Gaza kini menjadi potret paling kelam dari krisis kemanusiaan dunia. Sejak serangan militer Israel yang terus berlangsung, perang di wilayah itu bukan lagi sekadar konflik, melainkan berubah menjadi pemusnahan manusia.
Skala kehancuran yang kian masif bahkan kerap dianggap lumrah, seakan hanya bagian dari rangkaian konflik berdarah akibat sentimen etnis dan agama.
Bagi warga Gaza, penderitaan jauh lebih dalam dari sekadar dentuman bom. Blokade yang diterapkan Israel membuat kelaparan menjadi senjata. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua sambil menghirup asap beracun dari kilang terbakar.
Petani dipaksa mengolah tanah yang tercemar uranium, sementara air yang terkontaminasi bahan kimia menjadi sumber penyakit dan krisis yang berkepanjangan.

Namun di tengah tragedi ini, diskusi global soal iklim justru kian menyempit. Jargon “nol emisi” lebih sering dijadikan kampanye korporasi, sementara jejak karbon masif dari industri militer, termasuk agresi Israel di Gaza, hampir tak pernah disentuh.
Para pemimpin dunia gencar membicarakan ancaman pulau yang tenggelam, tetapi menutup mata terhadap bom dan tank yang membakar masa depan.
Isu ini semakin mencuat setelah Global Institute for Tomorrow menggelar konferensi bertajuk “Perang Melawan Iklim: Mengungkap Biaya Konflik yang Tak Terhitung.” Forum tersebut menyoroti bagaimana emisi dari aktivitas militer sengaja dikecualikan dari laporan resmi.
Seperti dikutip dari South China Morning Post, fenomena ini sejalan dengan meningkatnya anggaran pertahanan di berbagai negara. Alih-alih menuju perdamaian, dunia justru bersiap menghadapi konflik yang lebih besar. Situasi ini menegaskan kegagalan sistem global dalam menetapkan prioritas.
Sejarah juga menunjukkan celah yang dimanfaatkan negara-negara besar. Pada Protokol Kyoto, misalnya, Amerika Serikat bersikeras agar emisi militer tidak dihitung. Hasilnya, salah satu penyumbang karbon terbesar justru mendapat kelonggaran.
Bahkan di tingkat PBB, emisi militer sering dikategorikan sebagai “bahan bakar bunker,” sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Lebih ironis lagi, ketika satu negara mengebom negara lain—seperti yang kini dilakukan Israel di Gaza—beban emisinya justru ditanggung oleh korban, bukan pelaku agresi.
Angka resmi menyebut aktivitas militer menyumbang 6% emisi global, setara 2,53 miliar ton CO² per tahun. Namun publik justru digiring untuk merasa bersalah atas hal-hal kecil seperti penggunaan sedotan plastik—padahal dampaknya tidak sebanding dengan jejak karbon militer.
Dr. Soroush Abolfathi, panelis konferensi tersebut, menegaskan bahwa emisi terkait konflik sebenarnya bisa mencapai 15-20% dari total global, atau sepuluh kali lipat dari data resmi. Jika perhitungan ini benar, mustahil krisis iklim bisa diatasi tanpa menyentuh sektor militer.
Pada akhirnya, perdamaian dan keadilan iklim tidak bisa dipisahkan. Membicarakan “nol emisi” tanpa menghentikan perang ibarat menambal retakan kecil di dinding yang sudah runtuh. Sebab tak ada artinya dunia berjanji melindungi bumi, jika pada saat yang sama Israel dan negara lain terus memproduksi bom yang menghanguskan masa depan umat manusia.
Penulis: Muhammad Ryan Sabiti