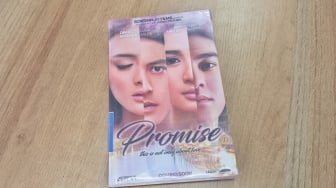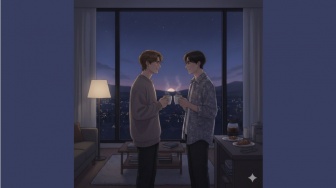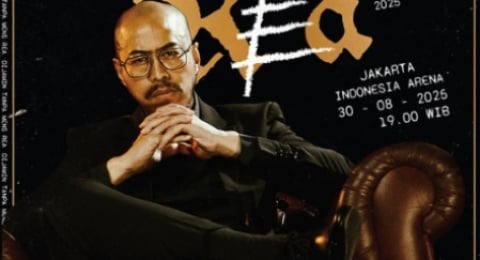Dulu, anak-anak sekolah menulis esai tentang pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia. Kini, para konglomerat menulis proposal konsesi agar hutan bisa jadi portofolio saham. Tak lagi cuma soal kayu atau getah, kini hutan disulap menjadi ladang karbon, lengkap dengan label "hijau" yang cocok untuk pajangan PowerPoint saat konferensi iklim.
Namun di balik layar presentasi itu, antrean panjang sudah mengular di lorong-lorong birokrasi kementerian. Data menyebutkan 152 perusahaan mengincar lahan seluas 4,82 juta hektare di 26 provinsi (EIA, 2025).
Ini bukan antre beli tiket Coldplay, ini antre rebutan oksigen untuk diperdagangkan. Bedanya, yang untung bukan masyarakat lokal, melainkan segelintir elite yang sudah kenyang makan kue pembangunan.
Skema “Perizinan Berbasis Persetujuan” atau PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang digadang-gadang sebagai terobosan pengelolaan hutan lestari, justru menyisakan banyak pertanyaan: di mana keterbukaan datanya?
Kenapa sosialisasinya lebih sering di hotel bintang lima daripada di kampung-kampung terdampak? Dan mengapa yang paling cepat dapat izin justru yang punya hubungan dengan politisi, pensiunan pejabat, atau konglomerat tua yang hafal cara menyisipkan amplop?
Di balik aroma pinus dan semangat konservasi, tampaknya ada aroma amis dari kapitalisme hijau yang sedang naik daun.
Antrean Panjang dan Prosedur yang Dibumbui Rahasia
Seperti antre minyak goreng saat pandemi, antrean konsesi kehutanan pun mengular. Tapi kali ini, yang mengantre bukan ibu-ibu membawa kantong kresek, melainkan perusahaan bersetelan jas yang membawa proposal proyek karbon.
Ada 152 perusahaan yang mengincar konsesi di 26 provinsi. Totalnya? Hampir lima juta hektare. Itu lebih luas dari gabungan Pulau Bali, Madura, dan Jakarta digabung jadi satu.
Namun yang lebih mencengangkan bukanlah luas lahannya, tapi ketertutupan prosesnya. Data publik nyaris nihil. Siapa yang mengajukan? Lahan mana saja? Apa evaluasinya? Semua gelap seperti hutan primer. Alih-alih audit publik, pemerintah malah mulai mengabulkan permohonan diam-diam, seperti sedang bagi-bagi warisan keluarga.
Menurut Hartati et al. (2024), perubahan regulasi lewat UU Cipta Kerja mempercepat perizinan investasi besar dan menyingkirkan elemen partisipasi masyarakat. Padahal ini bukan investasi biasa. Ini investasi yang menjanjikan laba dari karbon, sebuah komoditas yang tak terlihat, tapi bisa diukur dan diuangkan.
Dengan sistem begini, publik ibarat penonton dalam konser privat: tak tahu siapa mainnya, tapi tetap disuruh tepuk tangan.
Dari Surya Dumai hingga Sinar Mas—Semesta Konglomerasi PBPH
Kalau ada yang berpikir proyek karbon hanya diisi oleh startup idealis berisi anak muda pencinta lingkungan, maka mari kita kenalkan realitanya: konglomerat lama dengan nama-nama yang tidak asing di layar Forbes dan daftar Panama Papers.
Grup besar seperti Surya Dumai, Triputra, Integra, Harita, hingga Sinar Mas sudah mengantongi izin PBPH. Bahkan PT SHL dan SHE, yang menguasai lebih dari 140 ribu hektare hutan di Sorong, terhubung ke Angelia Bonaventure Sudirman—cucu dari pendiri Surya Dumai.
Kita bicara tentang wilayah yang katanya untuk jasa lingkungan, tapi malah dibagi dalam konsesi seperti celengan.
Bila bisnis zaman dulu membabat hutan untuk dijadikan sawit, bisnis zaman sekarang menjanjikan bahwa hutan yang "dibiarkan" itu akan menghasilkan uang—dari karbon.
Tapi jangan salah, mereka bukan tidak mengambil apa-apa. Mereka mengambil hak atas lahan, kontrol atas wilayah, dan otoritas untuk menentukan siapa yang boleh hidup di hutan itu.
Ini seperti seseorang yang bilang: “Saya tidak menyentuh nasi Anda,” tapi lalu ia duduk di meja Anda, menguasai sendok, dan menentukan kapan Anda boleh makan.
Simbiosis yang Tak Lagi Tersembunyi—Kekuasaan dan Korporasi
Kalau politik adalah seni kemungkinan, maka korporasi adalah seni kenalan. Salah satu contoh yang sudah tercium publik adalah Misran, mantan Sekretaris Dirjen PHL di Kementerian Kehutanan yang kini menjabat sebagai Direktur di PT SHL dan SHE. Dulu bikin aturan, sekarang main di lapangan. Lengkap!
Sosialisasi kepada masyarakat bukan dilakukan di balai desa, tapi di ballroom hotel. Penduduk lokal yang tinggal puluhan tahun di hutan-hutan Papua atau Aru bahkan tak tahu bahwa tanah mereka sedang dinegosiasikan di Jakarta sambil minum espresso dan kue sus.
Dugaan konflik kepentingan ini bukan hanya jadi asumsi. Penelitian Permadi et al. (2023) menunjukkan bahwa jaringan oligarki antara elite politik dan bisnis telah membatasi efektivitas advokasi masyarakat sipil. Regulasi yang mestinya melindungi rakyat, justru digunakan sebagai payung hukum bagi penguasaan.
Simbiosis ini begitu sempurna hingga membuat jamur tiram di hutan pun iri. Tapi beda dengan jamur, hubungan ini tidak bisa dimakan. Hanya menghasilkan kenyang untuk satu pihak, yaitu pemilik modal.
Kapitalisme Hijau dan Lahan Merah
Kita sering mendengar istilah "hijau itu indah." Tapi dalam konteks PBPH dan karbon, hijau bisa berarti “izin menguasai.” Skema perdagangan karbon dijual dengan narasi “sustainable development” alias pertumbuhan berkelanjutan. Tapi benarkah itu yang terjadi?
Sebagian besar izin diberikan di wilayah-wilayah sensitif: Papua, Aru, Kalimantan Tengah. Daerah yang kaya akan biodiversitas dan budaya. Namun sayangnya, pelibatan masyarakat adat nyaris tak ada. Mereka yang hidup berdampingan dengan hutan sejak nenek moyang justru jadi tamu tak diundang dalam pesta karbon ini.
Prakasa et al. (2022) mencatat bagaimana komunitas Laman Kinipan di Kalimantan Tengah menjadi korban perampasan tanah atas nama konservasi. Lahan mereka dialihfungsi tanpa persetujuan, dan saat mereka melawan, mereka dicap melawan pembangunan.
Ironisnya, nama programnya seringkali terdengar seperti iklan sabun: “Multiusaha Kehutanan untuk Masa Depan Cerah.” Padahal isinya adalah kombinasi eksploitasi lama: hutan tetap dikuasai elite, hanya kali ini dibungkus lebih cantik dan beraroma vanilla.
Karbon Dijual, Suara Adat Diredam
Kita hidup di zaman di mana polusi dijadikan komoditas, dan udara bersih dijual sebagai kemewahan. Kapitalisme hijau bukan semata tentang menjaga bumi, tapi lebih tentang siapa yang bisa menguasai “penjagaan” itu untuk dijadikan sumber laba.
Narasi konservasi yang mestinya berbasis komunitas justru dibajak oleh korporasi. Skema perdagangan karbon, jika tidak diawasi dan tidak transparan, akan menjadi monopoli baru yang lebih halus tapi tak kalah destruktif dari pembabatan hutan dengan chainsaw.
Apa yang kita butuhkan bukan hanya perizinan yang cepat, tapi tata kelola yang adil. Bukan hanya proyek berbasis emisi, tapi inisiatif berbasis hak masyarakat dan keberlanjutan sejati.
Karena jika semuanya dijadikan komoditas, maka kita hanya menunggu waktu sampai udara napas kita juga dimasukkan dalam portofolio bursa saham.