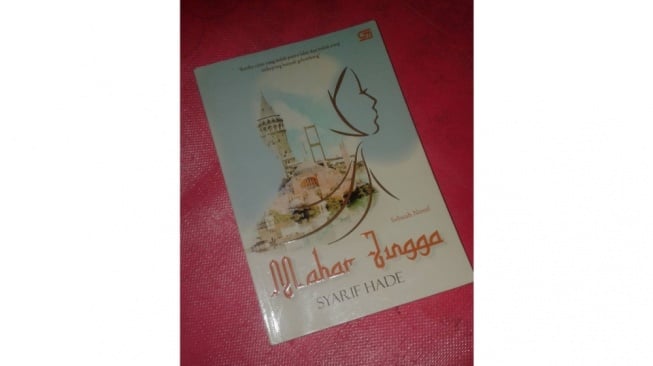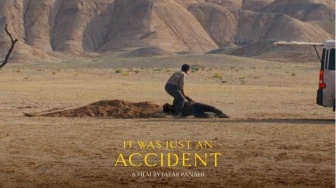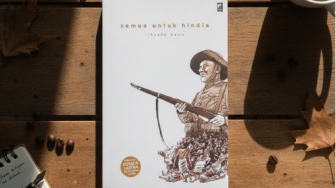"Apa gunanya cinta jika harus melukai yang lain? Dan apa arti halal jika hanya menjadi legalitas bagi luka yang tak pernah sembuh?”
Begitulah kira-kira gema yang tertinggal usai membaca novel Mahar Jingga karya Syarif Hade. Sebuah novel yang tak hanya membicarakan cinta, tetapi juga mengupas kompleksitas batin dalam hubungan yang dianggap sah menurut agama, namun belum tentu adil secara rasa.
Di tengah banyaknya novel bertema romansa yang memuja kebahagiaan bersama kekasih, Mahar Jingga justru hadir sebagai antitesis. Novel ini mengajak kita menyelami sisi lain cinta: cinta kedua, yang meskipun halal, bisa jadi membawa luka yang tak kalah dalam.
Nizam, Nadya, dan Sabria: Segitiga Cinta yang Tak Romantis
Tokoh utama novel ini adalah Nizam, seorang pria dewasa yang telah menikah dengan Sabria, istri setia yang membersamai sejak awal. Namun, hidup Nizam berubah ketika ia bertemu Nadya, perempuan cerdas, lembut, dan tampak ditakdirkan untuk mengisi ruang lain di hatinya.
Nizam menghadapi dilema besar: mengikuti bisikan cinta kedua yang katanya suci, atau bertahan dengan cinta lama yang sudah teruji. Ia tak ingin menjadi lelaki yang melukai. Namun ia juga tak bisa membohongi perasaannya. Maka, jalan yang ia pilih adalah poligami.
Namun apakah benar itu solusi?
Mahar Jingga: Simbol dari Cinta yang Goyah
Judul Mahar Jingga sendiri bukan sekadar estetika. Warna jingga digambarkan sebagai warna transisi—di antara kuning yang ragu dan merah yang membakar. Dalam konteks cerita, “mahar jingga” adalah simbol dari mahar kedua: mahar yang disampaikan bukan dari kelapangan jiwa, tapi dari perasaan yang belum utuh terbentuk.
Pernikahan kedua yang dilakukan Nizam ternyata tak seindah yang dibayangkan. Nadya pun bukan sekadar penerima cinta, tetapi perempuan yang akhirnya menanggung beban batin karena menyakiti perempuan lain. Dan Sabria? Ia adalah potret perempuan pertama yang tak diberi pilihan selain menerima atau terluka dalam diam.
Cinta Tak Cukup Sekadar Halal
Salah satu kekuatan novel ini adalah keberanian Syarif Hade untuk mengatakan hal yang jarang dibahas secara jujur: tidak semua yang halal membawa kebahagiaan. Terkadang, hukum boleh berkata "boleh", tapi hati manusia tidak sesederhana itu.
Novel ini tak menghakimi poligami. Justru sebaliknya, ia menyelami semua sisi: sisi lelaki yang mencinta tapi takut menyakiti, sisi perempuan yang ditinggal tapi tetap setia, dan sisi perempuan lain yang juga mencinta tapi merasa bersalah. Semua tokoh punya luka, dan pembaca diajak menyelami luka itu satu per satu.
Bahasa yang Reflektif, Puitis, dan Kadang Menghantui
Syarif Hade menulis dengan bahasa yang tidak biasa. Banyak bagian dalam novel ini terasa seperti doa, seperti monolog jiwa yang gelisah.
Gaya bahasa seperti ini membuat Mahar Jingga lebih dari sekadar cerita. Ia adalah refleksi, bahkan mungkin peringatan, bahwa cinta bukan sekadar perasaan yang saling dibalas—melainkan juga soal tanggung jawab dan keberanian menahan diri.
Bukan Kisah Cinta, Tapi Tafsir Kehidupan
Yang membuat Mahar Jingga layak dibaca bukan karena ia membuat kita baper, tapi karena ia membuat kita berpikir. Novel ini membuka ruang diskusi tentang:
Apa arti keadilan dalam cinta?
Bisakah kita mencintai dua orang tanpa menyakiti siapa pun?
Apakah syariat bisa menjadi pembenaran atas luka yang ditinggalkan?
Bagi perempuan, novel ini bisa menjadi ruang pengakuan. Bagi laki-laki, bisa menjadi cermin batin. Bagi siapa pun yang pernah merasakan cinta yang rumit, novel ini bisa terasa sangat dekat.
Penutup: Cinta Kedua Tak Selalu Harus Dimiliki
Membaca Mahar Jingga bukan pengalaman yang ringan. Tapi justru karena itu, ia meninggalkan bekas. Buku novel ini menyadarkan kita bahwa cinta sejati tak harus memiliki, dan niat baik pun bisa jadi racun bila tak disertai keikhlasan semua pihak.
Bila kamu sedang berada dalam dilema hubungan, atau ingin memahami cinta dari sisi yang lebih dalam, maka Mahar Jingga adalah bacaan yang tepat. Ia tidak menjawab semua pertanyaanmu—tapi setidaknya, ia akan menemanimu dalam proses bertanya.