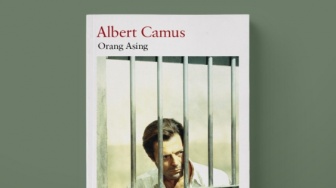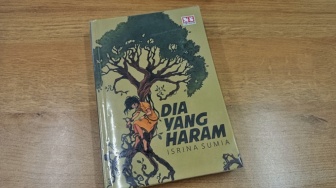Di tengah padatnya kehidupan urban, rasa kesepian dan kebutuhan akan ruang aman untuk bercerita masih menjadi masalah yang sering dialami banyak orang, termasuk di Yogyakarta.
Minimnya ruang yang benar-benar aman dan inklusif membuat banyak individu memendam cerita dan emosi sendirian.
Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, sebenarnya punya sisi lain berupa tekanan sosial dan isu kesehatan mental yang jarang diangkat.
Isu kesehatan mental di masyarakat, terutama Generasi Z yang jarang untuk membicarakan hal tersebut karena tidak punya ruang aman untuk berbicara atau takut dihakimi—sebenarnya sangat penting, namun tidak ada media untuk menampung isu tersebut.
Karena itulah, Menjadi Manusia punya beberapa kegiatan yang salah satunya adalah Open Mic. Open Mic sendiri membawa tema quarter life crisis, yang berdasarkan wawancara dengan Aji (PIC Teman Manusia Jogja), banyak anak muda yang sedang menghadapi fase quarter life crisis, dan mereka bingung untuk bercerita ke siapa atau bagaimana cara untuk menghadapi quarter life crisis itu sendiri.
Alasan banyak anak muda yang mengalami fase tersebut, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) karena adanya prevalensi gangguan jiwa berat di Yogyakarta yang meningkat dari 2,7‰ pada 2013 menjadi 9‰ pada 2018, di mana rentang usia 20 hingga 40 tahun yang termasuk kategori dewasa muda, adalah periode yang rentan mengalami stres.
Sementara itu, BBC mencatat bahwa dari 55.000 responden, menunjukkan bahwa kelompok usia 16–24 tahun justru merupakan kelompok yang paling sering merasa kesepian, meskipun mereka hidup di era digital yang tidak dibatasi oleh jarak.
Kebetulan, fase quarter life crisis tersebut relevan dengan Aji sendiri, sehingga ketika ada beberapa cerita peserta Open Mic yang senada dengannya, cara memenuhi ekspektasi keluarga atau aktivitas setelah lulus kuliah, ia merasa dikuatkan karena dirinya tidak sendirian dalam menghadap masalah tersebut.
“Seberat apapun masalahku, aku nggak sendiri menghadapi masalah-masalah itu,” ujar Aji.
Lalu, Aji menjelaskan bahwa lewat apresiasi dari peserta Open Mic berupa ucapan terima kasih sudah cukup untuk menunjukkan bahwa peserta merasa Teman Manusia Jogja adalah ruang aman bagi mereka untuk berbagi cerita.
“Karena jarang komunitas atau perusahaan yang menyediakan ruang seperti ini, karena hal-hal seperti ini basic-nya adalah psikolog atau konseling. Kalau ini, kita kemas dengan cara yang lebih ringan. Mereka lebih berterima kasih kayak, ‘Aku nggak sendirian, aku punya orang-orang yang menjadi support system kalau menghadapi hal-hal tertentu’,” jelas Aji.
Senada dengan Aji, Farhan (Sekretaris Teman Manusia Jogja) menyebut bahwa para peserta ternyata selain berbagi cerita, juga saling mencoba untuk menguatkan satu sama lain. “Mungkin yang satu ceritanya berat bagi dia, tapi yang satu lagi kan sudah melewati, jadi bisa saling membantu,” ujar Farhan. Bagas (Graphic Design dan Media Teman Manusia Jogja) juga menyebut hal yang sama. “Yang sampai dipaksa, didorong (untuk bercerita) gitu nggak ada sih. Ada yang awalnya memang diam saja, tapi akhirnya cerita. Mau nangis ya, nangis.”
Aji mengapresiasi para peserta yang berani datang dan bercerita, di mana ia akhirnya melihat adanya harapan baru lewat hadirnya ruang aman untuk bercerita bagi anak muda yang berkaitan dengan isu kesehatan mental.
Bagas menyampaikan bahwa semua orang berhak untuk mempunyai ruang dan menyampaikan keluh kesah mereka tanpa dihakimi. Berbeda dengan Aji dan Bagas, Farhan menyebut bahwa "mengobati" tidak harus dari obat atau psikolog, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu seperti memberi ruang aman untuk berbicara.
Dengan demikian, Teman Manusia Jogja berhasil meneguhkan posisinya sebagai komunitas kesehatan mental di Yogyakarta yang menyediakan tempat serta ruang aman bagi peserta untuk mengutarakan cerita-ceritanya.
Lewat Teman Manusia Jogja, kita mencoba untuk belajar memahami dan mendengarkan, bukan langsung menghakimi seseorang hanya karena ia tampak “berbeda”.