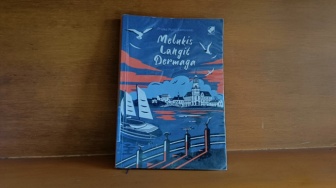Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang memaksa seorang penyandang disabilitas rungu dan wicara untuk berbicara. Hal itu dilakukan Risma saat pembukaan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kemensos, 1 Desember 2021 lalu. Saat itu, Risma berdialog dengan seorang anak Rungu Wicara bernama Aldi.
"Aldi, ini Ibu. Kamu sekarang harus bicara. Kamu bisa bicara, ibu paksa kamu untuk bicara… Kamu harus sampaikan ke Ibu apa pikiran kamu. Sekarang. Ibu minta kamu bicara enggak pakai alat. Kamu bisa bicara," kata Risma dalam dialog tersebut.
Tindakan Mensos Risma ini kemudian menuai kritik langsung dari penyandang disabilitas tunarungu bernama Stefan yang saat itu hadir pada peringatan tersebut.
"Ibu, saya harap (Anda) sudah mengetahui tentang CRPD. Bahwasannya, anak Tuli itu memang menggunakan alat bantu dengar, tetapi tidak untuk dipaksa berbicara," kata Stefan.
Kritik ini disampaikan karena tindakan Mensos Risma dinilai bertentangan dengan prinsip dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
UU Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 21 menegaskan bahwa negara harus membuat kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka.
Hal ini kemudian memantik pertanyaan publik, "Begitu susahkah pejabat kita memahami rakyat dari perspektif rakyat itu sendiri? Bagaimana negara bisa menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas jika pejabatnya saja tidak memiliki kesadaran moral dan pemahaman yang cukup mengenai disabilitas?"
Padahal, para penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini belum dapat mengakses sarana dan prasarana secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Monash University menemukan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buruk, peluang ekonomi yang lebih sedikit, dan akses yang lebih rendah ke layanan publik dibandingkan non-penyandang disabilitas.
Pada artikel ini, saya akan membahas dua langkah dasar yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Sebelumnya, mari kita telusuri seberapa banyak jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.
Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kelompok usia produktif menduduki presentase tertinggi penyandang disabilitas di Indonesia, sebesar 62,5 persen. Aksesibilitas penyandang disabilitas perlu segera ditingkatkan. Sebab, kelompok usia produktif ini jika dimaksimalkan potensinya akan bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Berikut merupakan langkah-langkah awal yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas:
Langkah pertama adalah dengan meningkatkan kompetensi profesionalisme pejabat publik yang terdiri dari kompetensi teknis, leadership, dan terutama kompetensi etika. Kompetensi teknis mencakup pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
Kompetensi leadership adalah kemampuan seorang individu untuk memengaruhi dan membimbing pengikut atau anggota lain dari suatu organisasi. Para pejabat publik juga harus menggunakan keterampilan manajemen untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat dan efisien. Hal yang paling penting, pejabat publik harus memiliki kompetensi etika.
Kekhawatiran atas perilaku tidak etis dari para pemimpin dan pejabat publik memaksa kita untuk membahas etika dan nilai-nilai pelayanan publik. Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan harapan masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas.
Untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat, seorang pejabat publik harus memiliki kesadaran moral yang tinggi. Bentuk dari kesadaran moral tersebut d iantaranya menyadari tanggung jawab yang diemban, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, menjamin hak-hak dasar individu dan kelompok, serta menjalankan amanah undang-undang.
Jika pemerintah berniat meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas, maka pejabat publik perlu menerapkan prinsip etika universal. Prinsip utama etika universal adalah prinsip keadilan, artinya kesamaan hak dan hormat kepada martabat manusia. Prinsip inilah yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan itu, pejabat publik akan memahami bagaimana memberikan keadilan akses bagi kelompok disabilitas.
Langkah kedua adalah dengan menanamkan nilai dan sikap penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas pada seluruh tingkat pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini sampai tingkat menengah atas. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan diskriminasi atas kelompok disabilitas.
Diskriminasi atas disabilitas terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang baik, atau tidak diberi kesempatan yang sama dengan orang lain dalam situasi yang sama, karena keadaan mereka. Seringkali, diskriminasi muncul karena tidak adanya pemahaman yang cukup.
Diskriminasi dapat berdampak pada aksesibilitas kelompok disabilitas, termasuk hak atas pendidikan. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pendidikan mereka. Program penanaman nilai dan sikap penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah sangat penting. Sebab, hal itu mendidik siswa agar menjadi warga negara yang lebih baik.
Program tersebut membuat anak-anak muda memiliki empati dan sikap positif. Itu menjadikan mereka warga negara yang lebih baik saat dewasa. Program penanaman nilai ini sesuai dengan pendapat Aristoteles terkait habitus. Pendapat ini menyatakan bahwa “Keutamaan diperoleh pertama kali oleh seseorang bukan melalui pengetahuan, melainkan melalui habitus, yaitu kebiasaan melakukan hal baik.”
Hari Disabilitas Internasional yang baru diperingati pada 3 Desember 2021 kemarin seharusnya dapat menjadi momentum yang tepat bagi semua pihak. Khususnya oleh pemerintah untuk menjamin aksesibilitas kelompok disabilitas.