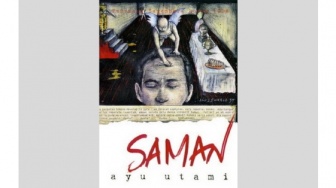Ki Hadjar Dewantara atau Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menyampaikan bahwa, “pengaruh pengajaran umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, sedang pendidikan memerdekakan hidup batinnya” (Ki Hadjar Dewantara, 1962).
Mari kita kita merenung sejenak, sudahkah kita menjadi manusia yang merdeka? Apakah pendidikan kita sudah sesuai dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara “Bapak Pendidikan Indonesia”?
Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1922 di Jogjakarta mendirikan Taman Siswa yang menjadi simbol perlawanan yang nyata. Taman Siswa bukan sekadar lembaga pendidikan, lebih dari itu adalah alat perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang menindas, elitis, dan diskriminatif.
Taman Siswa menjadi antitesa bagi semua sistem pendidikan kolonial. Taman Siswa tidak butuh restu untuk tegap berdiri dan melawan. Ki Hadjar Dewantara menghadirkan pendidikan tanpa syarat, dan tanpa kasta sebagai bentuk awal perlawanan.
Ia tidak ingin anak-anak hanya diajarkan membaca, menulis dan berhitung untuk kemudian menjadi pembantu pemerintah kolonial. Di sinilah gugatan itu mulai bergema.
“Daendels” dalam konteks ini adalah bentuk metafora dari sitem pendidikan kolonial. Dalam narasi bangsa Herman Willem Daendels adalah simbol kekuasaan kolonial yang otoriter.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, terkenal dengan proyek Jalan Raya Pos 1.000 Kilometer (Anyer-Panarukan) yang telah merengut ribuan nyawa.
Namun ada yang jauh lebih berbahaya, yaitu jalan pikiran yang dibangun “Daendels” kepada generasi-generasi setelahnya.
Pada masanya sekolah yang diberikan “Daendels” tidak bertujuan untuk mencerdaskan apalagi memerdekakan manusia. "Daendels" sejatinya hanya menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menjinakkan anak-anak pribumi.
Mereka tidak diajari bagaimana caranya berpikir kritis dan juga dijauhkan dari kondratnya yang natural.
Mari kita bertanya sekali lagi, apakah “Daendels” benar-benar telah mati? Atau justru “Daendels” masih hidup dalam rupa yang baru, lebih modern dan rapi?
Secara harfiah Daendels memang telah lama mati. Tetapi kita harus jujur, bahwa sistem pendidikan kita juga masih jauh dari apa yang menjadi cita-cita Ki Hadjar Dewantara.
Sistem pendidikan kita lebih terasa seperti sistem "ala kolonial".
Dewasa ini, pendidikan memang tidak lagi memandang kasta, namun dengan nyata kita masih bisa melihat ketimpangan. Orang-orang yang lebih mampu secara finansial akan mendapat akses yang lebih, dibanding dengan mereka para kaum marginal.
Selain itu, sistem lebih sibuk mencetak “angka” daripada membentuk “manusia”. Siswa belajar hanya untuk nilai, sementara guru lebih disibukkan oleh administrasi.
Dari kejadian itu, kita bisa melihat dengan jelas bayang-bayang “Daendels” dalam rupa yang baru. Dia bukan lagi pria Belanda yang memakai seragam militer, namun telah mewujud ke dalam sistem yang kaku dan sentralistis.
Kita telah kehilangan arah dalam membaca peta pikiran Ki Hadjar Dewantara.
Berbagai falsafahnya masih digunakan, dan digaungkan. Akan tetapi, pada praktiknya falsafah-falsafah itu telah kehilangan maknanya.
Falsafah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan menjadi teladan, di tengah meberi semangat, di belakang memberi dorongan) masih ramai dibicarakan di kelas-kelas. Namun, apakah benar jika kita sedang berusaha mewujudkannya?
Mengutip dari buku Pendidikan dan Kebudayaan karya Ki Hadjar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, dan/atau karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Oleh karena itulah, hal-hal di bawah ini harus diutamakan:
- Segala alat, usaha, dan cara pendidikan haruslah sesuai dengan kodratnya, atau keadaannya (natuurlijkheid, realiteit),
- Kodratnya keadaan itu tersimpan di dalam adat-istiadat setiap rakyat untuk mencapai hidup tertib-damai,
- Adat-istiadat sebagai peri kehidupan atau sifat pencampuran usaha dan daya upaya akan hidup tertib-damai tidak luput dari pengaruh zaman dan tempat,
- Untuk mengetahui “garis hidup” yang tetap dari suatu bangsa kita perlu belajar pada zaman yang telah lalu, menyelami zaman yang sedang dijalani hari ini, dan barulah kita bisa membayangkan zaman yang akan datang,
- Pengaruh baru diperoleh karena bercampurnya bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Pencampuran sekarang sangat mudah terjadi karena pengaruh hubungan modern. Akan tetapi, kita harus waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup, dan mana yang akan merugikan kita (Ki Hadjar Dewantara, 1962).
Bersama Taman Siswa, anak-anak didekatkan kepada kodratnya, bahasa ibunya, budayanya, sejarahnya dan bangsanya. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, tetapi juga diajarkan membaca keadaan.
Di sinilah Taman Siswa kembali menggugat “Daendels” yang dengan sengaja menjauhkan manusia dengan kondratnya, kehidupannya, dan penghidupannya.
Bersama Ki Hadjar Dewantara, Taman Siswa telah menjadi alat perjuangan kultural yang nyata. Berani berkata tidak terhadap sistem yang salah, serta berani menggugat pengekangan terhadap kemerdekaan setiap manusia.
Kini, sudah seratus tahun lebih sejak Taman Siswa berdiri, tetapi gugatan itu masih terus berlanjut.
Taman Siswa masih menggugat dan akan terus menggugat “Daendels” dan bayi-bayi bajangnya yang lahir dalam berbagai rupa bentuk.
Selama masih ada sistem yang timpang, dan membatasi manusia untuk berpikir bebas, maka Taman Siswa belum selesai dan tidak akan pernah selesai menggugat. Di kelas-kelas kecil, di pojok-pojok desa, di pinggiran-pinggiran kota, di setiap sudut Indonesia bisa menjadi bagian dari gugatan itu.
Taman Siswa mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan jalan menuju kekuasaan, melainkan jalan menuju kemerdekaan lahir dan batin.