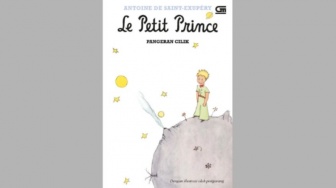Di era yang sama, pada dua daerah geografis yang berbeda, Ki Hadjar Dewantara dari Indonesia dan John Dewey dari Amerika Serikat, membangun fondasi penerapan pendidikan untuk menghadapi realitas sosial-politik masyarakat. Fondasi tersebut terbukti mampu bertahan oleh ujian zaman dan menjadi paradigma pendidikan yang berdampak luas bagi munculnya pemikiran dan praktik baik yang bermanfaat di masa sekarang.
Dewantara dan Dewey memang hidup pada periode sejarah dunia yang sama. Walaupun demikian, masyarakat lokal tempat mereka berada dalam suasana intelektual dan politik yang sangat berbeda. Dewey mengembangkan ide-ide progresifnya di lingkungan industrialis dan demokratis Amerika; sementara Dewantara memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat yang masih terjajah oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Kondisi sosial politik berbeda yang dihadapi oleh kedua tokoh justru menjadi menarik karena ada keselarasan ideologi dan filosofi pendidikan keduanya yang melampaui persamaan atau perbedaan latar belakang mereka.
Tinjauan Historis Latar Sosial Pendidikan
Masa kelahiran dan pertumbuhan John Dewey di Amerika Serikat merupakan periode emas perkembangan industri dan demokrasi modern. Negara yang baru saja selesai melewati perang saudara mulai menata kemajuan dengan mendorong inovasi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan publik meningkat. Secara bersamaan, pendidikan mengalami transformasi dari model klasik berbasis instruksi langsung menuju model yang lebih pragmatis melibatkan siswa.
Model pragmatis memberikan porsi lebih besar pada pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Peserta belajar dibentuk menjadi individu yang kritis dan inovatif. Dalam pandangan Dewey (2024), sekolah merupakan miniatur masyarakat demokratis. Di lingkungan sekolah, anak-anak belajar hidup bersama, menjunjung kesetaraan dan partisipatif (Shih, 2024). Kondisi ini akan menyiapkan anak-anak menjadi orang dewasa yang berguna dalam masyarakat demokratis (Festl, 2025).
Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara lahir di lingkungan bangsawan Jawa pada saat Hindia Belanda berkuasa. Lingkungan tumbuh Dewantara justru sangat kaku dalam menjalankan tradisi dan pendidikan sangat diskriminatif. Kesempatan pendidikan yang dikendalikan Hindia Belanda sangat elite dan tidak untuk semua kalangan masyarakat. Anak-anak Eropa dan kalangan bangsawan mendapat akses pendidikan, sedangkan rakyat jelata pada umumnya dibiarkan tetap tidak melek huruf.
Kondisi tidak melek huruf ini mempermudah proses menumbuhkan sikap dan tabiat menghamba. Tatanan sosial ini dibuat oleh Hindia Belanda agar tetap dapat menundukkan rakyat jelata dalam kuasanya. Dewantara melihat pendidikan sebagai alat pembebasan rakyat jelata dari penindasan dan penjajahan (Yusuf, 2024). Pendidikan yang merata dan memberikan teladan bukan hanya menghasilkan pribadi yang cerdas, tetapi juga dapat membangkitkan kesadaran kolektif untuk membebaskan dari keterbelakangan dan penjajahan (Dzul & Jamilah, 2024).
Persamaan Pemikiran Dewantara dan Dewey
Dewantara maupun Dewey sama-sama berpandangan bahwa pendidikan merupakan media penting untuk mendapatkan pengalaman dan pengembangan karakter. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan formal, tetapi harus menciptakan warga yang berpikir kritis dan bertanggung jawab secara sosial. Keduanya menolak sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pasif. Siswa harus didampingi untuk mengembangkan kecerdasan secara progresif dan berdaya dalam mengatasi masalah sehari-hari.
Dewantara memang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah demokrasi di dalam menjalankan ide besar pendidikannya. Namun, prinsip pendidikan yang dikembangkannya jelas menekankan peran pendidik sebagai pembimbing yang menuntun dan memberdayakan, bukan menggurui secara otoriter. Sebaliknya, Dewey secara jelas mengemukakan prinsip demokrasi akan tumbuh jika institusi pendidikan menjalankan fungsinya dengan memberikan siswa kebebasan berpikir dan otonomi dalam proses belajar.
Keduanya juga berpandangan bahwa pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Dewey menekankan pentingnya demokrasi sebagai kerangka pendidikan, sedangkan Dewantara memandang pendidikan sebagai alat perjuangan menuju kemerdekaan bangsa. Meskipun realitas sosial-politik yang mereka hadapi berbeda, keduanya percaya bahwa pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam perubahan sosial.
Reformis-Nasionalis vs. Liberalis-Progresif
Perbedaan mendasar antara Dewantara dan John Dewey terletak pada latar sosial-politik dan tujuan akhir pendidikan. John Dewey hidup dalam sistem negara yang demokratis, sehingga ia lebih menekankan penguatan karakter individu sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam sistem demokrasi liberal. Baginya, pendidikan adalah instrumen untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan kerja sama dalam komunitas yang egaliter.
Dewantara, pada sisi lain, hidup dalam suasana kolonialisme, di mana pendidikan digunakan sebagai alat penjajahan budaya dan politik. Jalan politik Dewantara jelas tidak bisa dilepaskan dari agenda perjuangan kebangsaan saat itu. Dewantara melihat pendidikan sebagai alat perlawanan dan kebangkitan nasional. Pendirian Taman Siswa olehnya bukan hanya sekedar formalisasi institusi pendidikan bagi rakyat; tempat pendidikan ini sekaligus merepresentasikan hakikat manusia yang merdeka, baik dalam berpikir maupun bertindak, sekaligus memiliki kesadaran nasional.
Jalan politik Dewantara lebih bersifat reformis dan nasionalis. Perjuangannya untuk perubahan sosial melalui pendidikan tetap berakar pada budaya lokal dan semangat kebangsaan. Sedangkan Dewey, sebagai liberalis progresif, lebih menekankan pentingnya adaptasi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat industri dan demokratis, di mana individu dihargai sebagai subjek otonom yang bebas.
Pentingnya Kajian Perbandingan untuk Pendidikan Indonesia
Analisis perbandingan antara pemikiran Dewantara dan Dewey penting sebagai kajian refleksi sejarah. Kajian ini juga memberikan sudut pandang kritis mengenai perancangan pendidikan yang tepat untuk Indonesia saat ini. Walau sudah merdeka, sebagian warga masih belum bisa mendapatkan pendidikan. Selain itu, ketidaksejahteraan pendidik berdampak besar terhadap pendidikan berkualitas.
Dari Dewey dan Dewantara kita bisa belajar bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak semestinya dilakukan dalam satu pola universal. Pendidikan tidak seharusnya hanya mengikuti dogma dan retorika pengambil kebijakan. Regulasi umum pendidikan memang penting. Tapi tidak kalah penting juga melibatkan pemangku pemerintahan lokal, pakar pendidikan lokal, dan masyarakat daerah untuk menentukan muatan-muatan di dalam pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Dengan melakukan perbandingan pemikiran kedua ahli pendidikan ini, kita dapat mengembangkan model pendidikan yang tetap terhubung dengan budaya lokal, sekaligus terbuka terhadap praktik pendidikan global yang menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpikir.