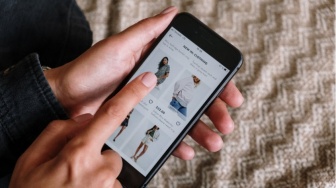Kolom
Jerit Politik Bangsa dari Jiwa Pendidikan yang Terluka

Sebagai seorang mahasiswi yang berjuang menempuh pendidikan sambil bekerja, saya merasakan betapa gema perjuangan Ki Hadjar Dewantara kini bagaikan seruan yang teredam. Ki Hadjar Dewantara, melalui Taman Siswa, pernah menyuarakan pendidikan sebagai jalan kemerdekaan jiwa, sekaligus fondasi politik bangsa yang berkeadilan.
Namun, di Indonesia akhir-akhir ini, pendidikan yang seharusnya memerdekakan justru menjadi beban berat bagi rakyat kecil seperti saya, sementara korupsi ratusan triliun merampas harapan jutaan orang. Refleksi atas perjuangan politik Ki Hadjar Dewantara dari kacamata seorang perempuan pejuang pendidikan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan jeritan untuk menantang bangsa yang seakan acuh terhadap penderitaan rakyatnya. Gema Dewantara harus dihidupkan kembali, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai nyala api yang membakar ketidakadilan.
Ki Hadjar Dewantara memimpikan pendidikan yang membebaskan, bukan yang memenjara. Konsep “among” yang ia gagas menekankan pendidikan sebagai sarana membentuk kesadaran kritis dan karakter bangsa. Dalam politik, ia melawan penjajahan dengan menanamkan nasionalisme melalui tulisan dan organisasi seperti Indische Partij.
Namun, kini saya, seorang mahasiswi, harus berjuang membayar biaya kuliah yang melonjak, bekerja hingga larut malam, sementara pejabat koruptor yang mencuri ratusan triliun hanya dihukum dengan pertimbangan keadilan yang kurang memuaskan. Ketimpangan ini adalah pengkhianatan terhadap visi Ki Hadjar Dewantara. Korupsi telah merusak sendi pendidikan dan politik bangsa, meninggalkan rakyat seperti saya dalam jerat kemiskinan dan ketidakadilan. Gema perjuangannya menyeru kita untuk melawan, bukan dengan diam, tetapi dengan kesadaran politik yang tajam.
Pendidikan yang layak, yang seharusnya menjadi hak setiap warga, kini menjadi barang mahal. Saya menyaksikan beberapa teman ada yang putus kuliah karena tak mampu membayar UKT, sementara kasus korupsi seperti timah maupun bahan bakar minyak telah merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah.
Hukuman bagi koruptor, yang sering kali hanya beberapa tahun penjara, adalah tamparan bagi rakyat yang berjuang demi secercah harapan melalui pendidikan. Ki Hadjar Dewantara pernah mengajarkan bahwa pendidikan adalah jiwa politik bangsa, tetapi jiwa itu kini terluka oleh sistem yang memanjakan pelaku korupsi. Problematika ini menunjukkan bahwa pendidikan politik rakyat, yang dulu digaungkan Ki Hadjar Dewantara, telah dikhianati. Kita butuh pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membangkitkan keberanian untuk menuntut keadilan.
Politik inklusif Ki Hadjar Dewantara, yang merangkul keberagaman budaya dan memperjuangkan kesetaraan, kini terkubur di bawah puing-puing polarisasi dan pragmatisme. Sebagai perempuan, saya merasakan lapisan ketidakadilan yang lebih berat: beban finansial, stigma sosial, dan minimnya representasi perempuan dalam politik.
Sementara itu, elit politik sibuk memainkan narasi identitas untuk memecah belah rakyat, alih-alih menyelesaikan krisis pendidikan dan korupsi. Gema Dewantara, yang menyerukan persatuan melalui pendidikan, menantang kita untuk menghidupkan kembali politik yang berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan. Pendidikan politik yang inklusif, yang memberi ruang bagi suara perempuan dan kelompok marginal, harus menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan sistemik.
Apatisme politik yang melanda masyarakat adalah luka lain yang memperparah penderitaan bangsa. Ki Hadjar Dewantara melalui Taman Siswa mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk rakyat kecil, memiliki peran dalam politik bangsa.
Namun, ketika saya melihat teman-teman saya yang kehilangan harapan, memandang politik sebagai ranah kotor yang tak relevan dengan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa percaya, ketika koruptor hidup mewah sementara kami berjuang untuk bertahan?
Ketidakpercayaan ini adalah akibat dari pendidikan politik yang gagal, yang tidak lagi mencerminkan semangat Ki Hadjar Dewantara. Gema perjuangannya menuntut kita untuk membangun pendidikan kewarganegaraan yang membumi, yang mengajarkan rakyat untuk berani menuntut pertanggungjawaban dan melawan ketidakadilan.
Tantangan terbesar adalah mengubah kemarahan menjadi aksi. Gema Ki Hadjar Dewantara bukan sekadar seruan nostalgia, tetapi panggilan untuk bertindak. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan memperberat hukuman koruptor, memastikan transparansi anggaran, perampasan aset, dan menjadikan pendidikan terjangkau sebagai prioritas.
Kami, mahasiswa, juga harus bangkit, menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengorganisir gerakan melawan korupsi dan ketidakadilan. Komunitas akademik, bersama masyarakat sipil, perlu menghidupkan kembali dialog kritis yang menggugat sistem. Gema Dewantara mengajak kita untuk tidak menyerah, tetapi untuk menjadikan pendidikan sebagai senjata politik yang tajam, yang mampu mengiris habis ketidakadilan dan membangun bangsa yang lebih adil.
Terakhir, gema Ki Hadjar Dewantara adalah jeritan saya, seorang mahasiswi yang lelah dengan ketidakadilan, namun tetap percaya pada kekuatan pendidikan. Korupsi yang merajalela dan pendidikan yang kian mahal adalah pengkhianatan terhadap visi Ki Hadjar Dewantara, tetapi gema perjuangannya adalah harapan yang tak padam.
Marilah kita, rakyat kecil, mahasiswa, dan perempuan, menghidupkan kembali semangat Dewantara dengan menjadikan pendidikan sebagai jiwa politik bangsa. Dengan keberanian, kesadaran kritis, dan aksi nyata, kita dapat mengubah jerit penderitaan menjadi nyanyian kemenangan, menuju Indonesia yang adil, merdeka, dan tercerahkan.