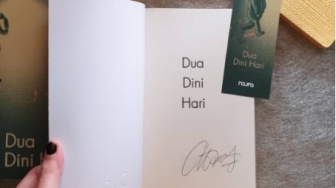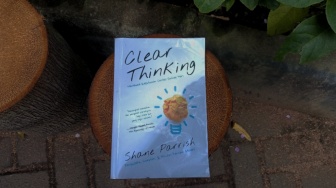Banyak orang bicara pendidikan hari ini yang asyik membahas kurikulum, digitalisasi, dan kecerdasan buatan. Lupa untuk menoleh ke belakang untuk melihat akar sejarah pendidikan kita yang masih sangat relevan untuk dipelajari. Dengan sedikit menoleh ke belakang dan menanyakan, pendidikan seperti apa yang pernah dibayangkan untuk bangsa ini?
Renungan tadi akan mengantarkan kita menemukan sosok yang dibuang oleh Belanda karena tulisannya berjudul "Seandainya Saya Orang Belanda." Hingga ia pulang ke Yogyakarta setelah dibuang Belanda, lalu mendirikan sistem pendidikan dengan skema kesetaraan bernama Taman Siswa. Sosok itu bernama Ki Hadjar Dewantara, bukan hanya guru, tetapi juga pemikir dan pejuang kelas.
Dua Napas Satu Tubuh
Ki Hadjar Dewantara adalah simpul penting dari gerakan buruh dan pendidikan. Ia bukan sekadar pendiri Taman Siswa, ia juga seorang penerjemah lagu yang dinyanyikan buruh internasional berjudul "Internasionale" ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1920 yang dipublikasikan oleh koran harian Sinar Hindia dengan nama Soewardi Soeryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara.
Ia adalah seorang yang sangat peduli pada ruang kesetaraan dan kebebasan. Kepedulian itu menjadi simpul penting dalam sejarah bangsa kita. Bagaimana Ki Hadjar Dewantara melepas mahkota ia sebagai ningrat dari Keraton Paku Alaman, untuk mengajari bangsa tentang kesetaraan dan kebebasan, hingga merubah namanya dari Raden Mas Soewardi Soeryaningrat menjadi Ki Hadjar Dewantara pada saat mendirikan Taman Siswa.
Ia seorang pendidik dengan dua napas kehidupan, yaitu gerakan dan pengabdian pendidikan. Menjadi refleksi penting untuk guru dan para pejuang gerakan agar tidak anti pada dua elemen ini karena saling mendukung satu sama lain. Ki Hadjar memandang bahwa pendidikan menjadi instrumen penting dalam melakukan pergerakan agar bisa mengurai sekema-sekema konkret pada ruang kesetaraan dan keadilan.
Guru hari ini harus bisa mencontoh pada sikap yang diajarkan oleh bapak pendidikan kita, bagaimana ia melakukan pendidikan yang bukan sekadar ruang seremonial, tetapi lebih pada ruang esensial dalam membangun pendidikan untuk memperjuangkan kesadaran rakyat untuk membebaskan dari ruang ketertindasan pada saat itu.
Guru hari ini juga harus berani melepas mahkota feodalisme yang hadir dan melekat pada sistem pendidikan kita yang masih tercermin dari perilaku bahwa guru dianggap sebagai pemilik otoritas sepenuhnya dalam ruang kelas. Persepsi pembebasan yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara harus kembali disyiarkan dalam ruang kelas bahwa guru adalah fasilitator keilmuan, bukan sumber kebenaran.
Tri Pusat dan Sistem Among, Masihkah Kita Mengamalkannya?
Ki Hadjar telah merumuskan sistem pendidikan yang masih sangat relevan sampai hari ini, yaitu sistem Tri Pusat. Sistem ini membawa konsep tiga alam siswa yang harus ditopang, yaitu:
- Alam Rumah: Menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pendidik di rumah dengan fungsi memperkuat keimanan, norma, dan etika.
- Alam Sekolah: Bertanggung jawab guru sebagai fasilitator untuk menumbuhkan pengetahuan siswa pada ruang-ruang keilmuan dengan sistem yang demokratis. Guru bukan sipir penjara yang merasa semua kebenaran adalah miliknya. Otoritas kebenaran dalam kelas dibangun secara bersama melalui ruang diskusi.
- Alam Masyarakat: Ki Hadjar memandang organisasi sebagai instrumen penting bagi siswa untuk melakukan aktualisasi hasil pendidikan di alam pertama dan kedua, yang output-nya adalah kebermanfaatan di lingkungan masyarakat.
Yang menarik, Ki Hadjar memiliki konsep guru dengan nama sistem among, di mana guru sebagai fasilitator pengetahuan. Ia memandang guru bukan seorang yang pasti benar, maka ia harus sadar posisinya dalam ruang kelas sebagai tenaga yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Guru bukan penyiar kebenaran satu arah dan anti kritik siswa.
Pada konsep yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara, mari kita merenungkan bersama, apakah sistem semenarik dan relevan ini masih diamalkan? Konsep pendidikan yang memberikan banyak ruang aktualisasi pada siswa dan berfokus pada pengembangan keilmuan dan minat siswa ini, masihkah menjadi landasan pendidikan kita?
Jangan terlalu fokus mengkaji sistem luar, sedangkan bapak bangsa kita telah mencetuskan gagasan pendidikan berbasis karakteristik kebangsaan kita. Bukankah ini lebih relevan dibanding menggunakan sistem luar negeri hasil studi banding ratusan miliar tiap tahunnya?
Dua Hari Satu Makna
Ada hal menarik di mana Hari Pendidikan dan Hari Buruh bersebelahan secara tanggal, yaitu 1 Mei untuk Hari Buruh dan 2 Mei untuk Hari Pendidikan. Keduanya berdekatan hingga menyiratkan makna akan cita-cita Ki Hadjar Dewantara tentang keberpihakan pendidikan pada kelompok tertindas.
Pendidikan sebagai alat melepas belenggu dari kebodohan, feodalisme, dan keterjajahan. Bagi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah simpul penting dari ruang kebebasan. Tanggal yang berdekatan membawa makna tentang tujuan pendidikan untuk harapan pembebasan.
Apakah guru saat ini memaknai hari itu dengan makna yang sama, tentang konsep pendidikan yang membebaskan siswa dari rasa takut akan cita-cita dan harapan untuk meneruskan tongkat sejarah bangsa?
Relevansi Sosialisme Humanistik ala Ki Hadjar
Ki Hadjar Dewantara setelah menerjemahkan lagu "Internasionale" banyak yang beranggapan bahwa dia adalah seorang ekstremis kiri. Padahal ia bukan bagian dari gerakan itu. Ia adalah seorang sosialisme kultural yang tidak suka penindasan pada kelompok mana pun. Sosialisme ala Ki Hadjar sangat konseptual, membawa nilai-nilai lokal yang melekat: anti keterjajahan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Narasi ini sudah jarang dibawa oleh banyak orang hari ini. Mereka melihat bahwa argumentasi Ki Hadjar seakan tidak relevan. Bahkan, kampanye tentang andil seorang guru dalam mewariskan nilai tentang konstruksi ruang gerak sosial hampir jarang dilakukan. Guru hari ini hanya fokus pada persiapan kerja, tetapi luput memupuk harapan sosial pada siswa.