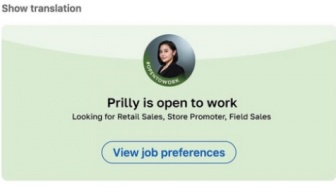Hiruk pikuk akhir tahun ajaran sekolah kembali terasa. Bukan hanya karena pembagian rapor dan persiapan libur panjang, tetapi juga karena tradisi wisuda yang kian meriah di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat.
Ironisnya, kemeriahan ini sering kali berbanding terbalik dengan esensi pendidikan itu sendiri, bahkan tak jarang membebani kantong orang tua murid dengan biaya yang tak sedikit, setara atau bahkan melebihi biaya wisuda di tingkat perguruan tinggi. Pertanyaan mendasar pun muncul: masih relevankah tradisi wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah ini?
Tentu, tidak ada yang salah dengan merayakan pencapaian. Menyelesaikan satu jenjang pendidikan adalah momen penting yang patut diapresiasi.
Wisuda, dalam konteks idealnya, adalah seremoni yang memberikan pengakuan atas kerja keras siswa, dukungan guru, dan pengorbanan orang tua. Namun, realitas di lapangan sering kali jauh dari ideal.
Wisuda sekolah dasar dan menengah kini bertransformasi menjadi ajang unjuk kemewahan. Gaun dan jas yang disewa atau dibeli dengan harga selangit, riasan wajah profesional, hingga biaya gedung dan dekorasi yang fantastis, semuanya seolah menjadi standar yang tak tertulis.
Akibatnya, orang tua murid, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, harus merogoh kocek dalam-dalam.
Biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak yang lebih esensial, seperti buku pelajaran, les tambahan, atau bahkan tabungan untuk jenjang pendidikan selanjutnya, justru tersedot untuk sebuah seremoni yang manfaatnya dipertanyakan.
Tak jarang, orang tua terpaksa berutang atau menahan kebutuhan lain demi memenuhi gengsi agar anaknya tidak merasa berbeda dari teman-temannya.
Lebih jauh lagi, esensi wisuda sebagai momen refleksi dan apresiasi seringkali tergerus oleh kemeriahan semata. Fokus bergeser dari pencapaian akademik dan perkembangan karakter siswa menjadi pesta perpisahan yang glamor.
Anak-anak, yang seharusnya menjadi bintang utama, terkadang hanya menjadi figuran dalam acara yang lebih menonjolkan aspek hiburan dan visual.
Lantas, apakah wisuda di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA benar-benar krusial? Tentu, perayaan kelulusan bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan bermakna.
Acara pentas seni yang menampilkan bakat siswa, kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian, atau sekadar acara perpisahan sederhana di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh siswa dan guru, bisa menjadi alternatif yang lebih mendidik dan tidak memberatkan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2023 mengeluarkan imbauan penting terkait kegiatan wisuda di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.
Surat edaran yang ditujukan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta kepala satuan pendidikan ini menekankan bahwa wisuda tidak boleh menjadi kewajiban bagi siswa dan orang tua, serta melarang adanya pungutan biaya yang memberatkan.
Esensi kelulusan ditekankan pada pengakuan penyelesaian belajar dan penyerahan kembali siswa kepada orang tua, bukan pada seremoni mewah.
Sebagai alternatif, Kemendikbudristek mendorong sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan akhir tahun yang lebih sederhana, bermakna, dan melibatkan seluruh siswa, seperti pentas seni, pameran karya, atau acara perpisahan di lingkungan sekolah.
Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan sekolah melalui musyawarah dengan komite dan orang tua, arah kebijakan ini jelas mengarah pada pengurangan praktik wisuda berbiaya tinggi.
Dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan wisuda agar tidak memberatkan orang tua murid.
Polemik mengenai urgensi wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah semakin mengemuka, bahkan merambah ke ranah perdebatan publik yang lebih luas.
Kasus viral seorang remaja putri, Aura Cinta, lulusan SMA di Bekasi, yang sebelumnya dikenal karena kritiknya terhadap proyek penggusuran, turut menyumbangkan perspektif menarik.
Kekecewannya terhadap ditiadakannya acara wisuda di sekolahnya, yang ia sampaikan melalui video, mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi.
Aura Cinta menyebut bahwa tidak semua orang dapat mencicipi jenjang pendidikan tinggi dan merasakan wisuda selepas kuliah sehingga wisuda di jenjang sekolah ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa, meskipun biaya yang harus ditanggung terbilang cukup besar bagi kalangan menengah ke bawah.
Namun, Dedi Mulyadi memberikan sudut pandang yang berbeda, terutama dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat penggusuran. Ia mempertanyakan prioritas pengeluaran untuk acara seremonial semacam wisuda dibandingkan dengan kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, papan, dan bahkan tabungan pendidikan.
Pandangan Dedi Mulyadi ini sejalan dengan imbauan Kemendikbudristek yang menekankan kesederhanaan dan menghindari pembebanan biaya wisuda kepada orang tua.
Argumennya menyoroti sebuah pertanyaan mendasar: di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat, apakah perayaan kelulusan yang mewah di setiap jenjang pendidikan merupakan prioritas yang tepat?
Jika setiap jenjang, mulai dari TK hingga SMA, menyelenggarakan wisuda dengan format yang cenderung glamor dan mahal, akumulasi biaya yang harus ditanggung orang tua bisa menjadi sangat signifikan, terutama bagi keluarga dengan lebih dari satu anak atau mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.
Lebih lanjut, perdebatan ini menyentuh isu kesenjangan sosial. Ketika wisuda dipaksakan menjadi ajang unjuk kemewahan, anak-anak dari keluarga kurang mampu berpotensi merasa terpinggirkan dan malu karena keterbatasan ekonomi orang tua mereka.
Momentum yang seharusnya menjadi perayaan kebersamaan dan pencapaian justru bisa menjadi sumber kecemasan dan perbandingan sosial yang tidak sehat. Hal ini mengikis nilai inklusivitas dalam pendidikan, di mana seharusnya setiap siswa merasa dihargai atas proses belajarnya, bukan atas kemampuan finansial keluarganya dalam membiayai seremoni.
Oleh karena itu, wacana mengenai urgensi wisuda TK-SMA bukan sekadar persoalan tradisi atau perayaan semata, melainkan juga menyentuh isu prioritas anggaran keluarga, kesenjangan sosial, dan esensi dari makna kelulusan itu sendiri.
Imbauan dari Kemendikbudristek dan perspektif yang disampaikan oleh tokoh publik seperti Dedi Mulyadi menjadi pengingat penting bagi sekolah, komite sekolah, dan orang tua untuk bersama-sama merenungkan kembali format perayaan kelulusan yang lebih bijaksana, adil, dan berfokus pada pencapaian pendidikan yang sesungguhnya.
Mengedepankan kreativitas, kebersamaan, dan nilai-nilai pendidikan akan jauh lebih bermakna daripada sekadar mengikuti arus kemewahan yang berpotensi menggores prioritas yang lebih esensial.
Menimbang berbagai perspektif dan imbauan yang ada, sudah saatnya kita menggeser fokus perayaan kelulusan di jenjang TK hingga SMA dari kemewahan seremonial menuju esensi penghargaan terhadap proses belajar dan pencapaian siswa.
Prioritas anggaran keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang beragam, hendaknya menjadi pertimbangan utama.
Alih-alih terjebak dalam tradisi yang berpotensi membebani dan menciptakan kesenjangan sosial, sekolah dan orang tua perlu berkolaborasi menciptakan alternatif perayaan yang lebih sederhana, inklusif, dan bermakna, sehingga momen kelulusan benar-benar menjadi tonggak kebahagiaan dan kebersamaan tanpa mengorbankan kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih mendasar.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS