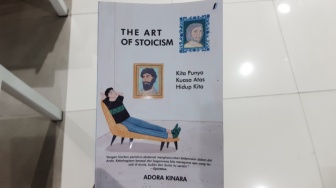Pernahkah kamu mengamati mengapa anak muda zaman sekarang, khususnya Gen Z tampaknya lebih sering mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau burnout?
Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat atau isu yang dilebih-lebihkan, melainkan cerminan dari kompleksitas hidup di era modern yang mereka alami.
Generasi Z adalah digital native sejati. Mereka tumbuh besar dengan internet, smartphone, dan media sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka.
Meskipun dunia digital membawa banyak manfaat luar biasa, seperti kemudahan akses informasi dan konektivitas global, media sosial juga menciptakan tekanan yang luar biasa dan seringkali tak terlihat.
Kita bicara tentang perbandingan sosial yang tiada henti. Bayangkan, setiap kali mereka membuka media sosial, mereka langsung dihadapkan pada kehidupan sempurna orang lain, pencapaian karier yang fantastis, hubungan romantis yang ideal, liburan mewah di tempat-tempat indah, dan penampilan fisik yang selalu tampak sempurna.
Mereka terus-menerus terpapar pada highlight kehidupan orang lain, yang secara tidak sadar memicu perasaan tidak cukup, iri hati, dan rendah diri. Ada beban psikologis yang berat karena merasa tertinggal atau kurang dibandingkan teman sebaya.
Kemudian ada fenomena Fear of Missing Out atau FOMO. Ini adalah kecemasan akan ketinggalan informasi penting, event sosial, atau momen-momen seru yang dipicu oleh melihat aktivitas teman-teman di media sosial. Hal ini bisa membuat Gen Z merasa wajib untuk selalu terhubung dan terlibat, bahkan ketika mereka seharusnya beristirahat, fokus pada pekerjaan, atau memberikan waktu untuk diri sendiri.
Akibatnya, mereka kesulitan untuk benar-benar lepas dan mengisi ulang energi. Lingkungan media sosial yang memakai akun anonim atau semi-anonim juga menjadi sarang bagi cyberbullying.
Paparan terhadap ujaran kebencian, komentar negatif, atau body shaming juga dapat sangat merusak kesehatan mental, terutama di usia rentan di mana mereka sedang mencari identitas diri. Belum lagi masalah kecanduan layar ponsel dan kurangnya waktu tidur, penggunaan ponsel yang berlebihan, terutama hingga larut malam juga dapat mengganggu pola tidur.
Kurang tidur kronis sendiri adalah pemicu utama kecemasan, suasana hati yang buruk, dan sulitnya konsentrasi, yang semuanya dapat berkontribusi pada munculnya gejala depresi dan burnout.
Selain tekanan dari dunia digital, Gen Z juga tumbuh di era dengan persaingan yang sangat ketat, baik di bidang akademis maupun profesional. Sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mereka diharapkan untuk berprestasi tinggi, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan memiliki CV yang cemerlang agar bisa masuk universitas favorit atau mendapatkan pekerjaan impian.
Tekanan untuk mencapai nilai sempurna, memenangkan setiap kompetisi, atau mendapatkan beasiswa seringkali berujung pada stres dan burnout yang parah. Mereka juga memiliki ekspektasi karier yang seringkali tidak realistis.
Banyak Gen Z yang berharap bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang sangat passionable, bergaji tinggi, dan punya dampak besar setelah lulus kuliah. Namun, realitas pasar kerja seringkali jauh lebih keras, persaingan ketat, dan gaji yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, yang mungkin tidak sejalan dengan impian besar mereka.
Ditambah lagi, ketidakpastian ekonomi global yang mereka saksikan, mulai dari berbagai krisis, pandemi, hingga inflasi yang menggerogoti, semuanya memengaruhi stabilitas pekerjaan dan biaya hidup.
Hal ini menimbulkan kecemasan mendalam tentang masa depan finansial dan kemampuan untuk mencapai kemapanan, bahkan untuk hal sesederhana membeli rumah di masa depan.
Meskipun sangat terhubung secara online, Gen Z seringkali kekurangan interaksi sosial tatap muka yang berkualitas. Meskipun mereka mungkin memiliki ribuan teman atau pengikut di media sosial, interaksi daring seringkali tidak mampu menggantikan kedalaman, keintiman, dan dukungan emosional yang diperoleh dari hubungan offline yang nyata.
Akibatnya, ini bisa menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi, meskipun mereka tampak terhubung secara digital. Ketergantungan pada komunikasi digital juga dapat mengurangi keterampilan sosial mereka dalam membaca isyarat non-verbal, bernegosiasi dalam konflik tatap muka, atau membangun empati yang mendalam, yang semuanya penting untuk hubungan yang sehat.
Selain itu, interaksi sosial di media sosial seringkali diwarnai oleh keharusan untuk tampil sempurna, menyembunyikan kelemahan, dan membangun citra yang ideal. Ini adalah beban emosional yang konstan dan bisa sangat melelahkan.
Di sisi lain, meskipun Gen Z lebih terbuka untuk membicarakan kesehatan mental, mereka mungkin belum sepenuhnya dibekali dengan strategi coping yang efektif. Banyak yang belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengembangkan mekanisme koping yang matang dalam menghadapi tekanan besar.
Mereka mungkin belum tahu bagaimana cara sehat mengelola stres, menghadapi kekecewaan, atau bangkit dari kegagalan. Stigma terhadap penyakit mental, meskipun sudah berkurang, masih ada disebagian masyarakat atau lingkungan terdekat, sehingga mereka mungkin ragu untuk mencari bantuan profesional.
Dan tentu saja, akses ke layanan kesehatan mental profesional yang berkualitas dan terjangkau masih menjadi tantangan di banyak tempat, termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Banyak yang mungkin tidak tahu harus mencari bantuan ke mana atau tidak mampu membiayainya.
Memahami semua faktor ini adalah langkah pertama untuk membantu Generasi Z. Ini bukan tentang menyalahkan mereka atas kondisi yang mereka alami, melainkan tentang memahami kompleksitas situasi dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.
Kita semua memiliki peran, orang tua, pendidik, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Kita perlu meningkatkan literasi kesehatan mental, mengajarkan penggunaan teknologi yang bijak dan pentingnya digital detox, membekali mereka dengan strategi mengelola stres, membangun resiliensi, dan menghadapi kegagalan.
Menciptakan lingkungan yang inklusif, menerima, dan mendukung sangat penting agar mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri dan mencari bantuan jika dibutuhkan. Mempermudah akses ke layanan kesehatan mental profesional, baik secara informasi maupun biaya, juga merupakan kunci.
Generasi Z adalah generasi yang cerdas, kreatif, dan sangat peduli. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, mereka dapat melewati tantangan ini dan menjadi agen perubahan yang positif bagi masa depan kita semua.