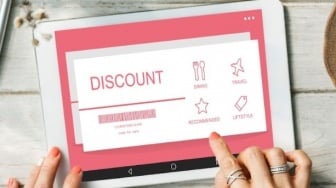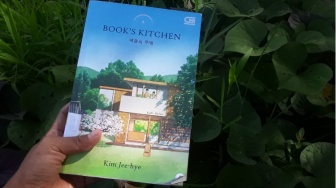Di jalan-jalan kota tua, di antara deru kendaraan bermesin dan kepulan asap knalpot, kita masih sesekali mendengar bunyi roda kayu bergesekan dengan aspal. Delman masih ada, meski semakin tersisih. Ia menjadi potongan masa lalu yang dipertahankan di tengah modernitas yang melaju cepat. Orang-orang sering menyebutnya romantis, seolah ada nilai sentimental yang harus dijaga. Tapi jika kita menyingkap lapis demi lapis romantisme itu, akan tampak wajah lain yang tidak seindah kenangan: kuda yang kelelahan, kulit yang lecet, tubuh yang kurus, dan tatapan mata yang nyaris padam.
Kuda delman bukan benda antik yang bisa kita pajang atas nama warisan budaya. Ia makhluk hidup yang punya batas, rasa lelah, dan hak untuk tidak disakiti. Namun di negeri ini, praktik semacam itu sering kali dilegitimasi oleh dua alasan klasik: tradisi dan ekonomi. Atas nama tradisi, kekerasan menjadi wajar. Atas nama ekonomi, penderitaan menjadi termaafkan. Maka kita pun terbiasa melihat pemandangan yang mestinya mengusik nurani, tetapi kini terasa biasa-biasa saja.
Persoalan delman sesungguhnya berbicara tentang cara kita memandang kebudayaan. Apakah budaya hanya perkara melestarikan bentuk, atau juga soal memperbarui nilai di baliknya? Melestarikan delman tidak bisa hanya berarti mempertahankan kuda yang menarik beban di tengah panas. Jika yang ingin dijaga adalah nilai gotong royong, kesederhanaan, atau kedekatan dengan alam, semua itu bisa hidup tanpa harus menjadikan hewan sebagai korban.
Dalam banyak kota, delman kini lebih banyak berfungsi sebagai atraksi wisata ketimbang alat transportasi. Ia hadir demi kepuasan visual wisatawan yang ingin merasakan nuansa masa lalu. Tetapi di balik itu, ada kontradiksi moral yang tajam. Kuda dipaksa bekerja berjam-jam, menempuh rute panjang di bawah matahari, tanpa cukup air atau makanan. Ia hanya berhenti ketika tenaganya benar-benar habis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa eksploitasi hewan sering kali berjalan dalam wajah yang beradab. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya kelelahan yang sunyi.
Jika kita bicara dalam kerangka hukum, kesejahteraan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan turunannya. Namun norma hukum itu sering berhenti di atas kertas. Pengawasan lemah, penegakan tidak berjalan, dan pelaku ekonomi kecil sering kali dibiarkan berjuang sendiri. Padahal, hukum mestinya menjadi jembatan antara nilai dan realitas. Ia tidak hanya mengatur, tetapi juga memelihara martabat. Dalam konteks ini, melindungi kuda delman bukan sekadar soal kasih sayang pada hewan, tetapi juga ujian atas keberpihakan hukum pada yang lemah, tak bersuara, dan tak punya kuasa.
Argumen bahwa delman harus dijaga karena menjadi mata pencaharian banyak orang juga perlu ditempatkan dalam perspektif yang adil. Tidak ada yang menolak fakta bahwa kusir delman adalah bagian dari rakyat kecil yang berjuang hidup di tengah tekanan ekonomi. Tetapi keadilan tidak bisa diwujudkan dengan memindahkan beban dari manusia ke hewan. Negara mestinya hadir dengan solusi yang lebih etis: alih profesi, bantuan sosial, atau transformasi delman menjadi kendaraan ramah lingkungan yang tidak lagi mengandalkan tenaga kuda.
Persoalan delman akhirnya membawa kita pada refleksi yang lebih besar tentang relasi manusia dengan makhluk lain. Di titik ini, kebudayaan diuji: apakah ia masih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, atau justru menjadi pembenaran bagi kekuasaan manusia atas segala yang hidup. Jika kita masih bisa merasa iba melihat kuda terengah di tengah terik, maka kita masih punya ruang untuk tumbuh sebagai bangsa yang beradab.