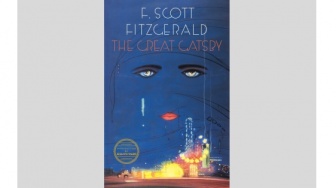Di ujung barat Nusantara, ada sebuah tanah yang indah dan kuat: Aceh. Provinsi yang sejak dulu dikenal sebagai “Serambi Mekkah”. Tempat lahirnya ulama-ulama besar, pusat perdagangan, dan daerah pertama yang menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia.
Namun, di balik sejarah emas itu, ada lembaran kelam yang jarang dibicarakan. Bahkan, seiring berjalannya waktu, terkubur dan sengaja dilupakan. Inilah kisah tentang air mata dan darah yang jatuh antara tahun 1989 hingga awal 2000-an, masa ketika Aceh berada di bawah status Daerah Operasi Militer (DOM).
Apa Itu DOM Aceh?
DOM berarti bahwa kehidupan sipil dihentikan dan digantikan dengan kekuasaan militer. Kekuasaan tidak dipegang oleh polisi atau pemerintah daerah, melainkan oleh pasukan bersenjata yang menjadi pengatur keamanan, hukum, dan tindakan di lapangan.
Pada tahun 1989, pemerintah Orde Baru menetapkan Aceh sebagai DOM untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, yang terjadi tidak sesederhana “menumpas pemberontakan.” Yang kemudian berlangsung adalah puluhan tragedi kemanusiaan.
Rumah Terbakar, Warga Dikumpulkan, Peluru Dijadikan Hukum
Di masa DOM, pasukan khusus, dengan pelatihan intelijen, penyamaran, dan operasi taktis, diturunkan ke Aceh. Ribuan operasi dilakukan. Dalam banyak kasus, warga biasa ikut menjadi korban hanya karena dituduh anggota GAM atau sekadar “diduga membantu.”
Kesaksian yang bertahan hingga kini menyebutkan rumah-rumah dibakar, warga dikumpulkan di lapangan atau di halaman desa, lalu ditanyai dengan todongan senjata:
“Kamu GAM, heh?”
“Kamu mata-mata GAM!”
Beberapa orang ditembak di tempat. Yang lain dibawa dan hilang tanpa jejak. Kuburan massal bermunculan di berbagai wilayah. Ada yang berisi puluhan jasad, ada yang mencapai ratusan.
Diperkirakan lebih dari 10.000 warga sipil meninggal dalam periode ini, 150.000 mengungsi, dan puluhan ribu lainnya mengalami penyiksaan, pelecehan, atau cacat fisik maupun mental seumur hidup.
Soeharto Jatuh, Tapi Aceh Belum Sembuh
Ketika Soeharto tumbang pada Mei 1998, harapan mulai muncul. Presiden Habibie mencabut status DOM, tetapi ketakutan masih bertahan. Konflik belum berakhir. Di era berikutnya, terutama pada masa pemerintahan Megawati, operasi militer kembali diperkuat. Ribuan orang lagi-lagi menjadi korban konflik baru.
Hingga hari ini, banyak janda, anak yatim, dan penyintas hidup tanpa kepastian. Luka mereka bukan hanya kehilangan keluarga, tetapi juga trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ironi: Sang Penolong dan Sang Korban
Aceh adalah provinsi pertama yang mendukung proklamasi tahun 1945. Aceh menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Indonesia. Pejuang-pejuangnya, lelaki maupun perempuan, berjuang bersama republik mempertahankan kemerdekaan.
Mulai dari Cut Nyak Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, Panglima Polem, dan Teuku Cik di Tiro. Namun, ironisnya, wilayah yang berjasa itu justru menjadi salah satu yang paling menderita oleh kebijakan negara yang seharusnya ia lindungi.
Sementara itu, sebagian tokoh di tingkat pusat yang merancang atau mengawasi operasi DOM kini hidup nyaman, dihormati, bahkan ada yang mendapat gelar pahlawan nasional.
Kenapa Kita Perlu Tahu?
Sejarah bukan untuk membuka luka, tetapi agar kita tidak mengulang tragedi yang sama. Aceh telah berdamai sejak Perjanjian Helsinki tahun 2005, tetapi bekas lukanya masih ada. Mengingat DOM bukan berarti menyalahkan generasi masa kini, melainkan memahami bahwa perdamaian hari ini dibangun di atas harga yang sangat mahal.
Mereka yang kehilangan keluarga, masa kecil, rumah, dan harapan, layak didengarkan. Layak dikenang. Layak dihormati. Aceh bukan sekadar wilayah di peta. Hanya karena zaman berganti bukan berarti semua menjadi dongeng semata.
Cerita tentang keteguhan, penderitaan, dan keberanian untuk bertahan ketika dunia menutup mata layak mendapatkan keadilan. Bahkan jika keadilan itu tidak pernah ada, penting untuk tahu diri dan tidak menginjak luka yang jelas masih bernanah.