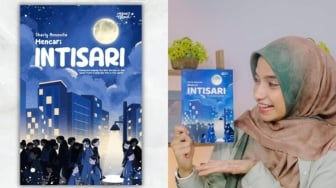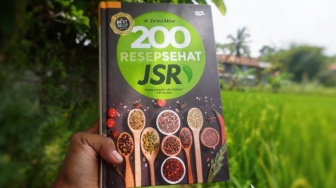Berdasarkan laporan pada awal tahun 2020, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 64 persen dari 272,1 juta populasi (Pertiwi, 2020). Angka ini tentu terus bertambah seiring waktu karena adanya perkembangan zaman dan tuntutan untuk penggunaan internet. Salah satu faktornya juga termasuk pandemi Covid-19. Pandemi ini menuntut banyak pekerja dan siswa-siswi untuk beraktivitas di rumah saja. Hal ini juga menjadi cara baru dalam bekerja dan belajar, hanya melewati aplikasi dengan fitur video call ataupun conference.
Perkembangan pengguna internet juga meningkatkan pengguna aktif media sosial. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia, kenyataannya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Pernyataan ini didukung dengan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia yang mencapai 59% total populasi, atau sekitar 160 juta pengguna.
Selain itu, Indonesia juga menempati urutan tinggi pada peringkat mengenai rata-rata waktu penggunaan media sosial per hari. Dilansir dari BBC, Indonesia menempati peringkat ke-2 di Asia dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial sebanyak 3-4 jam per harinya.
Perkembangan ini tentu berkaitan erat dengan perkembangan tuntutan akan kebebasan berpendapat di media sosial. Kebebasan berpendapat di media sosial awalnya memang merupakan hal yang wajar, mengingat adanya Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945 yang menjadi payung hukum mengenai kebebasan dalam berpendapat.
Hak Asasi Manusia yang tercantum pada UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 14-32 melindungi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik bentuknya lisan, tulisan, dan lain-lain. Tentu kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan juga dilindungi oleh Hak Asasi Manusia tersebut. Namun, pemanfaatan hak yang salah tentunya akan menimbulkan permasalahan.
Kemudahan untuk mengemukakan pendapat di media sosial, bahkan dengan fitur anonim, membuat masyarakat dapat merespon dan mengemukakan pendapatnya pada isu-isu di berbagai bidang, baik sosial, politik, maupun ekonomi.
Penyalahgunaan kemudahan yang disediakan media sosial tentu akan mendatangkan dampak negatif, seperti hoax, ujaran kebencian, perdebatan pro-kontra, hanya sebagian kecil dari banyaknya dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial. Oleh karena itu, untuk mengatur kebebasan berpendapat di media sosial, pemerintah Indonesia memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bagaimana pengguna internet harusnya mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi di dunia internet. Sehingga, menjadi penting untuk memahami perspektif etika dalam kebebasan berpendapat di media sosial.
Dengan maraknya perkembangan media sosial, dilema dalam etika semakin meningkat termasuk dalam hal pelanggaran privasi dan penindasan. Pada konteks ini, etika berguna untuk membimbing manusia dalam bertindak, dalam konteks berpendapat di media sosial maka etika berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Salah satunya ialah etika teleologi di mana membahas mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang berdasarkan tujuan yang akan kita capai. Dalam etika teleologi berbeda dengan etika deontologi karena etika ini membahas mengenai bagaimana kita bertindak dalam situasi tertentu dengan melihat akibat yang akan ditimbulkannya.
Dalam penerapannya, etika teleologi dibagi menjadi dua aspek yaitu, egoisme etis dan utilitarianisme. Pada implementasinya dalam kebebasan berpendapat di media sosial kedua hal tersebut dapat menjadi batasan bagi penggunaannya.
Pertama, egoisme etis merupakan etika yang menilai suatu tindakan sebagai hal baik karena dapat memberikan kebaikan bagi pelakunya. Sebagai contoh dalam penggunaan media sosial, tentunya kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Namun dengan adanya hal ini tidak dapat kita artikan bebas semaunya kita tanpa beretika, sehingga kita perlu mengetahui etika yang harus kita perhatikan dalam mengekspresikan pendapat kita dalam media sosial.
Sering kali terjadi permasalahan dalam media sosial akibat kurangnya kesadaran manusia dalam beretika, pada saat kita mengeluarkan pendapat dalam memanfaatkan media sosial kita perlu memperhatikan etika dalam berkomunikasi.
Hal ini dapat dilihat banyak sekali hate speech yang sering muncul melalui media sosial baik yang disengaja dan tidak sengaja. Dengan demikian, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dalam berinteraksi melalui media sosial agar tidak merugikan siapapun.
Kedua, utilitarianisme adalah etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang berdasarkan akibat yang akan didapatkan bagi banyak orang. Pada prinsipnya, etika utilitarianisme menganut bahwa segala tindakan yang kita lakukan dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, sehingga yang perlu dilakukan hanyalah memikirkan tindakan yang kita lakukan apakah merugikan orang lain atau tidak.
Dalam praktik kebebasan berpendapat dalam media sosial, kita harus mempertimbangkan dampak yang akan diberikan bagi banyak orang sebelum berkomentar di media sosial. Pastinya manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi satu sama lain dan setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda. Biasanya dengan adanya perbedaan pandangan atau pendapat ini akan memudahkan timbulnya masalah.
Manusia pada hakikatnya akan memperjuangkan keinginan yang dimiliki dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas dirinya. Namun dalam utilitarianisme lebih mementingkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri, dalam hal ini pertimbangan yang kita lakukan sebelum berpendapat di media sosial harus dilakukan untuk membawa manfaat bagi banyak orang.
Dalam bermedia sosial, pengguna juga harus memperhatikan berbagai macam etika termasuk virtue ethics atau etika keutamaan. Etika keutamaan atau virtue ethics biasa disebut juga etika kebajikan yang berfokus pada sumber-sumber moralitas dalam kehidupan dan karakter batin (Baron, Petit, & Slote, 2001). Etika ini ingin menjawab pertanyaan dasar yaitu saya harus menjadi orang yang bagaimana (Bertens, 2013).
Kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945, apabila ditinjau dari sudut pandang etika kebajikan maka tidak sepenuhnya sempurna dalam menjamin kebebasan termasuk di media sosial. Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di Indonesia tersebut juga sering bertabrakan dengan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3).
Salah satu contoh kasus dari polemik tersebut adalah penetapan vonis 1 tahun penjara yang diterima oleh musisi tanah air, Ahmad Dhani, yang dinyatakan bersalah usai melakukan cuitan di akun Twitter. Dalam hal ini, pemerintah melalui pejabat publik ketika memutuskan tindakan atau kebijakan dalam situasi tertentu memanfaatkan pendekatan etika ini. Oleh sebab itu, institusi publik atau anggotanya harus menumbuhkan sifat-sifat karakter yang berbudi luhur dan melakukannya dalam perilaku sehari-hari (Deverette, 2002).
Implementasi kebebasan berpendapat di media sosial juga selaras kaitannya dengan ketiga cakupan dari virtue ethics atau etika kebajikan yaitu eudaimonism, agent-based, dan ethic of care. Cakupan yang pertama adalah eudaimonism yaitu kebajikan yang berbasis pada kemampuan menalar. Sedangkan agent-based yaitu kebajikan adalah bertindak sebagaimana kita ingin orang lain bertindak kepada kita. Selain itu ada ethic of care yaitu nilai-nilai yang berbasis feminitas seperti kepedulian, perawatan, dan kasih sayang.
Dalam kebebasan berpendapat di media sosial, aspek yang paling berkorelasi adalah agent-based. Hal tersebut dikarenakan kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hal yang diatur dalam etika terutama virtue ethics atau etika kebajikan. Apabila kita ingin diperlakukan baik di media sosial, maka kita harus berbuat baik pula. Konsep tersebut merupakan implikasi dari agent-based yang merupakan cakupan dari virtue ethics atau etika kebajikan.
Media sosial menjadi media yang penting untuk menyampaikan pendapat, bertukar opini, diskusi, dan sarana berinteraksi. Namun, perkembangan proses berkomunikasi kadangkala menciptakan kegaduhan publik. Seringkali pendapat disampaikan tanpa memikirkan perasaan orang lain, dipenuhi caci maki, celaan, bahkan menimbulkan cyberbullying. Dari hal ini terjadi krisis etika dalam berkomunikasi di media sosial.
Dalam media sosial, kita memang diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun, di manapun, dan kapanpun. Namun, bebas disini bukan berarti tanpa etika, melainkan harus diimbangi etika yang diperlukan dalam menggunakan jejaring sosial.
Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika dalam media sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wahana untuk mendudukkan proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud harmonisasi.
Komunikasi harus dijalani dengan etika karena jika tidak disertai etika maka akan mengarah pada kekacauan yang akan merugikan masyarakat. Media yang semestinya membantu masyarakat memahami persoalan sosial politik secara jernih dan obyektif, justru jadi ajang persitegangan dan perseteruan tak berujung (Sudibyo, 2016).
Etika dalam berkomunikasi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik namun diwujudkan dari niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang menggunakan etika akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bercirikan penghargaan, perhatian, serta dukungan secara timbal balik dari pihak-pihak yang berkomunikasi.
Penyampaian aspirasi dan pendapat dalam media sosial memerlukan komunikasi yang beretika. Realitanya, penggunaan etika dalam berkomunikasi di media sosial masih seringkali kurang santun dan dipinggirkan. Disamping itu, sebagai pengguna yang cerdas, kita perlu bijak dalam menanggapi berita-berita hoax yang tersebar di internet. Sebelum menyebarkan suatu informasi, baiknya diperiksa terlebih dahulu kebenaran berita atau informasi agar tidak menyesatkan ataupun merugikan pihak lain.
Cara yang dapat dilakukan untuk melatih etika dalam berkomunikasi di media sosial adalah dengan membiasakan diri untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar saat kita berinteraksi, siapapun lawan bicara kita. Pengguna media sosial juga sebaiknya cermat dan menghindari penyebaran tulisan-tulisan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA, pornografi, dan aksi kekerasan.
Sebagai pengguna media sosial yang cerdas, kita dapat menyebarkan hal-hal yang berguna di media sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak serta membuat media sosial menjadi lingkungan yang aman serta nyaman untuk setiap penggunanya.