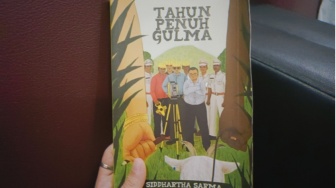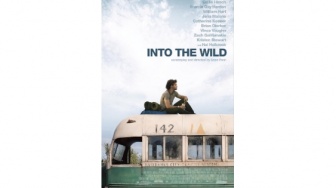Pernah terpikir untuk mengintip karya-karya klasik Indonesia? Barangkali, sebagian dari kita ada yang merasa bahwa karya tersebut tidak begitu relevan lagi dengan keadaan saat ini. Anggapan itu tidak seluruhnya salah, sebab konflik, bahasa, dan isu-isu yang ada kemungkinan memang berbeda. Namun, bukan berarti karya klasik zaman dahulu tidak menarik untuk dibaca saat ini. Apalagi, bagi mereka yang tertarik dengan kajian kebahasaan, karya klasik bisa menjadi pilihan.
Ada anggapan bahwa buku menjadi sarana yang tak kalah pentingnya dalam menambah pengetahuan kebahasaan kita. Dari buku-buku, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah kalimat dibentuk, bagaimana paragraf saling terhubung, dan bagaimana menggunakan kosakata yang sesuai konteks. Dan tentu, kita menggunakan buku dalam memperdalam kemampuan berbahasa Indonesia kita dengan melirik karya-karya lintas zaman, atau karya klasik Indonesia .
Melirik karya lintas zaman ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Sebab, bagaimanapun, tatanan bahasa yang digunakan tiap zaman berbeda satu sama lain. Kita barangkali pernah membaca karya-karya klasik terbitan Balai Pustaka, atau karya-karya yang ditulis oleh penulis peranakan Tionghoa. Dari situ, kita bisa mendapati perbedaan yang sangat mencolok. Terutama, bila kita membandingkannya dengan karya-karya yang beredar saat ini.
Dengan membaca karya-karya lintas zaman seperti itu, setidaknya kita jadi tahu perkembangan bahasa Indonesia yang digunakan para penulis. Ia berkembang tidak saja soal ejaan saja— dari Van Ophuijsen sampai EYD, tetapi juga terdapat perkembangan dalam hal struktur kebahasaan dan kecenderungan penggunaan kosakata tertentu. Selain itu, hampir tiap-tiap zaman memiliki keunikan dan perbedaan yang bila dicermati amat kentara dalam setiap karya-karyanya.
Hal itu misalnya, tampak dalam kalimat pembuka cerita anak “Pemandangan Dalam Doenia Kanak-kanak: Si Samin Semasa Ketjil” karya Moehammad Kasim berikut: Si Samin doedoek mentjangkoeng menghadapi doea tongkol djagoeng rebus, yang baharoe diberikan oleh iboenja. Cerita ini, karena terbit pada tahun 1925, patut diduga masih menggunakan ejaan Van Ophuisjen. Lalu, ia juga punya kosakata khas yang lazim didapati pada karya-karya klasik, terutama terbitan Balai Pustaka: Mencangkung.
Kalau kita bandingkan dengan struktur bahasa yang lazim digunakan saat ini, kosakata tersebut bisa dibilang jarang sekali ditemukan lagi. Pengarang kita hari ini kerap kali menggantinya dengan, misalnya, duduk mengangkat lutut atau berjongkok saja. Sementara, bila kita melirik lebih jauh ke dalam KBBI, terdapat kata bertinggung yang punya kesamaan makna dengan kata ini. Namun, sama seperti mencangkung, kata bertinggung lebih tak sering lagi kita dapati.
Perubahan penggunaan itu bisa jadi disebabkan kebanyakan dari pengarang ini menganggap kosakata tersebut terlalu klasik. Soal itu, mungkin kita bisa menelusurinya lebih jauh lagi. Namun, yang perlu diingat, walau jarang digunakan, setidaknya kita tahu kosakata itu tetap eksis. Selain itu, kosakata atau pola kalimat yang terdengar asing di telinga kita bukan hanya itu saja, sebab terdapat ratusan karya sastra klasik yang ditinggalkan. Dan, dari situ, kita bisa meliriknya lagi, lalu mendapati bahwa bahasa Indonesia itu sungguhlah kaya.