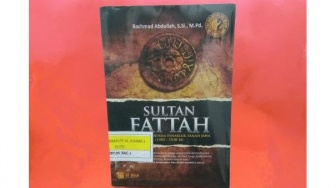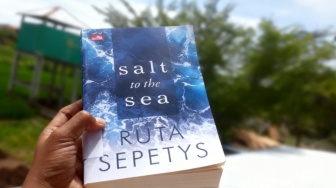Apa yang ditawarkan Siddharta Sarma di buku debutnya, Tahun Penuh Gulma (Marjin Kiri, 2020), ini? Bila membaca keterangan penerbitan ke bahasa Indonesia, yang menyebutkan bahwa buku ini diganjar Neev Book Award 2019 untuk kategori novel Young Adults, kita bisa menduga ada sesuatu yang penting di dalamnya. Sesuatu yang penting itu mungkin dinilai subjektif semata, tapi tetap, kita tidak bisa menafikan bahwa Tahun Penuh Gulma melekatkan hal tersebut dalam jati dirinya. Pertanyannya, apakah hal penting dari novel yang edisi bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Barokah Ruziati ini?
Kesadaran. Inilah poin utama yang coba dipantik Sarma terhadap pembaca novelnya. Dikisahkan, suku Gondi yang tinggal di distrik Odisha, India, tengah mengalami ancaman dari pihak luar. Ancaman ini bukan budaya atau teknologi yang mengubah sekian kebiasaan dan menghapus nilai-nilai luhur mereka. Lebih dari itu, ancaman tersebut lebih membahayakan lagi, sebab ruang hidup merekalah yang dipertaruhkan. Bukit Devi yang selama bertahun-tahun mereka jaga dan menjadi tumpuan hidup mereka terancam dijadikan lahan tambang. Dan, atas rencana tersebut, mereka diminta untuk angkat kaki dari tempat tinggal yang mereka tempati sekarang.
BACA JUGA: 5 Buku Self Improvement Favorit, Upgrade Diri untuk Kehidupan Lebih Baik!
Konflik agraria. Itulah yang menimpa masyarakat suku Gondi pada saat itu. Konflik ini tentu tidak dipancing oleh mereka sendiri, tetapi pihak luarlah yang memulainya terlebih dahulu. Dan bukan pihak lain, mula-mula, ada pihak perusahaan yang menginginkan bukit Devi. Di mata mereka, bukit itu mengandung kandungan mineral bauksit yang melimpah, bahkan menjadi satu yang paling melimpah dari sekian bukit atau lahan di seluruh India. Namun, nilai bukit Devi tidak semata segundukan tanah dengan mineral tambang di dalamnya. Bagi suku Gondi sendiri, bukit itu dinilai keramat: “Bukit itu adalah dewi suku Gondi di sini. Mereka percaya itulah sebabnya ada begitu banyak tanaman obat di tubuhnya. Itu sebabnya hanal kot di sini adalah yang terpenting bagi banyak suku Gondi di seluruh distrik (Hal. 31).”
Oleh sebab itu, mereka lantas berjuang mati-matian dalam mempertahankan tanah mereka. Semua penduduk sepakat untuk menolak pembukaan tambang. Di tubuh masyarakat suku Gondi ini, kemudian muncul satu bocah yang menjadi pusat cerita di novel. Nama anak itu Korok, bocah lanang yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah milik pejabat kehutanan. Kendati tidak lulus sekolah dan buta aksara, nyatanya bocah ini bukan anak yang sembarangan. Ia memiliki kemampuan berkebun paling mahir di desa. Insting dan sikap kritisnya pun sudah kentara sejak kecil. Ia menjadi satu-satunya anak suku Gondi yang terjun langsung dalam perjuangan menolak pembukaan tambang.
Upaya mereka jelas bukan perkara yang mudah. Bagaimanapun, yang mereka lawan adalah pihak kapitalis yang mempunyai modal dan kekuasaan yang terjamin. Maka, tidak perlu heran, bila jalan yang diambil pihak perusahaan adalah dengan turut melibatkan pemerintah dan jaringan khusus untuk menangani perlawanan masyarakat suku Gondi. Imbasnya, suku Gondi menjadi berjuang sendirian. Perjuangan itu juga menerbitkan rasa putus asa yang tak bisa dihindarkan. “Kita tidak bisa melawan pemerintah. Kita bisa bicara kepada mereka, mengangkat-angkat spanduk dan poster ke depan mereka, tetapi pada akhirnya mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan (Hal. 160).”
Apakah mereka menyerah begitu saja? Belum tentu. Kendati banyak hal yang merintangi perjuangan suku Gondi, tetapi mereka terus memilih maju. Sebab di mata mereka tanah itu sedemikian penting, dan kehilangan ruang hidup sama saja dengan kehilangan identitas mereka. Apa yang dialami suku Gondi kemudian menjadi penggambaran dari sekian dampak yang ditimbulkan konflik agraria di banyak tempat, terutama di negara-negara Dunia Ketiga. Sama seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya, konflik ini lebih sering menguntungkan satu pihak saja. Dan, jelas, pihak itu bukan masyarakat atau kelompok adat yang dilibatkan. Alih-alih, mereka justru yang paling sering dirugikan dengan adanya perseteruan ini.
BACA JUGA: Menelisik Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Buku "Humanisme dan Sesudahnya"
Kita bisa melihat contohnya dari banyak kasus yang merentang selama ini. Selain terancam memperoleh kerugian materil, mereka juga terancam kehilangan tempat tinggalnya. Atas masalah ini, pemerintah yang semestinya menjadi pihak yang menengahi atau memihak warganya, kerap kali justru menutup mata. Bahkan, mereka sering berdiri di kubu perusahaan atau kapitalis yang hendak merebut tanah miliki warga atau kelompok masyarakat tertentu tersebut. Ya, mereka jarang hadir di dalam kepentingan dan perjuangan rakyatnya.
Sikap menutup mata ini juga bisa jadi ditopang oleh kebobrokan sistem pemerintahan di daerah tempat konflik berlangsung. Misalnya, di dalam novel ini, digambarkan secara jelas betapa pihak kepolisian sama sekali tidak hadir sebagai pelindung dan pengayom keamanan suku Gondi. Malahan, mereka hanya melihat suku Gondi sebagai orang-orang yang bisa ditahan untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan (hal. 216). Selain itu, meja pengadilan yang semestinya menjadi ranah untuk menegakkan keadilan, justru bercorak lembaga yang mudah diotak-atik. Hukum bisa dengan mudah dibeli. Dan, kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga sangat terepresentasikan dalam kisah suku Gondi ini.
BACA JUGA: Gambaran Peliknya Relasi Pertemanan dalam Novel 'Pencuri Amatir'
Atas semua hal yang kita dapati di dalam novel, maka kita patut memaklumi bahwa novel ini layak diganjar sejumlah penghargaan. Selain tidak dikisahkan dengan narasi yang muluk-muluk, bahkan cenderung sederhana, novel ini juga secara jelas memiliki misi untuk menyadarkan kita atas betapa keadilan dalam konflik agraria masih sukar ditegakkan. Penulis seolah ingin kita sadar akan isu ini. Ia ingin agar kita tidak begitu saja menutup mata, sehingga kita bisa menunjukkan kepedulian.
Namun begitu, kendati mempunyai misi membangun sikap kritis dan kesadaran, novel ini tidak begitu saja terjebak sebagai karya dengan narasi yang berat. Ia tidak tampil sebagai sebuah paksaan, ceritanya bukan sesuatu yang menuntut. Ia hanya bercerita, bercerita dengan kepolosan. Dan hal inilah yang lantas membuatnya hadir sebagai hiburan sekaligus narasi penggugah kesadaran.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS