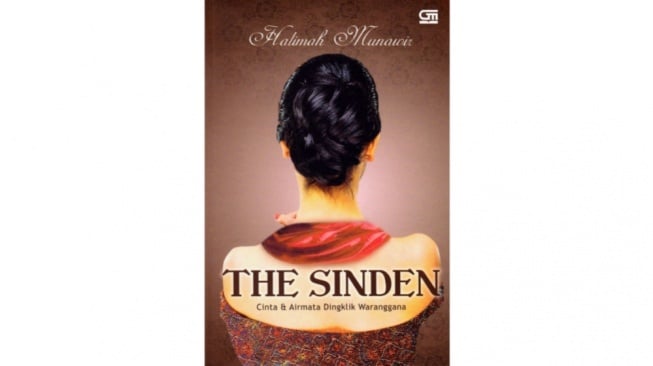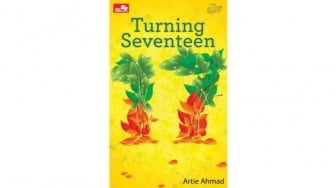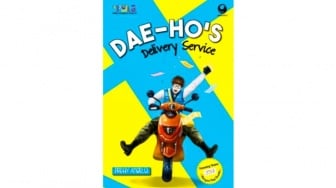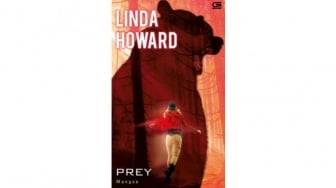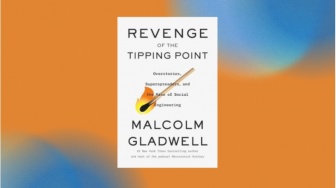Novel The Sinden mempunyai premis yang cukup menarik, yaitu tentang kehidupan seorang sinden, penyanyi wanita pada seni gamelan atau dalam pertunjukan wayang (golek, kulit).
Novel terbitan Gramedia Pustaka Utama (2011) karya dari Halimah Munawir ini berkisah tentang keinginan besar dari seorang sinden terkenal, Nyi Inten, untuk menjadikan putri semata wayangnya, Waranggana, seorang sinden juga seperti dirinya.
Sejak kecil Waranggana dilatih vokal, diajari bermacam tembang, dan diberi pengetahuan tentang ritual yang biasa dilakukan seorang sinden. Waranggana juga mewarisi dingklik milik Nyi Inten, yang saat digunakan bisa memancarkan aura dan pesona saat nyinden.
Suatu ketika penguasa baru Desa Sukomaju mencari gadis-gadis cantik untuk dijadikan istri samping/selir dan untuk tumbal pembangunan jembatan. Waranggana termasuk yang menjadi incaran sang penguasa baru.
Nyi Inten segera meminta Jarok, paman dari Waranggana untuk menyelamatkan putrinya. Mereka berdua lalu melarikan diri dari desa dan sejak itu dimulailah perjalanan Waranggana menjadi sinden, sampai memakai nama panggung ‘Dingklik Waranggana’.
Novel The Sinden menarik dari segi tema. Tak banyak novel yang menceritakan kehidupan sinden dan saya cukup berekspektasi tinggi pada novel ini. Namun sayangnya, banyak sekali cacat logika, serba kebetulan, dan plot hole yang saya temui selama pembacaan saya.
Seperti disebutkan dalam narasi bahwa Jarok adalah kemenakan Nyi Inten atau anak dari adiknya (Hal. 15). Lalu mengapa Jarok bisa menjadi paman dari Waranggana? Jika narasinya demikian, bukankah mereka seharusnya sepupu?
Lalu saat Waranggana dan Paman Jarok kabur dari desa, mereka sempat menumpang truk Kang Parto, yang ‘kebetulan’ sahabat dari ayahnya Jarok, Jakiman.
Waranggana juga pernah kabur dari restoran ayam goreng milik Mbah Darmi, orang yang menerimanya bekerja setelah pergi dari desa. Ketika kabur ke arah pantai, Waranggana menasehati perempuan yang ingin bunuh diri dan ‘kebetulan’ perempuan itu adalah sinden.
Dari pantai tersebut lalu Waranggana berjalan kaki sampai ke candi Borobudur. Karena terasa mengganjal, saya langsung browsing internet untuk mencari ‘pantai terdekat dari Borobudur’.
Ada 4 pantai terdekat, salah satunya Pantai Indrayanti, yang jika berjalan kaki sampai Borobudur membutuhkan waktu 20 jam lebih. Jika Waranggana berjalan kaki dari restoran pada larut malam, lalu ke pantai, dan tiba di Borobudur ‘masih’ malam hari. Betapa saktinya Waranggana, pikir saya, atau penulisnya kurang riset jadi menimbulkan cacat logika dan plot hole.
Di Borobudur Waranggana tahu-tahu bertemu seorang perempuan bernama Nyi Mimi yang ‘kebetulan’ sahabat Nyi Inten, ibunda Waranggana. Waranggana lalu ikut berkolaborasi di kelompok tari milik Nyi Mimi yang akan pentas di acara pagelaran seni di candi Borobudur esok harinya.
Latihan satu hari dan Waranggana bisa langsung nge-blend dengan kelompok tari yang berlatih berbulan-bulan? Sedangkan Waranggana nyinden, yang berarti kelompok tari tersebut harus mengubah komposisi tarian, musik, dll demi menyesuaikan dengan ‘kehadiran’ Waranggana. Sangat tidak masuk akal bagi saya.
Setting waktu dan tempat tidak jelas. Sebagai pembaca saya jadi menerka-nerka, mencari kesesuaian lewat narasi dan dialog yang dihadirkan. Tapi, usaha itu pun tidak menolong karena ceritanya sendiri terlampau absurd.
Konflik cerita cukup banyak, tapi sayangnya semua tak berujung pada penyelesaian alias menggantung. Salah satunya saat Waranggana yang dirayu ke Jakarta oleh Ki Joko, ketua karawitan yang mengiringi Waranggana nyinden di restoran Mbah Darmi, sampai memberi Waranggana koin emas. Cerita itu tak jelas kelanjutannya.
Begitu pun ketika Waranggana (lagi-lagi) lari ke puncak gunung dan bertemu perempuan Belanda bernama Suzanna. Suzanna? Nama ‘Dingklik’ Waranggana sudah cukup aneh bagi saya, masih ditambah lagi dengan orang Belanda bernama Suzanna.
Cerita menjadi semakin absurd saat Nyi Inten ikut rombongan orang yang mencari Waranggana ke puncak gunung, karena gadis itu dikatakan dibawa Wewe Gombel. Nyi Inten tiba-tiba punya kemampuan mengendus-endus macam anjing pelacak dan menjadi penunjuk arah.
Saat rombongan kelelahan, Nyi Inten jadi satu-satunya orang yang masih gagah. Bahkan saat yang lainnya beristirahat, Nyi Inten terus jalan sendirian untuk mencari anaknya. Luar biasa!
Ending cerita terlampau terburu-buru seakan hanya demi menuntaskan cerita. Ya mau bagaimana lagi, jika diteruskan ceritanya tentu akan semakin absurd dan bikin frustrasi pembaca seperti saya.
The Sinden memang masih memiliki banyak kekurangan, tapi bagusnya novel ini tak memiliki banyak typo. Jadi, sebagai pembaca yang tabah—karena tetap membaca novel ini sampai selesai meskipun absurd—saya masih melihat adanya kelebihan dari novel ini.
Kelebihan lainnya, di awal-awal bab, profesi sinden sudah dijelaskan meski tak mendetail. Setidaknya pembaca jadi tahu ada ritual-ritual yang dilakukan seorang sinden, seperti ritual kungkum sebagai prosesi 'wisuda' seorang sinden yang dianggap sudah mentas dan juga ritual sebelum manggung.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.