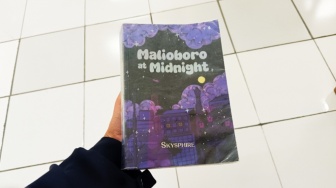Ulasan
Review Film Ziarah: Perjalanan Mbah Sri Menyusuri Luka dan Harapan
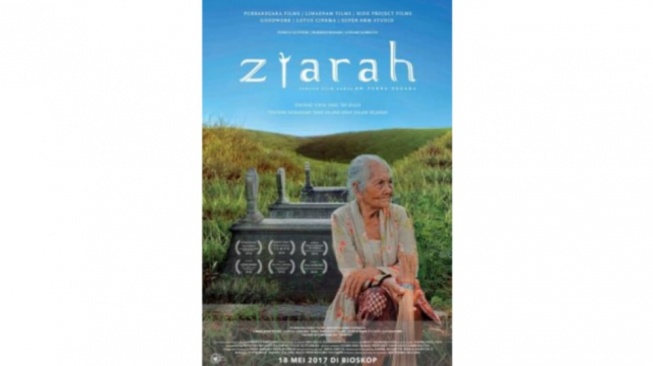
Ada film-film yang memikat bukan karena visual bombastis atau bintang papan atas, tapi karena diam-diam menampar dengan lembut dan meninggalkan bekasnya dalam hati.
‘Ziarah’ (2017), film panjang perdana sutradara BW Purba Negara jelas salah satunya. Film ini bukan hanya berhasil menggugah lewat kisahnya, tapi juga menempatkan sosok nenek berusia 95 tahun yang belum pernah berakting sebelumnya sebagai pemeran utama. Dan lebih dari sekadar gimmick, penampilan Mbah Ponco Sutiyem justru jadi pusat emosi film ini—natural, mengena, dan menyentuh.
Sekilas tentang Film Ziarah
Diproduksi Limaenam Films, Ziarah mengajak kita melakukan perjalanan batin dan fisik bersama Mbah Sri (Ponco Sutiyem) perempuan tua dari desa kecil yang masih menyimpan luka lama. Dia kehilangan suaminya, Pawiro Sahid, sejak Agresi Militer Belanda II pada 1948.
Suaminya berpamitan untuk berjuang, tapi nggak pernah kembali. Puluhan tahun berlalu, dan Mbah Sri belum juga tahu di mana makam sang suami. Hingga suatu hari, ada seorang veteran perang mengaku mengetahui lokasi peristirahatan terakhir Pawiro. Dengan modal informasi yang sangat minim, Mbah Sri memulai perjalanannya seorang diri, melintasi desa demi desa, menapak masa lalu yang belum selesai.
Kisahnya simpel sih, tapi … mending baca terus sampai tuntas ya!
Impresi Selepas Nonton Film Ziarah
Cerita ini sebetulnya sangat sederhana, tapi justru di situ kekuatannya. Aku merasa seperti sedang ikut menyusuri lorong waktu bersama Mbah Sri. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan berbagai orang yang juga menyimpan luka sejarah: dari konflik tanah, trauma perang, hingga desa yang lenyap akibat pembangunan waduk. Semua fragmen ini dirangkai BW Purba Negara dengan hati-hati, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ziarah bukan hanya tentang makam, tapi juga tentang memeluk masa lalu yang pahit.
Lebih menarik lagi, film ini menggunakan pendekatan yang sangat njawani. Dari awal film, aku langsung dibawa masuk ke suasana khas Jawa.
Musik yang dikerjakan sama Miyoshi Masato dan Clemens Felix Setiyawan begitu kental nuansa tradisionalnya. Bahkan pada adegan pembuka, kamera ditempatkan di dalam liang kubur. Ibarat menempatkan diriku sebagai penonton dalam posisi simbolis, yang siap dikuburkan, atau siap merenungi kematian.
Oh iya. Ini bukan film horor, tapi film ini ada memunculkan elemen mistik khas Kejawen. Misalnya, ada adegan di mana keris bergerak sendiri. Eh, tapi bukan untuk menakuti ya, melainkan menjadi tanda, harapan, atau semacam keajaiban kecil yang justru menambah kesan spiritual kisahnya.
Sebagai penonton, aku merasakan betul bagaimana BW mengolah naskahnya dengan filosofi Jawa yang khas, terutama lewat praktik othak-athik gathuk—kebiasaan orang Jawa mengait-ngaitkan satu cerita dengan cerita lain, walau tanpa kepastian mutlak.
Dan itu jadi landasan utama bagaimana Mbah Sri dan cucunya, Prapto (diperankan Rukman Rosadi), melakukan pencarian. Mereka hanya berbekal petunjuk samar, tapi keyakinan membuat mereka terus berjalan.
Film Ziarah memang fiksi, tapi terasa sangat dekat dengan realita. Kok bisa? Soalnya si sutradara menyisipkan elemen dokumenter ke dalam filmnya, seperti ketika Prapto “mewawancarai” warga tentang peristiwa sejarah lokal, atau saat mereka membahas desa-desa yang hilang akibat proyek pembangunan. Aku jadi merasa ini bukan sekadar cerita tentang satu keluarga, tapi juga cerminan tentang sejarah yang seringkali luput dari arsip negara, tapi ada dan selalu diingat sama masyarakat.
Sayangnya, aku merasa film ini agak timpang dalam ritme. Banyak adegan perjalanan yang hanya menampilkan Mbah Sri duduk termenung atau berjalan sendiri dalam sunyi. Aku paham, ini mungkin diniatkan sebagai momen kontemplasi, tapi terkadang repetitif dan membuat tensi film mengendur. Rasanya akan lebih kuat kalau durasi dipadatkan, atau bahkan dibuat jadi film pendek saja.
Kendati demikian, performa Mbah Ponco benar-benar menambal banyak kekurangan. Dia nggak terlihat seperti sedang berakting, tapi seperti benar-benar sedang hidup di depan kamera. Semua gestur, sorot mata, dan dialog yang dilafalkannya penuh ketulusan.
Dan satu aspek teknis yang cukup mengganggu tuh terkait editing film ini. Beberapa transisi terasa kasar, bahkan membuat aku bingung di beberapa titik. Seperti ada adegan yang mendadak berpindah tanpa pengantar yang cukup, sehingga alur emosional jadi tersendat. Ini agak disayangkan, karena momentum-momentum reflektif film ini jadi kurang maksimal tersampaikan.
Terlepas dari kekurangannya, Film Ziarah tetap menyisakan pengalaman menonton yang nggak mudah dilupakan. Ending-nya, yang nggak akan aku bocorkan di sini, cukup mencekik dan membuatku termenung cukup lama.
Tontonlah, Sobat Yoursay. Minimal sekali seumur hidup.
Skor: 4/5