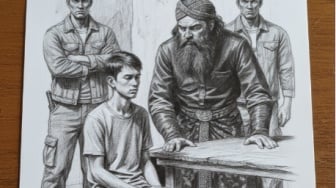Di peternakan tua yang dikelilingi pagar kawat berkarat, malam selalu lebih gelap daripada siang. Lampu sorot petani hanya menyapu kandang ayam dan kandang sapi.
Kandang kambing dibiarkan tenggelam dalam bayang-bayang. Di situlah Bima berdiri sendirian setiap malam, tanduknya yang melengkung menyentuh langit-langit jerami, matanya menyala seperti bara yang tak pernah padam.
Bima bukan kambing biasa. Ia lahir dari induk yang mati karena diseret traktor saat melahirkan. Sejak kecil ia menolak rumput kering yang dibagi rata.
Ia mencari daun liar di celah pagar, memakan kulit pohon muda, bahkan menggigit kabel listrik tua hingga peternak marah dan memasang kawat berduri ekstra.
Tapi Bima tak pernah berhenti. Ia percaya ada dunia di luar pagar yang tidak hanya terdiri dari rumput dan jerami.
Malam itu hujan sedang deras-derasnya. Angin menderu masuk lewat celah-celah papan. Ayam-ayam meringkuk ketakutan. Sapi-sapi mengunyah perlahan dengan mata setengah tertutup.
Hanya Bima yang bergerak. Ia mendekati pintu kandang yang terkunci rantai berkarat. Rantai itu sudah ia amati berbulan-bulan: satu mata rantai retak, cukup untuk ditarik keras-keras.
Dengan tanduknya ia menusuk celah rantai itu. Sekali, dua kali. Logam berderit. Ayam jantan tua bernama Joko terbangun.
“Kau gila, Bima. Besok pagi petani akan memotongmu.”
Bima tidak menjawab. Ia terus menarik. Rantai putus. Pintu terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dan rumput liar.
Ia melangkah keluar.
Bukan ke halaman depan peternakan yang terang. Ia berbelok ke belakang, ke lereng bukit kecil yang selama ini hanya dilihat dari kejauhan.
Di sana ada pohon-pohon liar yang tak pernah disentuh petani. Daunnya lebat, buahnya kecil tapi manis. Bima memakan sampai perutnya kembung. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kenyang sungguhan.
Tapi ia tidak berhenti di situ.
Di ujung bukit ada sungai kecil. Airnya jernih, tidak keruh seperti bak minum di kandang. Bima minum sampai tenggorokannya dingin.
Lalu ia melihat pantulan dirinya: tanduk panjang, bulu hitam legam, mata yang tak pernah tunduk. Ia tertawa kecil. Suara itu asing bagi dirinya sendiri.
Pagi mulai menjelang. Dari kejauhan terdengar suara traktor menyala. Bima tahu ia harus kembali sebelum petani membuka kandang.
Tapi ia tidak langsung pulang. Ia berjalan mengelilingi pagar belakang peternakan, mencari celah. Ia menemukan satu lubang kecil di bawah kawat berduri—mungkin dibuat kelinci atau landak. Dengan susah payah ia merangkak masuk, tanduknya menggores tanah.
Saat matahari terbit, ia sudah kembali di kandang. Rantai dipasang kembali seadanya oleh Bima sendiri menggunakan gigi dan kaki depan. Petani pun datang, membuka pintu, menghitung kepala. Semuanya lengkap. Tak ada yang curiga.
Malam berikutnya Bima keluar lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Seekor domba betina muda bernama Lila mengikuti. Ia melihat Bima pergi malam sebelumnya dan diam-diam menunggu.
“Kau mau ke mana?” bisik Lila.
“Ke tempat yang bukan milik petani.”
Mereka pergi bersama. Bima mengajari Lila cara minum dari sungai, cara memilih daun yang paling bergizi, cara menghindari lampu sorot. Lila belajar dengan cepat. Matanya yang tadinya selalu tertunduk mulai menatap lurus.
Satu per satu hewan lain mulai curiga. Joko si ayam jantan mulai bertanya. Sapi tua bernama Mbok Sari mendengar bisik-bisik. Bahkan babi gemuk yang biasanya hanya tidur mulai membuka mata.
Seminggu kemudian, saat bulan purnama, Bima berdiri di tengah kandang. Semua hewan terjaga.
“Aku tidak mengajak kalian memberontak,” katanya pelan.
“Aku hanya menunjukkan bahwa pagar itu bukan akhir dunia. Di luar sana ada rumput yang lebih hijau, air yang lebih bersih, dan malam yang tidak perlu ditakuti.”
Joko menggeleng. “Kau akan membawa kita semua ke potongan.”
Mbok Sari menghela napas panjang. “Tapi aku sudah lelah makan jerami kering setiap hari.”
Lila maju selangkah. “Aku ikut Bima malam ini.”
Satu per satu mereka memilih. Ada yang ikut, ada yang tetap diam. Yang ikut keluar lewat celah yang semakin lebar karena Bima terus menggali setiap malam. Yang tidak ikut menutup mata, berpura-pura tidur.
Petani mulai curiga saat jumlah kotoran di kandang berkurang. Rumput di halaman belakang mulai habis dimakan. Ia memasang kamera kecil di pohon. Malam itu rekaman menangkap bayangan kambing hitam melompat pagar, diikuti beberapa domba dan seekor sapi.
Pagi harinya petani marah besar. Ia memanggil tukang jagal. Tapi Bima sudah tahu. Ia tidak kembali malam itu.
Di lereng bukit, di bawah pohon besar, Bima, Lila, Mbok Sari, dan enam hewan lain berkumpul. Mereka tidak membentuk pasukan. Mereka hanya makan, minum, dan tidur di bawah bintang. Tidak ada pemimpin, tidak ada aturan baru. Hanya kebebasan yang sederhana.
Petani mencari mereka selama tiga hari. Lalu ia menyerah. Ia membeli kambing baru, domba baru. Kandang kembali ramai. Tapi setiap malam, jika angin bertiup dari bukit, terdengar suara kambing yang tertawa kecil—suara yang tak pernah ada sebelumnya di peternakan itu.
Bima tidak pernah kembali. Ia tidak perlu. Pagar sudah bukan lagi batas baginya. Hanya garis di tanah yang bisa dilompati kapan saja.
Dan di kandang malam, anak-anak kambing yang baru lahir kadang menatap ke arah bukit dengan mata berbinar. Mereka belum tahu cerita Bima. Tapi naluri mereka sudah berbisik: suatu malam, mungkin, mereka juga akan melompat.