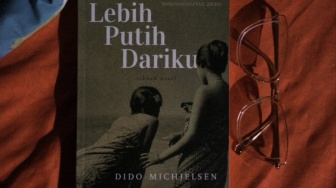Berbeda dengan era-era sebelumnya, kebanyakan orang hanya menjadi penonton pasif, dalam arti tak bisa mengambil peran lebih. Menilai dan berkomentar terhadap suatu tontonan hanya menjadi hak para kritikus, misalnya saja kritikus film, kritikus sastra, dan para pengamat.
Kini pada era memasyarakatnya media sosial, keadaannya jauh berbeda. Hampir semua orang dapat berperan menjadi penonton, orang yang ditonton, sekaligus bisa pula berperan sebagai komentator. Selebihnya dari semua itu, kini semua orang ingin menjadi terkenal atau populer dan menjadi tontonan khalayak.
Pada saat ini, menjadi viral merupakan hal yang ingin dikejar hampir semua orang. Alasannya orang yang menjadi viral atau sengaja diviralkan akan menjadi orang yang terkenal meskipun secara instan. Orang-orang yang aktif di media sosial, diakui atau tidak, selalu ingin mengejar viralitas dan popularitas.
Selain popularitas, keinginan dilihat seraya berhias dengan berbagai penampilan luar merupakan modal tambahan agar menjadi tontonan khalayak. Dari sini lahirlah hasrat untuk dilihat atau ditonton. Semakin banyak orang yang melihatnya, ia semakin populer, yang tak jarang mengantarkan seseorang menjadi selebritis baru yang tentu saja berujung dengan peraihan cuan.
Dari sudut pandang psikologi komunikasi budaya, hasrat seseorang yang ingin selalu ditonton, Nancy Etcoff (1999), salah seorang psikolog dari Amerika, menyebutnya dengan istilah lookism. Tak sedikit orang yang hasrat terhadap lookism-nya tinggi, seolah-olah “mempertuhankan” penampilan. Jargon yang ia pegang, semakin baik penampilan Anda, maka akan lebih sukseslah Anda dalam kehidupan.
Hasrat yang tinggi terhadap lookism tak jarang membuat seseorang berakting demi menarik perhatian orang. Aktingnya terkadang penuh kepura-puraan. Akting kepura-puraan inilah yang kemudian terkenal dengan istilah pencitraan.
Pencitraan sendiri lebih sering mementingkan penampilan permukaan alias penampilan luar, melupakan kedalaman makna, bahkan nirmakna. Gaya penampilan lebih penting daripada segalanya. Mode dan gaya pakaian lebih penting daripada fungsi pakaian itu sendiri.
Gaya penampilan sendiri menjadi sihir ampuh bagi khalayak. Mereka menjadi lebih banyak menilai penampilan luar, lebih menghargai gaya daripada makna. Tidaklah mengherankan jika banyak orang yang mementingkan penampilan dan menjadikannya sebagai selimut utama kepercayaan diri, melupakan hakikat jati diri yang sebenarnya.
Demi mengejar penampilan ini, gaya hidup konsumtifpun akhirnya singgah dalam kehidupan. Seseorang berani mengejar-mengejar keinginan terhadap suatu barang yang akan menunjang gaya penampilannya dan melupakan pertimbangan atas kebutuhan.
Mode pakaian, mode rambut, kosmetik, dan gadget selalu menjadi komoditi laris yang diburu orang-orang yang masuk ke dalam jeratan lookism. Mereka memakai dan memamerkannya demi popularitasnya ketika manggung dalam sandiwara kehidupan.
Banyak orang yang merasa terangkat harga dirinya ketika penampilan dan gaya hidupnya menjadi tontonan dan perbincangan khalayak apalagi jika penampilannya menjadi trend dan ditiru banyak orang. Kebanggaan ketika ditonton, ditiru, dan dipuja inilah yang sebenarnya disebut perilaku selebritas. Tidaklah salah jika era sekarang ini, selebritas bukan hanya milik para artis, tapi milik khalayak.
Tidaklah berlebihan jika Thomas C. O’Guinn, salah seorang pakar komunikasi menyebut masyarakat abad ke-21 segalanya adalah mengenai selebriti. Sikap selebritas biasanya berujung kepada keinginan untuk menjadi populer. Apapun akan dilakukannya demi konten dan popularitas. Tak sedikit orang yang berani mengorbankan nilai-nilai moral yang baik dan nilai-nilai spiritual demi konten dan popularitas.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkuasanya jaringan media sosial bukanlah hal yang sulit untuk menjadi populer, bahkan kepopuleran bisa dipesan dan dipasarkan. Siapapun bisa diviralkan dan memviralkan diri sendiri dan orang lain.
Kini media sosial telah menjadi industri besar yang memproduksi berbagai tokoh terkenal di dunia maya. Dengan kata lain, media sosial menjadi pasar terbesar untuk memasarkan konten, popularitas, dan menjadi public relation bagi hampir setiap orang.
Namun demikian, satu hal yang jarang disadari oleh kita, media sosial memiliki kuasa untuk membuat seseorang menjadi terkenal, tetapi sekaligus memiliki kuasa pula untuk melenyapkan siapapun dari tengah-tengah popularitas kehidupan.
Selama tujuannya baik dan ditempuh dengan suatu prestasi, serta tanpa menghancurkan prestise, menjadi populer bukanlah suatu hal yang salah. Kepopuleran yang tercela adalah kepopuleran yang dipaksakan, yakni kepopuleran yang diperoleh dengan menghancurkan nilai-nilai moralitas yang baik, melanggar norma agama, dan norma-norma sosial dengan tujuan utama agar dirinya dipuja-puji khalayak.
Popularitas yang diperoleh dengan cara melanggar moral yang baik, meskipun dipuja-puji khalayak tergolong kepada realitas popularitas semu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Para filosof, diantaranya Plato menggolongkan perbuatan melanggar moral demi puja-puji manusia sebagai perbuatan berselera rendah yang sebenarnya hampa dari nilai kebaikan di hadapan Yang Maha Agung.
Hasrat menjadi selebritas dan populer merupakan sikap yang melekat pada setiap jiwa manusia. Sikap ini tak akan hilang sepenuhnya dari jiwa manusia. Upaya yang bisa dilakukan setiap orang adalah mengendalikan hasrat berlebihan untuk menjadi selebritas dan meraih popularitas agar tidak menguasai diri dan mencemari nilai-nilai moralitas dan spiritual. Dengan kata lain, kita harus tetap menjaga komitmen terhadap moralitas dan spiritulitas, tidak mengorban keduanya demi lookism, selebritas, dan polularitas.