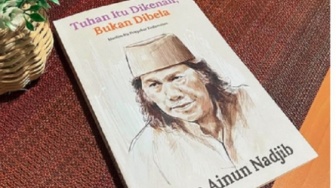Secara resmi Bawaslu RI mengumumkan perpanjangan rekrutmen bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di 4.272 kecamatan yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Dari Sumatera Barat, tersiar kabar, 44 kecamatan juga harus memperpanjang masa pendaftaran tersebut. Alasannya, pendaftar perempuan belum mencukupi ambang batas 30 persen.
Pagi kemarin lusa, saya berdiskusi dengan salah satu komisioner penyelenggara pemilu. Ia merupakan perempuan tangguh yang sudah berkecimpung di kepemiluan lebih dari satu dekade terakhir. Keterwakilan perempuan, katanya, seringkali diartikan bahwa perempuan hanya 30 persen dari jumlah yang dibutuhkan. Padahal itu syarat minimal, dan boleh lebih. Penafsiran keliru ini seringkali berujung pada syak-wasangka kecilnya probabilitas keterpilihan perempuan.
Dari kebimbangan tersebut, perempuan seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa sesama perempuan harus bersaing untuk merebut slot minimal 30 persen tadi itu. Pola pikir ini harus diubah. Dari semula berfikir: “berapa kuota perempuan, dan siapa saja perempuan yang mendaftar”. Diganti menjadi: siapa saja laki-laki yang mendaftar, dan berapa kuota laki-laki yang bisa direbut perempuan”.
Dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), dikenal sebutan affirmative action. Yaitu kebijakan yang dibuat untuk sejenak mengistimewakan kelompok tertentu agar bisa memperoleh peluang setara dengan kelompok lainnya. Dalam kontestasi pemilu, kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2004, dengan menetapkan kewajiban penempatan 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap (DCT). Sejak saat itu keterpilihan caleg perempuan mulai terdongkrak, meski belum cukup signifikan.
Tahun 2004 itu, perempuan hanya menguasai 11,24 persen kursi di DPR. Pemilu lima tahun kemudian jumlahnya naik menjadi 18,21 persen. Namun di tahun 2014, angka itu kembali menipis menjadi 17 persen. Periode inilah yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sayangnya, pada regulasi itu, salah satu frasa penting untuk penguatan affirmative action di tubuh penyelenggara pemilu, masih dibungkus dengan kata “memperhatikan” 30 persen keterwakilan perempuan. Tidak dengan tegas ditulis “wajib memenuhi”.
Produk hukum UU 7/2017 ini meletakkan kebijakan afirmatif dalam ranah abu-abu. Misalnya untuk komposisi keanggotaan KPU dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi: “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Untuk jajaran Bawaslu dapat dilihat di Pasal 92 ayat (11) yang berbunyi “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.
Selanjutnya, dari 575 Anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2019 lalu, ada 118 perempuan yang terpilih atau sebesar 20,5 persen. Ini adalah capaian tertinggi yang pernah diraih Indonesia terkait representasi perempuan di politik, kata Juniar Laraswanda Umagapi dalam risetnya yang diterbitkan di Jurnal Badan Keahlian DPR Volume 25 Nomor 1 tahun 2020. Tentunya produk-produk hukum dan kebijakan yang dilahirkan parlemen pada era ini, khususnya menyangkut pemberdayaan perempuan, masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Setidaknya, upaya mengubah frasa “memperhatikan” menjadi "wajib memenuhi” tadi itu, belum tercium sampai detik ini pergolakannya.
Untuk lebih jauh meneliti kerangka pemikiran ini, kata Dr Ani Soetjipto, dapat dibedah dari dua analisis yang tidak terlepas dari sudut pandang feminis. Dosen Politik dan Kajian Gender Universitas Indonesia itu mengemukakan perspektif analisis policy response untuk melihat bagaimana persoalan publik dan privat yang dihadapi perempuan direspons dan disikapi oleh kebijakan negara. Kemudian perspektif kedua dilihat dari analisis individual response, bagaimana perempuan dalam institusi birokrasi berusaha bersiasat dan berstrategi dari dalam sistem untuk mentransformasi negara patriarki.
Tulisan ini dapat dilihat dalam buku Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah (2018). Penulisan buku tersebut merujuk pada literatur klasik dalam ilmu politik tentang representasi, yakni buku “The Concept of Representation” yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967). Secara sederhana, Pitkin menjelaskan representasi sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili dengan cara tanggap (responsive) terhadap yang diwakili” (Pitkin, 1967: 209). Dengan kata lain, representasi memiliki esensi menghadirkan kembali yang tidak dapat ikut hadir dan mengutamakan relasi yang responsif antara wakil dan yang terwakili.
Jika demikian, seharusnya upaya kebijakan afirmatif untuk menempatkan keterwakilan perempuan 30 persen dalam formasi penyelenggara pemilu dapat saling melengkapi dalam hirarkis kelembagaan. Komposisi di tingkat pusat mendorong agar yang menjabat di level provinsi merepresentasi keterwakilan perempuan, begitu seterusnya sampai ke level penyelenggara pemilu terbawah. Kepada tim penulis buku Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah (2018), Ida Budhiati selaku Komisioner KPU RI 2012-2017, menegaskan kehadiran perempuan penting untuk memastikan kerja-kerja advokasi tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, kemudian (memastikan) keterwakilan perempuan penyelenggara di level yang lebih bawah, maka kehadiran perempuan itu penting dan perlu.
Tentu tidak lengkap rasanya opini ini tanpa menyematkan salah satu teori yang dipelajari dalam bidang Ilmu Komunikasi. Yang cukup populer untuk mengungkap perbedaan komunikasi budaya antara laki-laki dan perempuan, adalah Muted Group Theory temuan Edwin Ardener dan Shirley Ardener, tahun 1975. Karya duo antropolog sosial asal Inggris ini dapat dikenal sebagai teori kebungkaman atau teori kelompok bisu. Asumsi dasar teori ini, biasanya kaum laki-laki dipandang sebagai kelompok dominan secara hirarkis sosial sehingga memiliki power untuk menentukan pola komunikasi di sekitarnya. Sementara kaum perempuan dianggap sebagai kelompok marjinal yang hanya akan mengikuti sistem yang dibangun oleh laki-laki.
Asumsi kedua, untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka, kaum perempuan harus menyesuaikan gaya bahasa mereka ke ranah yang dapat diterima laki-laki. Mereka harus terlebih dahulu melakukan pengkodean bahasa. Teori ini berkembang, bahwa yang bisa disebut kelompok marjinal bukan hanya kaum perempuan, tapi juga kelompok minoritas dari suku, ras bangsa, agama, maupun kecenderungan seksual.
Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dapat menstimulus dan meningkatkan antusiasme perempuan untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Perempuan penyelenggara juga dinilai membantu caleg-caleg perempuan dalam proses penghitungan suara dan mengawal suara caleg perempuan. Begitu kata Ammy Amalia Fatma Surya, anggota Komisi II DPR RI periode 2014-2018 saat menjadi pembicara di acara Diskusi Media bertajuk “Mendorong Proses Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI yang Transparan dan Adil bagi Perempuan” yang diselenggarakan di Jakarta, 15 November 2016 silam.
Karena teori komunikasi ini juga menganggap kaum laki-laki itu tuli dan tidak bisa mendengar bahasa yang disampaikan perempuan, maka kita dapat meramu hipotesis sementara. Keterwakilan perempuan dalam demokrasi modern dipandang perlu agar terjadi keseimbangan suara-suara. Adalah manusiawi jika setiap individu lebih nyaman berinteraksi dengan sesama karena banyaknya kesamaan-kesamaan. Sesama alumni Unand akan lebih banyak bahan berinteraksi tentang kampusnya, dibanding saat berkumpul dengan alumni kampus lain, misalnya. Begitu pula dalam komposisi penyelenggara pemilu. Adakalanya, calon legislatif lebih nyaman berkonsultasi tentang kepemiluan dengan penyelenggara pemilu perempuan dibanding harus berbaur dengan komisioner laki-laki.
Dan pada akhirnya, potret rekrutmen Panwascam tahun ini menjadi peluit peringatan ultrasonik bagi segenap pemangku kepentingan. Sekuat apa pun sistem yang dibangun untuk mengafirmasi kesetaraan perempuan, harus dibarengi dengan kesiapan SDM, sosialisasi masif, dan kesadaran bersama. Sebab, irama merdu hanya akan terdengar apabila si bisu bersuara lantang, dan si tuli mengorek kuping.(*)