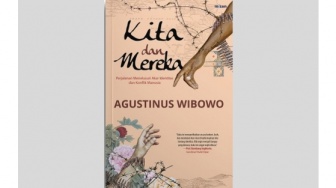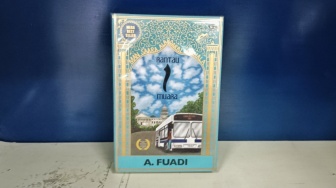Komentar kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara beberapa waktu lalu menjadi salah satu contoh nyata betapa pentingnya etika berbahasa bagi pejabat publik.
Kejadian ini menimbulkan kegaduhan dan melukai hati banyak pihak, khususnya para guru, yang merasa profesinya direndahkan. Fenomena ini bukanlah yang pertama, dan sayangnya, sering kali terulang.
Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan pemahaman. Bagi seorang pejabat publik, yang kata-katanya mewakili otoritas dan kebijakan, setiap ucapan memiliki bobot yang signifikan.
Ingat kembali UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 25 undang-undang yang secara tegas menyebutkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam segala komunikasi yang terjadi di forum resmi nasional, yang mencakup berbagai kegiatan di ruang publik.
Seorang pejabat publik, yang merupakan representasi dari negara, seharusnya memiliki kecakapan komunikasi yang mumpuni. Setiap kata yang terucap, apalagi di ruang publik, memiliki dampak yang besar.
Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai cerminan dari pola pikir, sikap, dan etika seseorang.
Ketika seorang pejabat memilih kata yang tidak tepat atau bahkan merendahkan, ia tidak hanya menciptakan kesalahpahaman, tetapi juga dapat merusak kredibilitas institusi yang diwakilinya.
Kasus Sri Mulyani adalah pelajaran berharga. Meskipun kemudian dijelaskan bahwa konteks "beban" yang dimaksud adalah beban fiskal atau anggaran, pilihan kata tersebut tetaplah kurang bijak dan tidak sensitif.
Mengapa? Karena dalam bahasa sehari-hari, "beban" memiliki konotasi negatif yang kuat, yaitu sesuatu yang memberatkan atau merepotkan. Penggunaan istilah ini di hadapan khalayak umum menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap perasaan dan peran strategis para guru sebagai pilar pembangunan bangsa.
Ketidakmampuan pejabat dalam memilih diksi atau tata bahasa yang tepat bisa berujung pada konsekuensi fatal. Pertama, menimbulkan kegaduhan dan polemik yang tidak perlu. Alih-alih fokus pada substansi kebijakan, energi publik terkuras untuk membahas kontroversi yang berakar dari kesalahan berbahasa.
Kedua, melukai dan menyinggung perasaan kelompok tertentu, seperti yang terjadi pada kasus guru. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan jarak emosional antara rakyat dan para pemimpinnya.
Ketiga, menurunkan wibawa dan kredibilitas pejabat itu sendiri. Masyarakat akan mempertanyakan kapasitas dan profesionalisme mereka jika terus-menerus melakukan kesalahan yang sama.
Kasus Sri Mulyani hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Masih teringat bagaimana beberapa pejabat lain juga pernah melontarkan pernyataan yang kontroversial karena pilihan kata yang tidak tepat.
Mulai dari pernyataan yang terkesan meremehkan masalah sosial hingga komentar yang berbau seksisme atau stereotip. Semua kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan abai terhadap pentingnya retorika publik yang bijaksana dan beretika.
Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah pernyataan "Ndasmu etik!". Kalimat ini dilontarkan Prabowo dalam sebuah kongres internal partai Gerindra pada Desember 2023, sebagai respons terhadap pertanyaan tentang etika yang diutarakan Anies Baswedan dalam debat calon presiden.
Diksi ini sontak menjadi viral dan memicu perdebatan luas di masyarakat. Banyak pihak menilai penggunaan kata yang berasal dari bahasa Jawa, "ndas" (kepala), yang memiliki konotasi kasar, tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh nasional.
Banyak pihak menilai penggunaan kata yang berasal dari bahasa Jawa, "ndas" (kepala), yang memiliki konotasi kasar, tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh nasional.
Meskipun juru bicaranya mengklarifikasi bahwa itu hanya candaan, banyak kritikus berpendapat bahwa candaan seperti itu tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang calon pemimpin yang sedang berupaya mendapatkan kepercayaan publik.
Selain itu, Prabowo juga pernah menggunakan diksi-diksi lain yang memancing reaksi publik. Contohnya, dalam sebuah acara, Prabowo melontarkan kata-kata seperti "tolol" dan "goblok" ketika mengkritik pihak yang dianggapnya tidak memahami masalah bangsa, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam.
Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap merendahkan lawan politik dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya mengedepankan debat substansial dan narasi yang konstruktif.
Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ucapan mereka. Mereka tidak bisa sembarangan berdalih bahwa "konteksnya berbeda" setelah pernyataan mereka menimbulkan kegaduhan. Seharusnya, sebelum berbicara, mereka sudah memikirkan dengan matang bagaimana pesan tersebut akan diterima oleh masyarakat luas.
Masalahnya bukan lagi soal melukai perasaan dan bahasa itu sendiri, tetapi bagaimana pengaruhnya ketika ditiru oleh publik. "Pejabatnya saja bisa ngomong gitu, kenapa kita harus santun?"
Ketika ini terjadi, bukankah peran pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah menjadi penting? Tidak bisa dimungkiri, bagi segelintir orang, pelajaran ini dianggap remeh karena dalih bahasa sehari-hari, padahal mereka lupa ada aneka aturan yang membungkus bahasa itu yang mungkin tidak dipelajari di kehidupan sehari-hari, tetapi harus dipelajari begitu dalam di buku-buku dan sekolah.
Sesungguhnya, penting bagi para pejabat dan kita sendiri sebagai warga Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan komunikasi publik mereka.
Instansi pemerintah seharusnya menyediakan pelatihan khusus mengenai hal ini. Selain itu, kesadaran diri dan empati juga menjadi kunci. Seorang pejabat harus mampu menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum mengeluarkan pernyataan.
Intinya, dalam berkomunikasi, kesan yang diterima lebih penting daripada niat yang dimaksud. Pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah dan tata bahasanya.
Dengan begitu, komunikasi antara pemerintah dan rakyat akan terjalin dengan lebih harmonis, minim kesalahpahaman, dan yang terpenting, tidak ada lagi pihak yang merasa direndahkan.