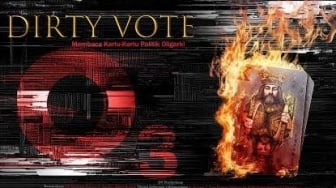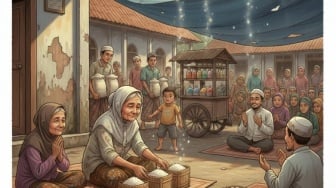Figur Ki Hajar Dewantara bagi sebagian besar kalangan mungkin sekadar terkenal sebagai tokoh pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Nama besarnya selalu lekat dengan Taman Siswa, sebuah pionir institusi pendidikan berbasis budaya di negeri ini. Namun, sejatinya Ki Hajar juga merupakan seorang figur politisi ulung.
Tarikh sejarah peradaban bangsa Indonesia di masa pergerakan menunjukkan bahwa Ki Hajar muda adalah seorang yang bermazhab radikal. Sosok kelahiran tanggal 2 Mei 1889 ini aktif di dalam pelbagai kegiatan perpolitikan dengan asas non-kooperatif. Ki Hajar dan kolega menolak berkompromi dengan Pemerintah Hindia Belanda. Tak pelak, aktivitas perpolitikan Ki Hajar pada akhirnya membuat beliau senantiasa berada dalam sensor pemerintah.
Karir perpolitikan Ki Hajar bermula sejak beliau ngangsu kawruh di STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) atau semacam sekolah dokter untuk pribumi. Selama di STOVIA, api politik radikal dalam diri Ki Hajar kian membara berkat diskusi intimnya dengan E.F.E Douwes Dekker. Saat menginjak tahun kelima studinya di STOVIA, berdirilah organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia bernama Budi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908.
Ki Hajar memang tidak semoncer Soetomo perihal lahirnya BO ini. Namun, standing point beliau pastilah berada di lingkaran para elite BO. Inisiatif Ki Hajar tentang penyelenggaraan kongres pertama BO di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908 bahkan mendapat sambutan positif. Kongres tersebut berhasil menetapkan dasar-dasar sebuah organisasi modern sekaligus pernyataan sikap tentang BO sebagai organisasi non-politik.
Namun, apakah BO telah sesuai dengan pikiran besar seorang Suryaningrat muda?
Menginisiasi Indische Partij
![Hi Hadjar Dewantara sedang berpidato dalam Sidang Rapat Besar VIII.[ist/circa 1950]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/31/83742-hi-hadjar-dewantara-sedang-berpidato-dalam-sidang-rapat-besar-viiiistcirca-1950.jpg)
Hati Ki Hajar gundah. Ia merasa bahwa BO belum cukup untuk menentang kolonialisme. Ia menginginkan sebuah kendaraan yang berani bersikap radikal terhadap pemerintah serta vokal tanpa tedheng aling-aling. Karenanya, bersama dua rekan karibnya, E.F.E Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar mendirikan Indische Partij (IP) pada 25 Desember 1912. Tiga karib sepemikiran itu lantas menjelma menjadi tri tunggal yang masyhur dikenang sejarah sebagai Tiga Serangkai. Di bawah kepemimpinan ketiganya, IP tampil ke gelanggang sejarah sebagai partai politik pertama di masa pemerintahan Hindia Belanda.
Pada salah sebuah pertemuan IP di Bandung, E.F.E Douwes Dekker yang kemudian hari mengkonversi namanya menjadi Danudirja Setiabudi menyatakan pendirian IP sebagai sebuah statement perang. Pidato Danudirja yang mesti diamini dua kompatriotnya itu merupakan sebuah identitas verbal akan arah pergerakan IP yang radikal, kontra penjajahan, serta non-kooperatif.
Menariknya, suara berani yang menggema lewat aktivitas-aktivitas IP justru berhasil menjaring dukungan publik. Catatan WS Utomo (2014) menyebut bahwa hingga tahun 1912 saja, anggota IP telah mencapai 7000 orang. Angka ini terbilang gila di zaman saat kesadaran akan kemerdekaan baru saja hinggap di pikiran kalangan terpelajar pribumi.
Progresivitas dan semangat juang IP di bawah komando Ki Hajar dan kolega pada akhirnya membuat pemerintah gusar. Terlebih, selepas terbitnya tulisan Ki Hajar bertitel Als Ik Nederlander Was atau Jika Aku Seorang Belanda, amarah pemerintah Hindia Belanda tak lagi bisa direm. Ki Hajar dan dua sahabat sepergerakannya itu mendapat dakwaan penyimpangan jurnalistik. Orang sekarang mungkin menyebutnya hoax atau hate speech.
Namun, bila mencermati sepak terjang revolusioner yang diusung IP, dakwaan tersebut tak lain sekadar sebuah bukti kekhawatiran. Pemerintah kala itu tak lebih dari seekor singa ompong yang kumisnya lekas ter-obong dan bingung mencari penolong. Apilah yang akhirnya dipersalahkan!
Ketakutan pemerintah kian hari kian membuncah. IP telah menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang menggerakkan tumbuhnya nasionalisme kebangsaan. Robert Elson (2008) seperti dicatut WS Utomo (2014) bahkan secara tegas menyatakan bahwa IP memiliki kontribusi yang lebih krusial ketimbang BO dalam hal menyemai bibit-bibit nasionalisme. IP telah menancapkan pasak tangguh bagi bulatnya suara nasionalisme yang dua dasawarsa selanjutnya menjelma dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Pada akhirnya, IP mesti dibubarkan. Ketiga motor penggerak IP menerima hukuman pengasingan ke Belanda demi membendung gelombang nasionalisme yang kian membesar. Nahas bagi Ki Hajar, statusnya sebagai bangsawan membuat hukuman yang ia terima lebih diperberat (Utomo, 2014). Beliau mendapat hukuman dari dua gelombang. Pemerintah mencapnya sebagai seorang anarkis, sedang para bangsawan menganggap Ki Hajar telah merusak tatanan unggah-ungguh dan laku utami.
Memadukan akal budi dan nurani
![Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato pada pembukaan kongres Tamansiswa.[Ist/Reprod]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/31/61002-ki-hadjar-dewantara-menyampaikan-pidato-pada-pembukaan-kongres-tamansiswaistreprod.jpg)
Meskipun memiliki arah pergerakan yang radikal dan non-kooperatif, Ki Hajar Dewantara justru berhasil menyelerasakan anatara akal budi (reasons) dan nurani (consciousness) di dalam sikap politiknya. Akal budi dan nurani yang melekat pada diri manusia bagi Ki Hajar merupakan senjata yang mesti berdaya guna untuk membangun sebuah identitas kebangsaan.
Akal budi atau nalar merupakan sebuah tuntutan yang muncul pada figur yang telah mencapai usia dewasa. Saat Ki Hajar menginjak masa dewasanya di STOVIA, ia sadar akan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Organisasi, jurnalisme, serta kritik lisan maupun tulisan merepresentasikan komitmen akal budi Ki Hajar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu.
Sementara, catatan Nayono et al (1994) sebagaimana dikutip Bambang Purwanto (2021) menyebut bahwa Ki Hajar memandang batin atau nurani sebagai akar tumbuhnya kesadaran untuk memperjuangkan kehormatan bangsanya. Kehormatan bangsa sebanding harganya dengan kehormatan pribadi. Artinya, selagi bangsanya terjajah, semerdeka dan semakmur apapun seseorang, tetap ia tidak terhormat.
Ajaran tersebut berhasil membangkitkan semangat pergerakan dari dalam diri pribadi anak bangsa. Berbeda dengan pendekatan kolektif komunal ala BO, sentuhan personal yang dihadirkan Ki Hajar mampu menyalakan api semangat nasionalisme dengan visi Indonesia inklusif.
Demikianlah jalan politik terjal yang ditempuh Ki Hajar. Beliau merupakan figur yang berani mendobrak sekat-sekat yang mengkotaki dirinya sendiri. Andai Ki Hajar lebih memilih hidup nyaman sebagai aristokrat kraton, mestilah beliau tak akan pernah merasakan dinginnya meja hijau serta hampanya pengasingan. Namun, jikalau itu yang Ki Hajar pilih, barangkali hingga hari ini kita masih menjadi jongos! Kita masih senantiasa terejek sebagai "een volk van koelies en een koelie onder de natie."
Jadi, mari kita lanjutkan pijar semangat Ki Hajar agar senantiasa berpendar merasuki jiwa-jiwa generasi muda!