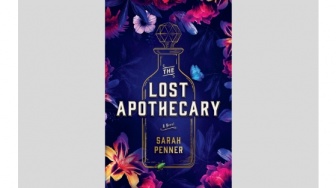Di sebuah ruangan steril dengan meja melingkar, para pejabat berseragam rapi sedang berdiskusi tentang kurikulum baru. Proyektor menyala, slide demi slide berisi istilah asing terlihat begitu saja. Di pojok ruangan, seorang pria tua berpeci dan berkebaya Jawa duduk diam, tak ada yang menoleh, tak ada yang menyapa, dan tak ada yang mengundangnya bicara.
Ia adalah Ki Hadjar Dewantara.
Tokoh yang dulu menggagas pendidikan nasional Indonesia kini hanya menjadi poster di dinding sekolah, kutipan dalam buku pelajaran yang dibacakan tanpa makna, dan nama yang diperingati setahun sekali dalam upacara Hari Pendidikan Nasional.
Padahal, dalam darahnya mengalir api perlawanan terhadap kolonialisme dan dalam pemikirannya tertanam akar pendidikan yang membebaskan.
Namun hari ini, ia tidak akan diundang dalam rapat kurikulum.
Ki Hadjar bukan sekadar tokoh pendidik. Ia adalah pejuang politik. Seorang kolumnis yang dengan berani menulis kritik tajam terhadap kebijakan Belanda lewat artikel “Als Ik een Nederlander Was” (Seandainya Saya Belanda), yang membuatnya diasingkan ke Belanda.
Dari pengasingan itu, ia menyusun gagasan besar tentang pendidikan sebagai alat perjuangan. Ia tidak sekadar mengajar membaca dan berhitung. Ia mendidik untuk merdeka.
Taman Siswa, lembaga yang ia dirikan, bukan hanya sekolah. Ia adalah ruang perlawanan. Tempat membentuk manusia merdeka yang berpikir, bertindak, dan merasa sebagai bagian dari bangsanya.
Ki Hadjar meyakini pendidikan harus berpijak pada kebudayaan, pada kenyataan sosial, dan pada kemanusiaan. Prinsipnya terkenal: Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan).
Tapi hari ini, siapa yang benar-benar tahu artinya?
Seandainya Ki Hadjar hidup hari ini dan masih mengajar, ia mungkin dipecat. Dianggap tidak relevan dengan zaman. Ia tidak akan mematuhi format administrasi absurd yang membuat guru lebih sibuk menyalin rencana pembelajaran ke berbagai template daripada mengajar. Ia tidak akan peduli akreditasi, angka, atau rangking. Ia akan mencoret kata “asesmen” dan menggantinya dengan “pembebasan.”
Ia akan menolak mengajar lewat Google Classroom kalau muridnya tidak punya HP. Ia akan duduk lesehan bersama anak-anak di teras sekolah, berdiskusi tentang sawah, pasar, dan harga beras. Ia akan membawa anak-anak jalan kaki ke kampung untuk melihat langsung bagaimana masyarakat hidup, dan dari situlah ia membangun pelajaran.
Dan sistem akan bingung. Karena sistem tidak mengenal kebebasan. Sistem hanya mengenal target, angka, dan statistik. Sistem tidak dirancang untuk membentuk manusia merdeka. Ia dirancang untuk mencetak tenaga kerja. Maka, Ki Hadjar dianggap usang.
Apa yang lebih menyakitkan dari dilupakan? Dimuseumkan.
Ki Hadjar telah menjadi simbol mati. Namanya disematkan di gedung-gedung, tapi semangatnya tidak diwarisi. Pidato-pidatonya dipotong untuk sekadar kutipan manis. Pendidikan hari ini tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan murid, melainkan mengejar akreditasi dan sertifikasi.
Ki Hadjar akan kecewa. Tapi ia tidak akan marah. Ia akan berjalan pelan ke ruang guru, mendengarkan keluhan guru honorer yang gajinya tak cukup untuk ongkos, mendengar anak-anak yang berhenti sekolah karena harus bantu orang tua, melihat murid yang tak pernah ditanya apakah ia bahagia. Ia akan menulis lagi. Tapi tulisannya takkan dimuat. Terlalu tajam. Terlalu politis. Terlalu jujur.
Dan kita, para pendidik dan murid zaman ini, mungkin akan merasa risih. Karena kehadiran Ki Hadjar adalah cermin. Ia memperlihatkan bahwa kita telah gagal melanjutkan perjuangannya. Kita membuat anak-anak duduk diam selama delapan jam, menghafal materi yang bahkan gurunya sendiri tak paham maknanya.
Kita mengajarkan “nilai-nilai Pancasila” tanpa memberi ruang untuk bertanya. Kita menghukum yang bertanya terlalu banyak. Kita menyuruh anak jadi kreatif, tapi menyamaratakan semua tugas. Kita ingin anak kritis, tapi tidak memberi ruang untuk berbeda pendapat.
Bayangkan jika Ki Hadjar diberi satu jam mengajar hari ini di sebuah SMA negeri. Ia tidak akan membawa power point. Ia tidak akan menanyakan nilai ujian. Ia akan bertanya, “Apa yang kalian takutkan?” Dan ruang kelas akan hening. Karena itu bukan soal pilihan ganda.
Lalu ia akan berkata bahwa pendidikan bukan untuk menjadi juara kelas, tapi menjadi manusia. Bahwa tugas guru bukan menyuruh, tapi menemani. Bahwa belajar bukan soal hafalan, tapi pengalaman. Dan para siswa akan terdiam. Sebagian mungkin tertawa. Tapi sebagian akan mulai berpikir.
Dan itulah pendidikan. Bukan sekadar sekolah.
Tapi sekali lagi, ia tidak akan diundang dalam rapat kurikulum hari ini. Ia terlalu revolusioner. Ia terlalu membahayakan status quo. Ia tidak bisa dilobi oleh vendor pelatihan. Ia tidak bisa dibungkam dengan jabatan. Ia tidak akan diam ketika melihat pendidikan hanya menjadi alat seleksi, bukan alat pembebasan.
Maka lebih aman jika ia dijadikan patung. Lebih mudah jika ia hanya dikenang, bukan diikuti.
Pendidikan kita hari ini kehilangan arah bukan karena tidak punya kurikulum, tapi karena kehilangan keberanian. Kita takut jika anak-anak bertanya terlalu dalam.
Kita takut jika guru menolak tunduk pada birokrasi. Kita takut jika sekolah menjadi tempat berpikir bebas. Padahal justru di sanalah letak merdeka belajar yang sesungguhnya.
Ki Hadjar tidak akan memaki. Tapi ia akan bertanya, “Untuk siapa sekolah ini dibangun? Untuk siapa pendidikan ini diciptakan?”
Dan kita akan kesulitan menjawab.
Karena jawabannya sudah lama kita tinggalkan.
Di luar ruang rapat kurikulum, Ki Hadjar akan berjalan sendiri. Tidak ada yang melambaikan tangan. Tidak ada yang memanggil.
Tapi langkahnya tetap pelan, pasti, dan merdeka. Karena ia tahu, meski tubuhnya tidak diundang, pikirannya akan selalu gentayangan di benak siapa pun yang masih percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemanusiaan yang utuh.
Dan bagi mereka yang masih mau mendengar, suara Ki Hadjar akan selalu ada: “Jangan jadikan sekolah sebagai tempat memenjarakan pikiran. Jadikan ia rumah bagi kebebasan yang bertanggung jawab.”
Tapi untuk hari ini, rapat kurikulum tetap berjalan. Tanpa dia.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS