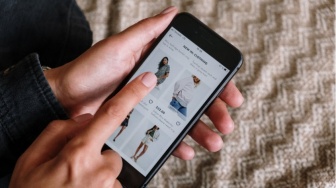Kolom
Bara Dewantara: Menantang Politik Bangsa dari Bangku Kuliah

Sebagai mahasiswa semester enam, bagian dari generasi Z yang melek politik dan lahir di tengah pusaran teknologi, saya memandang perjuangan Ki Hadjar Dewantara sebagai bara yang masih menyala, menantang kami untuk menggugat kemapanan politik bangsa. Warisan politiknya, yang menjadikan pendidikan sebagai senjata emansipasi, bukan hanya inspirasi, tetapi juga cambuk bagi kami yang resah melihat demokrasi Indonesia terjebak dalam pragmatisme, korupsi, dan polarisasi. Dengan lensa kritis, melalui tulisan ini saya ingin membedah relevansi perjuangan Ki Hadjar Dewanatara dalam menghadapi krisis politik kontemporer, sembari menegaskan bahwa generasi muda harus berani mengambil alih narasi kebangsaan tanpa mengkhianati akar budaya.
Perjuangan Ki Hadjar lahir dari darah dan api semangat anti-kolonialisme. Melalui Taman Siswa dan keberaniannya dalam Indische Partij, beliau menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membangunkan rakyat dari belenggu penjajahan, baik fisik maupun intelektual. Namun, di Indonesia kini, pendidikan telah dirampok maknanya, menjadi mesin birokratis yang melayani pasar, bukan rakyat. Politik, yang seharusnya menjadi wadah aspirasi kolektif, malah dikuasai elit yang memainkan narasi populis di media sosial untuk mempertahankan kuasa. Akar masalahnya adalah pengkhianatan terhadap visi Ki Hadjar Dewantara: pendidikan dan politik telah dipisahkan, meninggalkan rakyat dalam kebodohan politik dan apatisme. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai pelecehan terhadap cita-cita kemerdekaan.
Visi Ki Hadjar tentang pendidikan sebagai jalan menuju kesadaran politik terasa seperti seruan perang di tengah krisis demokrasi saat ini. Prinsip “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” adalah manifesto kepemimpinan yang anti-elitis, yang mengutamakan pemberdayaan rakyat. Namun, politik Indonesia kini adalah teater oligarki, di mana rakyat hanya menjadi penonton. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat demokratisasi, malah memperparah polarisasi dengan hoaks dan algoritma yang memenjarakan kita dalam gelembung informasi. Sebagai Gen Z yang kritis, saya mempertanyakan: jika Ki Hadjar mampu membangun Taman Siswa di tengah represi kolonial, mengapa kami, dengan segala teknologi dan kebebasan, masih terjebak dalam siklus politik yang manipulatif?
Untuk menghidupkan kembali semangat Ki Hadjar Dewantara tidak bisa ditunda. Krisis literasi politik di kalangan generasi saya bukan sekadar masalah pendidikan, tetapi ancaman eksistensial bagi demokrasi. Tanpa kesadaran kritis, kami rentan dimanipulasi oleh narasi politik yang memecah belah, seperti yang terjadi dalam berbagai pemilu baru-baru ini. Ki Hadjar mengajarkan bahwa pendidikan harus melahirkan manusia merdeka, yang mampu mengenali hak dan tanggung jawabnya. Namun, pendidikan tinggi yang saya jalani sering kali steril dari diskursus politik, lebih fokus pada keterampilan teknis ketimbang kepekaan sosial. Ini adalah kegagalan sistemik yang memperlemah daya tawar generasi muda dalam mengubah arah politik bangsa.
Tantangan untuk mewujudkan visi Ki Hadjar Dewantara di era digital sangatlah kompleks. Sistem pendidikan yang terpusat dan terobsesi pada metrik akademik telah mematikan kreativitas dan jiwa kritis mahasiswa. Di sisi lain, politik yang didominasi oleh dinasti dan kepentingan jangka pendek membuat suara anak muda sering diabaikan. Namun, sebagai Gen Z, kami memiliki keunggulan: teknologi adalah medan perang kami. Kami bisa menggunakan platform digital untuk membangun “Taman Siswa virtual,” menyebarkan pendidikan politik yang berbasis budaya lokal, seperti nilai kebhinekaan dan gotong royong. Yang terpenting, kami harus berani keluar dari zona nyaman, turun ke jalan, dan terlibat langsung dalam advokasi, sebagaimana Ki Hadjar pernah melawan penjajah dengan pena dan tindakan.
Langkah konkret harus segera diambil untuk menerjemahkan semangat Dewantara ke dalam aksi. Pertama, kampus harus menjadi laboratorium demokrasi, dengan mata kuliah yang mendorong analisis kritis terhadap isu politik dan budaya. Kedua, kami sebagai mahasiswa harus membentuk komunitas daring dan luring untuk mendidik rakyat tentang hak politik mereka, menggunakan bahasa yang relevan bagi Gen Z tanpa mengorbankan substansi. Ketiga, kolaborasi dengan organisasi budaya lokal dapat memperkuat narasi kebangsaan yang inklusif, menandingi narasi global yang sering mengikis identitas. Dengan langkah ini, politik tidak lagi menjadi permainan elit, tetapi gerakan rakyat yang hidup di tangan anak muda.
Bara perjuangan Ki Hadjar Dewantara adalah panggilan bagi kami, generasi Z, untuk tidak sekadar menjadi penutur kritik, tetapi pelaku perubahan. Di tengah krisis politik yang mengoyak bangsa, visinya tentang pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan batin adalah senjata paling ampuh. Dengan teknologi sebagai alat dan budaya sebagai akar, kami harus berani menggugat kemapanan, merobek tirai manipulasi, dan merajut kembali politik bangsa yang berpihak pada rakyat. Dari bangku kuliah, saya bermimpi melihat Indonesia yang tidak hanya merdeka secara lahiriah, tetapi juga batiniah—sebuah bangsa yang hidup dalam cahaya keadilan, persatuan, dan martabat. Bara itu kini ada di tangan kami, tinggal bagaimana kami menyulutnya.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.