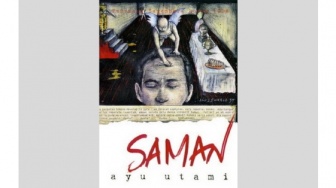Ki Hadjar Dewantara dikenal luas sebagai Bapak Pendidikan Nasional, namun sedikit yang menyoroti perannya sebagai tokoh politik yang lantang melawan kolonialisme. Melalui tulisannya yang tajam dan lembaga pendidikan Taman Siswa, ia menyatukan perjuangan intelektual dan politik dalam satu napas. “Pendidikan harus memerdekakan manusia,” tulisnya dalam buku “Ki Hajar Dewantara Pemikiran dan Perjuangannya”.
Sebagai pendiri Indische Partij bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo, Ki Hadjar menunjukkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan dapat dilakukan melalui jalan pemikiran dan pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks Indonesia kini, ketika pendidikan sering terjebak dalam birokratisasi dan politik kerap kehilangan arah etis, penting untuk bertanya: bagaimana nilai-nilai perjuangan politik Ki Hadjar dapat direfleksikan dalam kondisi saat ini?
Tulisan ini bertujuan untuk menggali kembali relevansi perjuangan Ki Hadjar Dewantara, baik sebagai pendidik maupun politikus, dan menilainya dalam konteks sosial-politik Indonesia kontemporer.
Pada masa kolonial, Ki Hadjar Dewantara aktif dalam pergerakan politik bersama tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo melalui organisasi Indische Partij, yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi pribumi. Salah satu bentuk perlawanan politiknya yang terkenal adalah tulisan berjudul “Als Ik een Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda), yang mengecam ketidakadilan penjajahan Belanda. Dalam tulisannya, ia menyindir tajam sikap kolonial yang memaksakan perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan:
“Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan di negeri yang masih kami rampas kemerdekaannya.”
Tulisan ini mengakibatkan pemerintah kolonial membuang Ki Hadjar ke Belanda. Namun justru di sana, ia mendalami pemikiran tentang pendidikan progresif dan menemukan bahwa pendidikan dapat menjadi alat strategis untuk membebaskan dan membentuk kesadaran bangsa.
Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi sarana perjuangan politik yang membebaskan. Melalui lembaga Taman Siswa yang ia dirikan pada 1922, ia menanamkan filosofi kepemimpinan yang membumi:
"Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani"
Artinya seorang pemimpin harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan mendorong dari belakang.
Pendidikan menurutnya adalah jalan menuju kemandirian bangsa, bukan sekadar untuk mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia merdeka. Ia juga menulis:
“Anak-anak harus dididik agar menjadi manusia merdeka dalam berpikir, merdeka dalam perasaan, dan merdeka dalam kemauan.”
Alih-alih memilih konfrontasi bersenjata, Ki Hadjar memilih jalur perjuangan non-kekerasan melalui pemikiran, budaya, dan pendidikan yang mencerdaskan. Strategi ini menjadi cara revolusioner untuk melawan penjajahan secara moral dan intelektual.
Dalam era globalisasi dan modernisasi yang serba cepat, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Komersialisasi pendidikan telah menggeser esensi sejatinya sebagai alat pembebasan menjadi sekadar komoditas ekonomi. Institusi pendidikan kerap kali tidak lagi menjadi ruang pembentukan karakter, melainkan tempat mengejar gelar, status, dan keuntungan finansial. Politisasi pendidikan pun marak terjadi, baik dalam penentuan kebijakan hingga pengangkatan pejabat pendidikan, yang sering kali tidak berpijak pada kualitas dan integritas.
Sementara itu, dunia politik Indonesia juga mengalami gejala pragmatisme akut, di mana idealisme perjuangan seperti yang pernah diusung Ki Hadjar Dewantara nyaris terpinggirkan. Etika dan nilai-nilai kebangsaan tidak lagi menjadi fondasi utama, tergantikan oleh kepentingan jangka pendek, elektabilitas, dan transaksionalisme kekuasaan. Dalam situasi inilah, pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi sangat relevan untuk dihidupkan kembali. Ia pernah menegaskan bahwa:
“Tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan manusia: merdeka pikirannya, merdeka perasaannya, dan merdeka kemauannya.”
Pernyataan ini mencerminkan pandangannya bahwa pendidikan harus menumbuhkan manusia seutuhnya—yang berpikir kritis, beretika, dan memiliki daya juang moral. Jika pendidikan kehilangan arah ini, maka bangsa pun akan kehilangan karakternya. Lebih dari itu, pendidikan dalam pemikiran Ki Hadjar bukan hanya soal mengajar, tetapi membangun peradaban. Ia menyatakan:
“Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar kepandaian, jika tidak dibarengi budi pekerti, maka ia tidak akan menjadi manusia yang sejati.”
Dari sinilah terlihat bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi tentang pemulihan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam politik. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan yang memberi teladan adalah warisan pemikiran Ki Hadjar yang harus diintegrasikan kembali dalam sistem politik kita.
Maka, pembaruan sistem pendidikan berbasis karakter menjadi kebutuhan mendesak. Kurikulum dan kebijakan pendidikan harus dirancang untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Di sisi lain, kepemimpinan politik pun perlu belajar dari filosofi Ki Hadjar: menuntun, bukan memaksakan; membangun dari dalam, bukan mendikte dari atas.
Ki Hadjar Dewantara bukan hanya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tetapi juga sebagai seorang visioner yang meletakkan dasar-dasar pemikiran politik kebangsaan yang berakar pada etika, kebudayaan, dan kemanusiaan. Melalui pendidikan, ia membangun jalan perjuangan yang halus namun revolusioner untuk mencetak manusia merdeka sebagai pondasi bagi bangsa yang berdaulat.
Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, pemikiran Ki Hadjar menjadi semakin relevan. Harapannya, generasi muda dan para pemimpin bangsa masa kini dapat meneladani semangat perjuangannya agar dapat membangun Indonesia melalui pendidikan yang membebaskan dan bermartabat, serta politik yang menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai kemanusiaan.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.