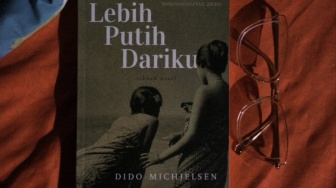Bayangin gini: kamu lagi jalan kaki di sekitar Masjidil Haram, di tengah lautan manusia dari segala penjuru dunia, dan tiba-tiba kamu ngelihat warteg, tukang bakso, dan spanduk bertuliskan “Diskon oleh-oleh haji, asli dari Cirebon”. Kamu lagi di Mekkah, tapi kok rasanya kayak di Tanah Abang?
Itulah kira-kira gambaran awal yang muncul ketika Presiden Prabowo menyebutkan rencananya membangun “Kampung Indonesia” di dekat Masjidil Haram.
Konsep ini, katanya, udah dibicarakan langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), dan kabarnya disambut cukup positif. Bahkan Menteri Agama udah diminta untuk menindaklanjuti. Sekilas, terdengar keren dan nasionalistik.
Tapi… emang perlu ya?
Mari kita kupas perlahan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya kita sebagai warga muda bisa mikir bareng—apa yang sebenarnya sedang ditawarkan di balik gagasan ini?
Pertama-tama, kita perlu bertanya: ide membangun kampung haji Indonesia di Mekkah itu untuk siapa, dan demi apa? Kalau niatnya memudahkan jemaah haji dan umrah—dalam hal akomodasi, makanan, bahasa, atau bahkan logistik—itu niat baik, tentu.
Tapi bukankah secara teknis hal-hal itu udah ada solusinya lewat regulasi haji yang makin ketat dan layanan travel resmi yang makin banyak?
Lagi pula, konsep "kampung" ini, meski terdengar hangat dan akrab, bisa juga menjebak kita pada nostalgia palsu. Apa jadinya kalau orang Indonesia ke tanah suci tapi masih makan rendang, belanja batik, ngobrol pakai Bahasa Indonesia, lalu pulang dengan pengalaman “internasional” yang sebenarnya lokal juga?
Ibarat kamu ke Jepang tapi nginep di hotel yang dekorasinya serba Nusantara, makannya nasi padang, dan tur guidenya orang Bekasi. Niat awalnya jalan-jalan, tapi akhirnya cuma pindah kamar ke versi global.
Data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) per 2024 menunjukkan bahwa dana haji Indonesia yang dikelola mencapai lebih dari Rp165 triliun. Tapi antrean berangkat haji masih belasan bahkan puluhan tahun. Banyak warga tua yang akhirnya wafat sebelum sempat mencium Hajar Aswad.
Dalam kondisi ini, bukankah seharusnya energi pemerintah difokuskan pada bagaimana mempercepat dan mengefisienkan layanan haji, daripada membangun properti di luar negeri yang jelas akan butuh biaya besar dan proses panjang—bahkan bisa jadi sangat politis?
Pertanyaan lanjutan: ini pakai duit siapa? Kalau APBN atau dana publik yang dipakai, kita punya hak untuk bertanya lebih keras. Jangan-jangan ini proyek mercusuar yang ujung-ujungnya cuma jadi bangunan kosong yang dipoles-poles buat pencitraan.
Yang kita perlukan bukan kampung Indonesia di Arab Saudi, tapi akal sehat dan kebijakan yang membumi di Indonesia. Gimana caranya agar biaya umrah tidak mencekik? Gimana agar calo-calo visa ilegal tidak menipu jemaah? Gimana agar jemaah tidak kelelahan karena sistem transportasi lokal yang semrawut?
Jangan-jangan “kampung Indonesia” ini hanyalah kosmetik politis: strategi branding yang terlihat nasionalis, padahal fungsionalitasnya bisa dipertanyakan.
Kalau kita jujur, ini bukan pertama kalinya Indonesia punya mimpi “besar di luar negeri”. Kita pernah bangga dengan proyek-proyek monumen dan kerja sama internasional yang katanya “meningkatkan citra bangsa”. Tapi percuma citra naik, kalau infrastruktur dalam negeri keropos, pendidikan tertinggal, dan masyarakat makin sulit beli beras.
Membangun reputasi itu penting, tapi jangan sampai jadi overcompensating alias "menutupi kekurangan internal dengan kesuksesan simbolik eksternal".
Daripada sibuk bikin kampung Indonesia di luar negeri, kenapa nggak fokus membangun kampung-kampung di negeri sendiri yang masih jauh dari layak? Di Papua, di pelosok Kalimantan, di pesisir-pesisir Sumatera, masih banyak yang bahkan belum merasakan air bersih, apalagi layanan kesehatan memadai.
Gagasan “kampung Indonesia” di Mekkah memang terdengar wah. Tapi jangan biarkan pesona retorika menutupi pertanyaan paling sederhana: ini sebenarnya siapa yang butuh, siapa yang untung, dan siapa yang bayar?
Kalau jawabannya mengambang, mungkin kita harus belajar untuk lebih skeptis. Karena kebijakan yang baik bukan yang terlihat bagus di headline berita, tapi yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di garis depan.
Dan buat generasi muda yang udah mulai sadar pentingnya akuntabilitas, mari terus tanyakan, kritik, dan dorong kebijakan agar tetap waras.
Karena kadang yang kelihatan religius, belum tentu rasional. Dan yang kelihatan nasionalis, bisa saja cuma... narsistik.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS