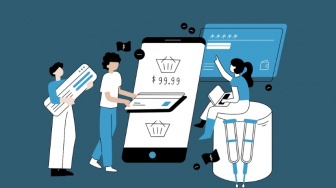Tiap tahun ajaran baru, kalender pendidikan Indonesia punya tradisi yang tidak bisa dilewatkan, yaitu kisruh penerimaan peserta didik baru. Mulai dari antrean subuh yang mengalahkan antrean BTS meal, sistem digital yang down bak server promo e-commerce 11.11, hingga praktik “salaman hangat” yang mendadak bikin kursi sekolah jadi lebih empuk bagi yang punya amplop.
Kini, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diganti nama menjadi SPMB (Seleksi Peserta Masuk Belajar). Sebuah akronim yang terdengar segar, tapi apakah ini permainan semantik semata untuk menenangkan publik? Atau benar-benar langkah strategis ala reformasi pendidikan Finlandia?
Ibarat mengganti nama toko dari “Warung Sederhana” menjadi “Cafe Edukasi”, tapi tetap jualan kopi sachet dan gorengan semalam. Esensi yang tak berubah, hanya kemasannya yang lebih Instagrammable. Maka dari itu, mari kita bedah: apakah ini transformasi substansial atau sekadar rebranding tahunan dari kementerian?
Kisruh PPDB/SPMB, Drama Tahunan Tanpa Sutradara
Setiap bulan Juni-Juli, layar kaca dan linimasa media sosial dipenuhi kisah pilu dari orang tua murid. Ada yang menginap di depan sekolah sejak tengah malam demi nomor antrean, ada pula yang menangis histeris saat sistem zonasi menunjukkan anaknya kalah jarak 200 meter dari batas radius. Dan jangan lupa, si "error sistem" yang selalu muncul seperti tokoh antagonis sinetron.
Masalahnya beragam dan klasik: pungutan liar (pungli), jual-beli kursi, surat domisili palsu, piagam prestasi dadakan hasil turnamen fiktif, dan entah apa lagi. Semua jadi ritual tahunan yang lebih mirip audit moral kolektif daripada sekadar seleksi masuk sekolah.
Tahun 2024 lalu, Ombudsman RI mencatat lebih dari 5.000 laporan pelanggaran selama PPDB (Ombudsman, 2024). Ini bukan angka, ini tsunami keputusasaan sistemik. Belum lagi kisah ironis: anak ASN di Jakarta mendaftar lewat jalur afirmasi ekonomi lemah, atau rumah kontrakan di depan sekolah mendadak disewa 100 keluarga dalam semalam demi Kartu Keluarga (KK) baru.
Dalam konteks ini, perubahan nama dari PPDB ke SPMB seperti mengganti label obat, tapi isi masih paracetamol. Bisa mengurangi demam sebentar, tapi infeksi sistemiknya belum sembuh.
Berganti Istilah, tapi Tidak Ganti Nasib
Perubahan istilah menjadi SPMB pada tahun 2025 diharapkan menjadi “refresh” sistem seleksi. Tapi sayangnya, jalur penerimaan masih tetap: afirmasi (untuk keluarga tidak mampu), zonasi (berdasarkan domisili), prestasi, dan mutasi (biasanya untuk anak ASN/TNI/pindahan).
Masalahnya bukan pada nama jalur, tapi pada mudahnya jalur-jalur ini disulap jadi jalan tol bagi yang punya koneksi atau kocek tebal. Jalur afirmasi menjadi playground pemalsuan surat keterangan miskin. Zonasi malah mendorong bisnis sewa rumah fiktif. Jalur prestasi jadi ladang produksi piagam instan.
Bahkan ada orang tua yang mengoleksi piagam seperti kartu Pokémon demi anaknya bisa masuk SMP unggulan. Sayangnya, yang dikoleksi bukan pengetahuan, tapi legalitas kertas.
Dalam teori, zonasi dibuat untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi segregasi sosial (Sutadi et al., 2025). Nyatanya, orang tua dari kalangan menengah ke atas tetap berlomba mencari cara agar anaknya tidak "terjebak" di sekolah negeri biasa. Akibatnya, ketimpangan tetap eksis, hanya bungkusnya saja yang berubah.
Semua Jalur Bisa Dimanipulasi, Kecuali yang Punya Integritas
Manipulasi dalam seleksi siswa bukan mitos urban—ini kenyataan nasional. Jalur afirmasi dimanipulasi dengan surat keterangan miskin yang bisa "dibeli" dari RT/RW longgar integritas. Bahkan ada biro jasa yang khusus mengurus surat tersebut, lengkap dengan jaminan “masuk sekolah favorit atau uang kembali”.
Zonasi? Jangan harap bersih. Cukup pindah domisili sebulan sebelum pendaftaran, lalu keluarkan KK baru. Tak masalah kalau rumahnya cuma seukuran kamar mandi asalkan ada nama di KK dan titik GPS yang “dekat”. Ironisnya, sistem ini mendorong migrasi administratif yang semu, bukan mobilitas pendidikan yang nyata.
Jalur prestasi pun penuh polemik. Turnamen siluman muncul menjelang pendaftaran. Ada yang bikin lomba catur antar komplek dengan 3 peserta, dan tentu saja: anaknya juara satu. Bahkan piagamnya lebih kinclong daripada kualitas materinya.
Satu-satunya jalur yang relatif sulit dimanipulasi adalah mutasi. Namun, ini hanya berlaku untuk ASN, TNI, atau guru yang pindah tugas. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Mutasi pun bisa "dijadikan proyek", jika yang mengurus punya jejaring kuat dan alasan yang bisa disulap.
Sekolah Favorit, si Idaman yang Menguras Segala
Akhirnya, semuanya bermuara pada satu obsesi: masuk sekolah favorit. Entah itu karena kualitas guru, kedisiplinan, biaya murah, atau sekadar gengsi. Sekolah negeri unggulan seperti magnet, menarik semua orang tua yang ingin masa depan anaknya lebih baik, meskipun harus menginap semalam di tenda depan sekolah.
Dan inilah problem struktural kita. Kualitas sekolah tidak merata, fasilitas timpang, guru tidak tersebar adil. Maka, alih-alih meningkatkan semua sekolah menjadi bagus, kita malah saling sikut demi masuk ke segelintir sekolah yang “dipercaya bermutu”.
Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 yang menyatakan bahwa sekolah swasta juga harus digratiskan oleh negara di tingkat dasar dan menengah (MK, 2024) adalah langkah revolusioner. Tapi realisasi teknisnya? Jangan berharap semulus drama Korea. Pemilihan sekolah swasta mana yang layak dibantu, kesiapan anggaran negara, dan potensi konflik kepentingan akan jadi medan laga berikutnya.
Realitasnya, sekolah swasta pun terbagi dua kutub: elit dan sederhana. Yang elit mematok harga selangit, tapi fasilitasnya seluas kampus. Yang sederhana, ya... kadang satu guru bisa merangkap sebagai petugas kebersihan dan satpam. Ketimpangan ini makin menegaskan bahwa sistem pendidikan kita bukan lagi menara gading, tapi kastil dengan gerbang tertutup bagi si miskin.
Solusi Sistemik atau Sekadar Pindah Masalah?
Refleksi terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru mengarah pada urgensi solusi sistemik yang tidak sekadar mengganti istilah dari PPDB ke SPMB.
Saat ini, DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan salah satu gagasan menarik: meniru sistem pendidikan Finlandia.
Dalam sistem tersebut, proses seleksi peserta didik tidak ditangani langsung oleh sekolah, melainkan dikelola oleh aparat non-guru seperti lurah atau camat.
Tujuannya adalah agar guru bisa sepenuhnya fokus pada proses pembelajaran, bukan menjadi panitia seleksi yang harus menghadapi tekanan dari orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi.
Namun, gagasan ini tidak serta-merta tanpa cela. Ada kekhawatiran bahwa jika proses seleksi dipindahkan ke tangan aparat administratif, potensi penyalahgunaan wewenang hanya berpindah tempat.
Dalam konteks budaya birokrasi kita yang masih rentan terhadap praktik korupsi, ada risiko bahwa lurah atau camat justru menjadi aktor baru dalam jual-beli kursi sekolah. Alih-alih mengatasi masalah, pendekatan ini bisa saja melanggengkan praktik kecurangan dalam wujud baru yang lebih terselubung.
Untuk itu, perbaikan sistem tidak cukup dilakukan dengan reposisi aktor seleksi, tetapi harus mencakup pembangunan sistem pengawasan dan audit yang kuat. Diperlukan tenaga pengawas yang profesional, sistem digital yang andal, dan prinsip transparansi yang dibangun sejak desain awal.
Praktik manipulasi seperti surat domisili palsu atau piagam prestasi instan harus dicegah dengan verifikasi yang ketat dan otomatis.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi keharusan, agar mereka tidak terjebak dalam dilema etik akibat godaan suap. Gaji guru yang layak akan memperkuat integritas mereka, sebagaimana pernah disarankan secara jenaka oleh masyarakat: "gaji guru samakan dengan hakim, biar bisa tolak amplop juga."
Perlu dicatat bahwa kebijakan zonasi pada dasarnya memiliki semangat yang baik: menciptakan pemerataan akses pendidikan.
Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Dinda Febrianti Putri et al. (2024), menunjukkan bahwa zonasi berhasil meningkatkan peluang siswa dari keluarga tidak mampu untuk mengakses sekolah negeri. Namun, implementasinya masih terhambat oleh disparitas kualitas fasilitas dan sumber daya antar sekolah.
Persepsi masyarakat yang masih melekat pada istilah “sekolah favorit” turut memperparah ketimpangan, menjadikan zonasi sebagai ruang kontestasi administratif alih-alih instrumen keadilan sosial.
Oleh karena itu, langkah pembenahan tidak bisa dilakukan setengah hati. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap semua jalur penerimaan, memperkuat regulasi terhadap pemalsuan data, serta menyempurnakan sistem digital yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, guru dan pengawas pendidikan harus dibekali insentif dan kapasitas yang memadai. Yang tidak kalah penting adalah membangun citra bahwa setiap sekolah negeri memiliki mutu yang baik dan layak dipilih oleh siapa pun.
Jika ini semua tercapai, maka anak-anak kita kelak tidak lagi harus bertarung dengan piagam instan, KK rekayasa, atau surat miskin palsu, melainkan cukup menunjukkan dirinya sebagai anak bangsa yang punya hak untuk belajar.