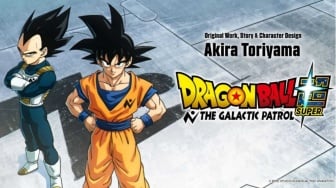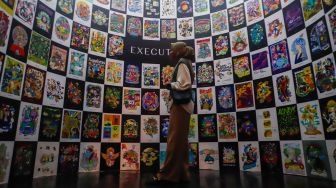Beberapa hari terakhir, kasus yang dialami oleh Neni Nur Hayati, aktivis demokrasi sekaligus Direktur DEEP Indonesia, ramai menjadi perhatian publik. Dalam sebuah video edukatif yang diunggah ke media sosial, khususnya TikTok, Neni menyampaikan pandangannya tentang bahaya buzzer politik tanpa menyebutkan nama atau jabatan pihak mana pun.
Namun, bagian video tersebut di-captured ataupun disunting, disebarluaskan ulang oleh sejumlah akun, termasuk akun resmi milik instansi pemerintah daerah, seperti Diskominfo Jawa Barat. Akun tersebut berhasil menyudutkan Neni sebagai pejuang demokrasi, seolah-olah Neni sedang menyerang sosok tertentu, yakni Gubernur Jawa Barat.
Penyalahgunaan foto pribadi atau bagian dari video konten itu menghasilkan gelombang serangan digital terhadap Neni yang berisi komentar kebencian, ancaman, hingga indikasi peretasan akun pribadi. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut telah merespons komentar-komentar tersebut secara terbuka, tetapi justru mendapat balasan yang lebih brutal.
Begitulah warganet Indonesia. Peristiwa ini menjadi contoh nyata terjadinya regresu demokrasi (kemunduran demokrasi). Ekspresi warga sipil bisa dengan cepat dibelokkan, dibungkam, dan bahkan dibahayakan di era komunikasi digital. Ruang publik digital menjadi ruang angker digital.
Kekerasan digital “Doxing”
Istilah doxing awalnya berasal dari kata “docs” (dokumen), sebuah istilah slang dari komunitas hacker tahun 1990-an yang merujuk pada praktik “dropping docs”—mengungkap identitas asli seseorang secara daring dengan maksud merugikan (Honan dalam Douglas, 2016; Chen et al., 2019).
Seiring waktu, istilah ini mengalami pelesetan secara pengucapan menjadi “doxxing”. Doxing didefinisikan sebagai penyebaran data pribadi seseorang ke ruang publik tanpa persetujuan, dengan niat merugikan atau menyakiti individu tersebut, dan umumnya disertai motivasi intimidasi, balas dendam atau tekanan sosial.
Menurut Snyder et al. (2017), doxing bukan hanya persoalan data, tetapi juga soal niat dan dampak. Praktik doxing ini diduga dilemparkan kepada Neni dengan maksud menghukum sikap kritisnya, sehingga ia merasa kebebasannya direnggut dan integritasnya sebagai pejuang demokrasi dikerdilkan. Doxing menjadi bentuk kekerasan digital berbasis informasi yang menimbulkan risiko nyata bagi keselamatan dan kebebasan individu, sehingga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi digital.
Dalam konteks komunikasi digital, doxing menjadi semakin berbahaya karena skala penyebaran informasi yang sangat luas dan cepat, serta minimnya kontrol atas narasi yang berkembang. Dalam kasus Direktur DEEP ini, kritiknya atas kebijakan pejabat negara melalui media sosial justru seperti dipelintir dan dijadikan senjata untuk memperburuk reputasi dan membahayakan keselamatannya.
Esensi dari doxing terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban—korban menjadi rentan karena informasi pribadinya dikendalikan oleh pihak lain dengan niat merugikan. Akibatnya, hak atas rasa aman, integritas diri, dan kebebasan berekspresi seseorang dapat tercederai.
Setiap orang perlu memahami bahwa doxing tidak hanya berdampak di dunia digital. Dampaknya sangat nyata dan menyentuh ranah kehidupan sosial langsung: mengganggu pekerjaan, relasi sosial, bahkan mengancam keselamatan fisik. Oleh karena itu, doxing perlu dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis teknologi yang membutuhkan perlindungan hukum, kebijakan platform, dan kesadaran publik yang lebih kuat.
Dalam kasus Neni Nur Hayati, meskipun yang disebarkan ulang oleh akun Diskominfo Jabar bukanlah data personal seperti nomor telepon atau alamat, namun penggunaan foto dari bagian video tanpa izin dan tanpa narasi dengan konteks utuh dapat dipahami sebagai bentuk manipulasi informasi yang memiliki efek serupa dengan doxing: memicu serangan personal yang intensif terhadap individu. Maka, perlu ada evaluasi lebih lanjut—secara etis dan hukum—apakah tindakan ini merupakan bentuk “doxing tidak langsung” atau minimal kontribusi aktif terhadap ekosistem kekerasan digital.
Doxing sebagai Alat Pembungkaman
Lebih dari sekadar pelanggaran privasi, doxing telah menjadi alat represif yang digunakan untuk membungkam kritik dan menekan kebebasan berpendapat, padahal hak tersebut dijamin dalam sistem demokrasi. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa serangan digital kepada orang-orang yang mengkritik merupakan bentuk pembungkaman digital yang tidak boleh ditoleransi (Amnesty.id, 17 Juli 2025). Pernyataan ini menyoroti bahaya besar yang mengintai kebebasan berekspresi jika tindakan semacam ini dibiarkan terus terjadi tanpa akuntabilitas.
Keterlibatan akun resmi pemerintah dalam menyebarluaskan ulang bagian konten tanpa izin juga menjadi sinyal serius. Hal yang dialami oleh Neni menunjukkan bagaimana sebuah narasi kritis yang tidak personal dapat diseret ke ranah pribadi, lalu dijadikan bahan serangan secara massal. Ketika sebuah institusi resmi ikut menyebarluaskan tanpa izin dan tanpa konteks yang utuh, maka terjadi kondisi yang memperparah pembungkaman.
Alih-alih menjadi pelindung hak-hak sipil, lembaga negara justru ikut memperburuk situasi dan memperbesar potensi serangan terhadap warganya sendiri. Ini bukan cuma masalah manajemen komunikasi digital, tapi juga cerminan lemahnya etika publik dan tanggung jawab institusional.
Kasus seperti ini menambah iklim ketakutan dalam dunia digital, yang mana pernah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya (seperti pemanggilan petinggi media dan rektor, serta ancaman terhadap Tempo). Warganet yang ingin menyampaikan pandangan rasional akhirnya memilih diam karena khawatir diserang secara personal dengan cara doxing.Doxing, dalam bentuknya yang sistematis dan terorganisir, menjadi instrumen perusak demokrasi yang pelan namun nyata: membungkam suara warga, menciptakan ketakutan kolektif, dan menghapus ruang aman untuk berdiskusi.
Demokrasi tidak mungkin tumbuh dalam atmosfer mencekam, penuh ketakutan dan intimidatif. Demokrasi hanya bisa hidup jika warga merasa bebas (liberal) untuk menyampaikan kritik tanpa ancaman. Diskusi yang terbuka, kritik yang tajam, dan keberanian warganet menyuarakan kegelisahan sosialnya justru adalah wujud emansipasi dalam demokrasi digital.
Begitu pula dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak yang tak boleh ditekan oleh kekuasaan, terlebih dengan alasan menjaga citra politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus ini memerlukan investigasi menyeluruh dan akuntabilitas yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam insiden ini, termasuk lembaga resmi negara yang turut menyebarluaskan foto ataupun bagian dari video dan narasi tersebut.
Jika kasus ini tidak ditindak tegas, maka akan menjadi preseden yang buruk bagi masa depan demokrasi digital di Indonesia. Kita sedang berada di persimpangan: tetap diam terbungkam dan membiarkan ketakutan mendominasi, atau berdiri tegak berjuang menghadirkan proses demokrasi digital sebagai bentuk pembelaan kebebasan sipil dan ruang aman berekspresi.
Besar harapan bangsa ini dapat mencapai keadilan dan transparansi dalam dunia digital. Adanya komitmen dalam memastikan hak digital, kebebasan sipil dan etika komunikasi dalam era demokrasi digital. Inilah demokrasi digital yang sehata dengan pondasi rasionalitas etis.
Penulis: Ade Indriani Siagian, M.I.Kom (Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta)