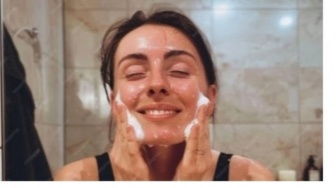Di balik potret sumringah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru saja naik jabatan—lengkap dengan foto Instagram berlatar belakang karangan bunga, terlihat rapi dengan setelan batik mutakhir dan senyum 45 derajat—terselip kisah muram yang tak sempat masuk frame: permohonan cerai. Fenomena ini makin mencuat seiring meningkatnya angka perceraian usai pengangkatan jabatan. Sebuah ironi: ketika karier naik, rumah tangga justru goyah.
Kata orang, naik jabatan itu berkah. Tapi bagi sebagian ASN dan PPPK, berkah itu datang dengan buntut masalah: hubungan rumah tangga mulai retak. Apakah ini karma karena terlalu sering keluar dinas dan lupa tanggal ulang tahun pasangan? Atau justru karena kekuasaan memang bisa bikin lupa siapa yang dulu nyuci piring waktu kamu masih golongan II-a?
Ini bukan soal gosip kantor atau desas-desus warung kopi. Ini nyata. Dan serius. Bahkan Guru Besar UIN Banten, M. Ishom el-Saha, sampai angkat bicara. Menurut beliau, perubahan status sosial kerap memicu dinamika baru dalam rumah tangga: dari perjuangan bersama menjadi ego pribadi.
Naik Pangkat, Naik Ego?
Kita semua tahu, kekuasaan itu menggoda. Dari zaman Julius Caesar sampai Pak RT di komplek, jabatan selalu punya efek psikologis. Naik jabatan bukan cuma soal kenaikan gaji atau tunjangan makan. Ini juga soal perubahan identitas sosial. Tiba-tiba, kamu bukan lagi “Pak Budi biasa,” tapi “Pak Kabid.” Di kantor, semua manggil sopan. Di rumah? Istri masih berani nyuruh buang sampah. Kok rasanya janggal, ya?
Perubahan semacam ini sering kali mengganggu harmoni rumah tangga. Dalam banyak kasus, salah satu pihak merasa tidak “ikut naik” bersama status pasangannya. Ini memperlebar jarak psikologis—dari yang dulunya berjuang bareng, jadi merasa ditinggal.
M. Ishom el-Saha mengingatkan bahwa naik jabatan tanpa kematangan emosional bisa menjadi bumerang. Ketika seseorang terlalu fokus pada citra profesionalnya, ia bisa teralienasi dari relasi personalnya. Ironisnya, di saat para ASN dan PPPK mengurus dokumen negara dengan rapi, urusan hati malah jadi acak-acakan.
Jadwal Padat, Cinta Longgar
Naik jabatan datang dengan bonus tak tertulis: rapat mendadak, acara dinas dadakan, dan pulang malam yang makin sering. “Demi negara,” katanya. Tapi negara tidak akan memeluk kamu saat kamu sakit atau menyambut kamu pulang dengan senyum dan teh panas.
Perubahan ritme kerja secara drastis seringkali tak diiringi dengan penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga. Pola komunikasi jadi renggang. Kalau dulu masih bisa ngobrol sambil makan malam, kini tinggal sisa obrolan via WhatsApp dengan balasan singkat: “Otw”, “Lembur”, atau “Zzz.”
Dalam jangka panjang, hubungan yang tak terpelihara ini seperti tanaman yang tidak disiram: layu. Tidak langsung mati, tapi pelan-pelan kehilangan nyawa. Dan ketika pasangan sudah lebih akrab dengan laptop daripada pasangannya, kita tahu: ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini soal prioritas yang bergeser.
Killewald et al. (2023) menunjukkan bahwa risiko perceraian tak lagi hanya milik kelas atas, tapi juga menular ke kelas pekerja. Dengan tekanan kerja dan ketimpangan peran domestik, bahkan mereka yang dulunya tampak harmonis mulai mengalami tekanan relasional yang sama.
Cinta Tak Bisa Dicicil seperti KPR
Kemapanan finansial tidak serta-merta menjamin kemapanan emosional. Dalam banyak kasus, justru setelah kondisi ekonomi membaik, masalah rumah tangga mencuat. Seolah-olah, kesibukan mencari uang dulu menutupi persoalan fundamental yang selama ini terpendam.
Inilah jebakan SES (socio-economic status) yang dijelaskan oleh Sandström & Stanfors (2023): semakin tinggi status sosial ekonomi, semakin tinggi pula risiko perceraian. Mengapa? Karena relasi makin dituntut untuk jadi “mutual partnership”—bukan hanya finansial, tapi emosional. Dan ketika ekspektasi itu tak terpenuhi, kekecewaan pun menggelinding seperti bola salju.
Sebagian pasangan lupa bahwa cinta tidak bisa dicicil seperti rumah atau motor dinas. Cinta butuh hadir, bukan sekadar transferan bulanan. Butuh kata-kata, bukan cuma hasil kerja. Tapi banyak ASN dan PPPK merasa bahwa kewajiban nafkah sudah cukup. Padahal, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan slip gaji.
ASN dan PPPK Butuh Bimbingan Emosional, Bukan Cuma Diklat
Selama ini pembinaan kepegawaian sering kali hanya fokus pada aspek teknis dan administratif: bagaimana menulis surat dinas, bagaimana mengelola anggaran, bagaimana membuat laporan kegiatan yang tebal tapi kosong makna.
Tapi tidak ada modul “Bagaimana Menjadi Pasangan yang Tetap Sadar Diri Setelah Jadi Pejabat.” Padahal, itu lebih urgen. Kita butuh Diklat Emosional. Pelatihan bagaimana tetap menjadi manusia, bukan hanya mesin birokrasi.
M. Ishom el-Saha mengusulkan agar pembinaan karakter dan penguatan emosional menjadi bagian dari sistem pembinaan ASN dan PPPK. Ini bukan ide aneh. Bahkan negara-negara Skandinavia mulai menerapkan pendekatan ini dalam sistem pelatihan kerja sektor publik. Karena mereka sadar, pegawai negara yang sehat emosional akan lebih stabil—baik dalam kerja maupun rumah tangga.
Bayangkan jika ada pelatihan seperti “Etika Berkata ‘I Love You’ Setelah Rapat Maraton” atau “Teknik Membagi Waktu antara Negara dan Rumah Tangga.” Jenaka, tapi relevan.
Negara Tidak Bisa Menjamin Bahagia
Naik jabatan adalah prestasi, tapi tidak boleh dibayar dengan kehilangan fondasi rumah tangga. Kita harus berani melihat bahwa ASN dan PPPK bukanlah robot pengabdi negara tanpa rasa. Mereka adalah manusia biasa yang juga butuh cinta, pengakuan, dan ruang untuk tetap menjadi pasangan yang hadir.
Fenomena meningkatnya perceraian di kalangan ASN dan PPPK adalah alarm sosial. Jangan sampai naiknya status menjadi pemicu jatuhnya relasi. Kita butuh kebijakan yang tidak hanya menilai kinerja di kantor, tapi juga peduli pada keseimbangan hidup pegawai.
Karena pada akhirnya, tidak ada gunanya mengurus negara kalau rumah tangga sendiri hancur. Lalu, apa gunanya menjadi pejabat publik kalau tidak bisa menjadi suami atau istri yang setia?