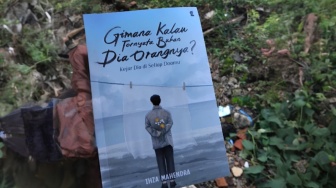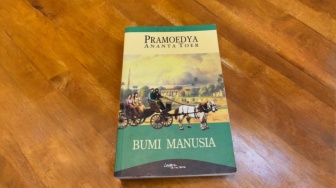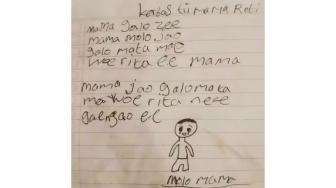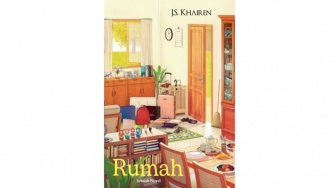Selama ini, kita sering diajari satu mantra yang terdengar mulia: alam harus dijaga dengan cara dibatasi dari manusia. Kawasan konservasi dibatasi aksesnya, wisata diperketat, drone dilarang, masyarakat dijauhkan. Alasannya satu, yaitu demi melindungi alam.
Namun, kenyataan di lapangan sering kali justru berkata sebaliknya. Di banyak kasus, cara paling aman menjaga lingkungan bukan dengan mengosongkannya, melainkan dengan menjadikannya ruang yang hidup. Termasuk sebagai destinasi wisata yang diawasi publik.
Wisata vs Konservasi: Mengapa Kerusakan Alam Justru Terungkap oleh Publik?
Logikanya sederhana. Tempat yang ramai akan lebih sulit dirusak secara diam-diam. Ketika ada wisatawan, pemandu lokal, fotografer, peneliti, dan warga yang datang silih berganti, maka mata publik bekerja. Setiap alat berat yang masuk, setiap pohon yang tumbang, setiap lubang tambang yang menganga akan cepat terdeteksi. Kerusakan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Viral atau tidak, cepat atau lambat, itu akan terlihat.
Sebaliknya, kawasan yang “terlalu steril” justru rawan disalahgunakan. Banyak taman nasional dan kawasan lindung di Indonesia berada jauh dari pengawasan publik. Akses dibatasi, masyarakat sekitar tidak dilibatkan, dan informasi dikelola secara tertutup.
Ironisnya, dalam kondisi seperti inilah aktivitas ilegal justru menemukan ruang. Tambang bisa beroperasi bertahun-tahun di tengah kawasan konservasi tanpa diketahui luas oleh publik. Warga sekitar sering kali baru tahu setelah kerusakan sudah telanjur parah.
Drone Dilarang, Tambang Dibiarkan: Konservasi untuk Siapa?
Kita berkali-kali menyaksikan paradoks yang menyakitkan. Drone dilarang dengan alasan mengganggu satwa liar, tetapi justru melalui rekaman drone-lah publik pertama kali melihat lubang-lubang raksasa bekas tambang di kawasan yang katanya dijaga ketat.
Kamera dari udara membuka fakta yang tak terlihat dari jalan setapak. Ini memunculkan pertanyaan serius: apakah larangan itu benar-benar demi perlindungan satwa, atau justru demi melindungi kerahasiaan?
Di titik ini, peran pengelola kawasan (mulai dari balai taman nasional atau lembaga konservasi) layak dipertanyakan. Apakah mereka sungguh menjaga, atau tanpa sadar (atau sadar sepenuhnya) justru menutupi?
Ketika transparansi minim, laporan sulit diakses, dan pengawasan hanya bersifat internal, maka publik kehilangan fungsi kontrol. Padahal, dalam ekologi modern, partisipasi publik adalah salah satu kunci konservasi yang efektif.
Ketika Akses Dibatasi, Kerusakan Justru Tak Terawasi
Wisata yang dikelola dengan benar justru bisa menjadi alat perlindungan. Kehadiran manusia tidak selalu berarti ancaman. Dengan regulasi yang jelas—pembatasan jumlah pengunjung, zonasi ketat, edukasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal—wisata alam dapat menciptakan insentif untuk menjaga. Alam yang bernilai ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan akan lebih dipertahankan daripada alam yang “sunyi” tapi diam-diam dieksploitasi.
Selain itu, wisata membuka ruang bagi keterlibatan warga sekitar. Ketika masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari alam yang lestari, mereka menjadi penjaga pertama. Mereka akan lebih cepat melapor jika ada aktivitas mencurigakan, karena kerusakan alam berarti ancaman langsung bagi sumber penghidupan mereka.
Alam yang Dijaga dalam Sunyi, Rusak dalam Diam
Pada akhirnya, konservasi bukan soal menutup rapat-rapat alam dari manusia, melainkan mengelola hubungan manusia dan alam secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Alam tidak selalu rusak karena terlalu banyak dilihat. Justru sering kali ia hancur karena terlalu lama disembunyikan.
Mungkin sudah waktunya kita bertanya ulang: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan ketika alam dijauhkan dari mata publik? Dan siapa yang paling dirugikan ketika kerusakan baru terungkap saat semuanya sudah terlambat?