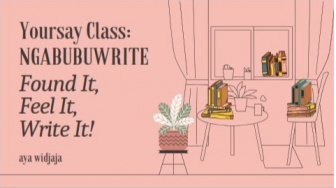Pernyataan Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan baru-baru ini, bikin publik geram. “Tuntunan 17+8 akan dipenuhi, tapi tak serentak, bisa repot,” katanya.
Kalimat yang mungkin dimaksud untuk meredam suasana, justru terdengar seperti pelecehan terhadap suara rakyat. Repot? Bukannya memang itu tugas pemerintah, mengurus keruwetan rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara?
Tuntutan 17+8 yang kini viral di media sosial berisi rangkuman panjang keresahan mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, hingga warganet. Dari desakan menarik TNI dari urusan sipil, membekukan kenaikan tunjangan anggota DPR, sampai menolak fasilitas baru bagi pejabat yang semakin hari makin jauh dari realitas hidup orang kebanyakan.

Ada 17 poin besar yang sifatnya mendesak, plus 8 tambahan yang jadi penegasan. Tenggat waktunya pun jelas, 5 September 2025.
Tapi apa yang publik dapat? Hanya narasi klasik, “Presiden sudah mendengar aspirasi, tapi tidak bisa dipenuhi semua.” Bukankah kalimat seperti itu sudah kita dengar bertahun-tahun? Dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, narasinya sama, aspirasi dihargai, tapi tanpa realisasi.
Padahal, rakyat tidak menuntut hal yang mustahil. Menarik TNI dari pengamanan sipil, misalnya, itu sejatinya hanya menjalankan amanat reformasi 1998. Menahan DPR agar tidak terus menambah fasilitas, itu soal keadilan, karena rakyat sedang berjibaku dengan harga sembako yang membengkak. Lalu apanya yang repot?
Repot itu justru ketika rakyat harus demo berhari-hari, tidur di jalan, dipukul gas air mata, hanya untuk mengingatkan pejabat bahwa mereka digaji dari uang rakyat. Repot itu ketika mahasiswa harus meninggalkan kelas, buruh kehilangan upah harian, emak-emak berdesakan di jalanan, demi meneriakkan sesuatu yang seharusnya sudah otomatis jadi prioritas pemerintah.
Komentar warganet pun menyambar cepat. “Gamau repot ngapain jadi pejabat? Bagian nikmatin duit rakyatnya aja baru semangat,” tulis satu akun. Dan sulit menyangkal itu.
Karena kita tahu betul, beberapa undang-undang kepentingan elite bisa selesai dalam hitungan hari. Omnibus Law contohnya, disahkan begitu cepat, seakan tak ada waktu untuk mendengar masukan rakyat. Jadi, alasan repot seharusnya tidak menjadi keterbatasan.
Kalau pejabat bilang memenuhi tuntutan rakyat itu bikin repot, lantas siapa yang selama ini dibuat repot? Apakah rakyat yang dipaksa tunduk pada kebijakan ngawur, atau pejabat yang kelelahan mendengar suara keras di luar pagar?
Demokrasi memang tidak pernah menjanjikan kenyamanan bagi penguasa. Justru esensinya ada di ketidaknyamanan. Kalau mau nyaman tanpa kritik, jangan bercita-cita jadi pemimpin di negara demokrasi.
Wiranto boleh bilang kalau Prabowo sudah mendengar semua tuntutan. Tapi apa gunanya mendengar kalau ujung-ujungnya disaring sesuka hati?
Apalagi, kata repot yang diucapkan Wiranto terasa merendahkan. Seolah rakyat yang sedang memikul beban hidup itu tidak penting dibanding kenyamanan birokrasi.
Padahal, konstitusi jelas menyebut kalau kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, bukannya repot, justru mandat konstitusional negara ada di sana, yaitu memenuhi apa yang rakyat minta.
Dan bukankah lucu, jika pemerintah bisa begitu luwes memenuhi permintaan investor asing, tapi lambat memenuhi permintaan rakyat sendiri? Misalnya, izin tambang bisa keluar kilat, tapi perbaikan nasib petani selalu jadi pekerjaan rumah yang tak pernah selesai.
Saat ini, yang dipertaruhkan bukan cuma tuntutan 17+8, tapi kredibilitas negara di mata rakyatnya.
Mungkin, inilah saatnya pejabat berhenti merasa diganggu. Karena demo, kritik, dan tuntutan itu bukan gangguan. Itu justru napas demokrasi. Kalau tuntutan rakyat dianggap repot, mungkin problemnya bukan di rakyat yang terlalu cerewet, tapi di pejabat yang terlalu manja.