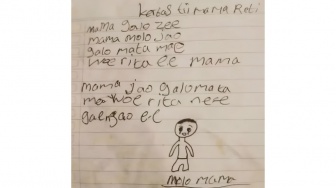Fenomena doomscrolling adalah salah satu gejala paling khas dari kehidupan digital modern sebuah kebiasaan yang tampak sepele, tetapi memiliki dampak psikologis yang dalam. Istilah ini merujuk pada tindakan terus-menerus menggulir layar untuk membaca berita atau informasi negatif, meski kita tahu bahwa hal tersebut menimbulkan kecemasan, kelelahan, bahkan rasa putus asa. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa disadari: seseorang hanya bermaksud “melihat sebentar” berita terbaru di media sosial, namun waktu berlalu tanpa terasa, dan pikiran justru semakin sesak oleh arus kabar buruk yang tiada henti.
Secara psikologis, doomscrolling dapat dijelaskan sebagai kombinasi antara rasa ingin tahu, kebutuhan akan kendali, dan dorongan biologis untuk mengenali ancaman. Otak manusia berevolusi untuk selalu waspada terhadap bahaya; karena itu, informasi negatif lebih mudah menarik perhatian dibandingkan hal-hal positif. Pada masa lalu, insting ini membantu manusia bertahan hidup. Namun, di era digital, mekanisme yang sama justru membuat kita terjebak dalam siklus stres dan kecemasan. Setiap kali membaca berita bencana, konflik, atau peristiwa tragis, amygdala bagian otak yang memproses rasa takut aktif, melepaskan hormon stres seperti kortisol. Akibatnya, kita merasa perlu terus mencari tahu lebih banyak, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi rasa aman. Ironisnya, semakin banyak kita membaca, semakin besar rasa cemas yang muncul.
Di balik layar, algoritma media sosial memperkuat perilaku ini. Platform digital dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Konten yang menimbulkan emosi kuat, terutama ketakutan dan kemarahan, terbukti menghasilkan interaksi lebih tinggi. Karena itu, sistem algoritmik secara otomatis mendorong berita dan video bernada negatif ke halaman kita. Setiap guliran jempol menghadirkan rangkaian tragedi baru, menciptakan ilusi bahwa dunia terus memburuk. Kita pun tanpa sadar menjadi bagian dari lingkaran yang menumbuhkan kecemasan kolektif. Dalam konteks ini, doomscrolling bukan sekadar kebiasaan buruk individu, melainkan hasil dari ekosistem digital yang memang mengandalkan emosi manusia sebagai bahan bakar ekonomi perhatian.
Dampak psikologis dari doomscrolling semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengaku sulit tidur karena tergoda membuka ponsel sebelum beristirahat, “sekadar ingin tahu” berita terkini. Namun, yang ditemukan bukanlah ketenangan, melainkan kecemasan baru: laporan perang, bencana alam, krisis ekonomi, atau komentar-komentar penuh kebencian di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berita negatif yang berlebihan berkaitan erat dengan peningkatan stres, depresi, dan perasaan tidak berdaya. Dalam jangka panjang, hal ini juga memengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan berpikir jernih, karena otak terus berada dalam kondisi waspada.
Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini. Mahasiswa dan pekerja muda, yang hidup di tengah arus informasi tanpa batas, sering kali menjadikan media sosial sebagai sumber utama berita. Batas antara fakta dan opini menjadi kabur, dan setiap isu global terasa dekat sekaligus mengancam. Banyak yang mengalami apa yang disebut para psikolog sebagai information fatigue kelelahan karena terlalu banyak informasi tanpa kemampuan memprosesnya. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa merasa tahu segalanya namun sekaligus tidak memahami apa-apa. Rasa takut terhadap masa depan meningkat, dan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk memperbaiki keadaan menurun.
Di tingkat sosial, doomscrolling juga menimbulkan efek domino. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi kabar buruk, empati bisa berubah menjadi kelelahan emosional. Orang tidak lagi tersentuh oleh penderitaan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena sudah terlalu sering terpapar. Fenomena ini disebut empathy fatigue. Kita berhenti merasakan karena rasa pedih yang berulang membuat jiwa kebas. Dalam jangka panjang, hal ini berbahaya: publik kehilangan semangat untuk terlibat, untuk berbuat sesuatu, atau sekadar berharap. Dunia seakan berjalan tanpa harapan karena narasi yang mendominasi adalah krisis dan kehancuran.
Namun, penting disadari bahwa doomscrolling bukan masalah yang tak bisa dikendalikan. Kesadaran menjadi kunci utama. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kebiasaannya mengonsumsi berita negatif hanya memperburuk keadaan emosional, langkah awal untuk keluar dari siklus itu telah dimulai. Psikolog menyarankan untuk mempraktikkan kesadaran digital mengatur waktu, memilih sumber berita yang kredibel, dan menyadari emosi yang muncul setiap kali membaca informasi. Ada pula tren joyscrolling, yaitu upaya sengaja mencari konten positif, inspiratif, atau edukatif untuk menyeimbangkan persepsi tentang dunia. Hal ini bukan berarti mengabaikan kenyataan pahit, melainkan memulihkan keseimbangan agar pikiran tetap sehat.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menuntut tanggung jawab moral dari dunia media. Dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian publik, banyak media menggunakan judul sensasional yang menonjolkan ketakutan dan kemarahan. Padahal, jurnalisme sejatinya berfungsi untuk memberi pemahaman, bukan menimbulkan kepanikan. Di sinilah psikologi komunikasi memiliki peran penting untuk membantu media memahami bagaimana cara menyampaikan informasi tanpa memicu trauma kolektif. Pemberitaan yang seimbang, berperspektif solusi, dan berfokus pada edukasi dapat membantu masyarakat tetap kritis tanpa kehilangan harapan.
Pada akhirnya, doomscrolling adalah cermin dari ketegangan antara dua kebutuhan manusia modern: kebutuhan untuk tahu dan kebutuhan untuk tenang. Di satu sisi, kita ingin memahami dunia dan merasa terkoneksi. Di sisi lain, kita juga ingin damai dan bebas dari ketakutan. Sayangnya, cara kita mencari pengetahuan sering kali justru menimbulkan kekhawatiran baru. Dunia digital telah memperpendek jarak informasi, tetapi juga memperluas jarak emosional antara kita dan kenyataan. Setiap kali jari menyentuh layar, kita dihadapkan pada pilihan: terus menggulir hingga tenggelam, atau berhenti sejenak dan bernapas.
Mungkin inilah tantangan terbesar era informasi: bukan sekadar bagaimana kita mendapatkan berita, tetapi bagaimana kita menjaga kewarasan di tengah arusnya. Doomscrolling tidak akan hilang begitu saja, karena ia lahir dari dorongan alami manusia untuk mencari makna di tengah ketidakpastian. Namun, dengan kesadaran dan disiplin, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih sehat bukan sekadar menggulirkan berita buruk, tapi juga menggulirkan harapan. Dalam dunia yang penuh kegelisahan, berhenti sejenak dari layar mungkin adalah bentuk keberanian yang paling sederhana, sekaligus yang paling penting.