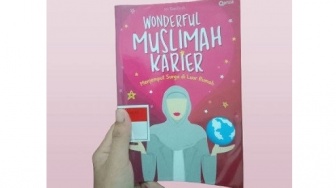Peristiwa di Sleman, Yogyakarta, ketika seorang suami yang membela istrinya dari penjambretan justru berakhir sebagai tersangka, menyentak kesadaran publik tentang satu persoalan mendasar dalam hukum pidana: di mana sesungguhnya batas pembelaan diri itu diletakkan.
Kasus ini bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan cermin dari ketegangan abadi antara kepastian hukum dan rasa keadilan.
Di satu sisi, hukum pidana menuntut keteraturan dan kepastian. Setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus diuji secara ketat melalui norma dan prosedur.
Di sisi lain, masyarakat hidup dalam realitas ancaman nyata, di mana kejahatan sering kali hadir tiba-tiba dan memaksa seseorang bertindak spontan demi melindungi diri atau orang terdekat. Ketika dua dunia ini bertabrakan, hukum diuji bukan hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai moral publik.
Pembelaan Diri dalam Norma Hukum
Dalam hukum pidana Indonesia, konsep pembelaan diri dikenal melalui doktrin noodweer. Secara normatif, pembelaan diri dibenarkan apabila dilakukan untuk menangkis serangan yang melawan hukum, bersifat seketika, dan tidak ada pilihan lain yang lebih ringan.
Pembelaan tersebut harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Di atas kertas, rumusannya tampak tegas dan rasional. Namun, dalam praktik, menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor pembelaan diri bukan perkara sederhana.
Hukum bekerja dengan logika kausalitas dan rasionalitas, sementara manusia bertindak dalam situasi genting dengan emosi, ketakutan, dan naluri bertahan hidup. Apa yang di ruang sidang dinilai sebagai “pilihan lain yang lebih aman”, dalam realitas lapangan bisa saja tidak pernah terpikirkan dalam sepersekian detik.
Kasus Sleman memperlihatkan dilema itu dengan terang. Seorang suami mengejar pelaku penjambretan demi melindungi istrinya dan mencegah kejahatan lanjutan.
Niat awalnya bukan untuk mencelakai, melainkan menghentikan. Namun, rangkaian peristiwa berujung pada kecelakaan fatal. Pada titik inilah hukum masuk, tidak hanya untuk membaca niat, tetapi menimbang akibat dan relasi sebab-akibat.
Antara Kausalitas dan Kepatutan Moral
Hukum pidana modern sangat bergantung pada konsep kausalitas: apakah tindakan seseorang secara langsung menyebabkan akibat tertentu. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, logika ini menjadi instrumen utama.
Tetapi pendekatan kausalitas murni sering kali berjarak dengan rasa keadilan sosial. Masyarakat bertanya, pantaskah seseorang yang bereaksi spontan melindungi keluarganya diperlakukan sama dengan pelaku kelalaian atau kesengajaan biasa?
Pertanyaan ini bukan ekspresi anti-hukum, melainkan refleksi moral yang wajar. Hukum pidana tidak hidup di ruang hampa; ia beroperasi dalam lanskap nilai sosial yang terus bergerak.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kesalahan yuridis dan kesalahan moral. Tidak setiap akibat tragis lahir dari kehendak jahat. Tidak pula setiap pelanggaran norma formal layak berujung pada stigmatisasi pidana. Ketika hukum gagal membaca konteks, ia berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
Mencari Titik Temu Keadilan
Kasus ini semestinya menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana hukum pidana memaknai pembelaan diri dalam konteks kejahatan jalanan yang kian marak.
Penegakan hukum tentu tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, tetapi juga tidak boleh tuli terhadap rasa keadilan masyarakat. Pendekatan yang lebih kontekstual diperlukan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.
Hakim, sebagai benteng terakhir keadilan, memiliki ruang untuk menggali nilai hidup dalam masyarakat, menimbang proporsionalitas tindakan, serta menilai apakah pemidanaan benar-benar menjadi solusi atau justru melahirkan ketidakadilan baru.
Menakar batas pembelaan diri bukan sekadar soal pasal dan ayat, melainkan soal keberanian hukum untuk bersikap manusiawi tanpa kehilangan ketegasannya.
Hukum yang baik bukan hukum yang sekadar menghukum, tetapi hukum yang mampu memahami mengapa seseorang bertindak, dalam situasi apa, dan dengan pilihan apa yang tersedia saat itu. Pada akhirnya, keadilan pidana tidak boleh berhenti pada kepastian normatif. Ia harus menjangkau rasa keadilan substantif.
Jika hukum ingin tetap dipercaya, ia harus mampu berdiri di tengah, tidak larut dalam emosi massa, tetapi juga tidak membeku dalam teks semata. Kasus di Sleman adalah pengingat bahwa di balik setiap berkas perkara, selalu ada manusia dan situasi yang jauh lebih kompleks daripada rumusan pasal.