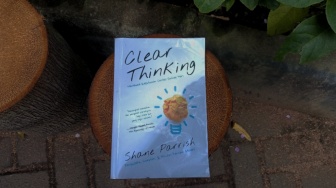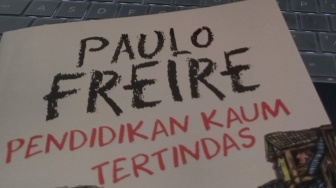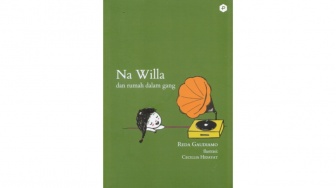Gerakan antirokok kerap dipresentasikan sebagai simbol kemajuan kesadaran kesehatan masyarakat. Semakin keras larangan, semakin tinggi pula klaim bahwa sebuah bangsa peduli pada kualitas hidup warganya.
Namun, jika dicermati lebih dalam, pendekatan yang semata-mata represif justru memunculkan pertanyaan lain. Apakah gerakan antirokok yang kita jalankan hari ini benar-benar lahir dari pendidikan publik yang matang, atau justru menandai kegagalan negara dalam mengelola perbedaan perilaku warganya?
Mari menengok beberapa contoh dari negara lain. Jepang, misalnya, dikenal sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Menariknya, Jepang bukan negara yang meminggirkan perokok secara ekstrem.
Smoking area tersedia di banyak titik. Terbuka, luas, bersih, dan nyaman. Para perokok tidak “dipamerkan” dalam bilik sempit mirip akuarium atau kandang transparan. Negara ini memilih jalan pengelolaan, bukan penghukuman sosial.
Australia pun menunjukkan pola serupa. Aturan merokok di ruang publik memang tegas, bahkan sangat tegas. Namun, pada batas-batas larangan itu, negara hadir dengan fasilitas yang layak. Tulisan “No Smoking Beyond This Line” hampir selalu disertai asbak permanen dan area yang jelas. Pesannya sederhana, perilaku merokok dibatasi, tetapi pelakunya tetap dihargai sebagai warga negara.
Bandingkan dengan Indonesia. Di sini, wacana pengendalian rokok sering kali berhenti pada larangan dan stigma. Area merokok sangat minim, sering tidak layak, tersembunyi, atau sama sekali tidak tersedia. Perokok diusir dari satu tempat ke tempat lain tanpa solusi, seolah keberadaan mereka adalah anomali yang harus disingkirkan, bukan realitas sosial yang perlu dikelola.
Padahal, dalam logika kebijakan publik, penyediaan ruang merokok bukan bentuk dukungan terhadap rokok, melainkan alat manajemen konflik sosial. Dengan ruang yang jelas dan manusiawi, “wilayah geo-politis” antara perokok dan non-perokok dapat dipisahkan secara damai. Hak atas udara bersih bagi non-perokok terlindungi, sementara hak perokok sebagai warga negara tetap diakui.
Ironisnya, ada fakta lain yang jarang dibicarakan dengan jujur: perokok adalah salah satu kelompok warga negara yang kontribusinya paling nyata terhadap penerimaan negara. Ketika orang lain mengonsumsi barang cukup dengan membayar harga produk, perokok membayar lebih. Di setiap batang rokok yang dibakar, ada cukai yang nilainya tidak kecil.
Sejak sekitar 2012, penerimaan negara dari cukai rokok secara konsisten berada di kisaran lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Dan total pajak rokok (Cukai Hasil Tembakau/CHT) yang masuk ke negara hingga Oktober 2025 sudah mencapai sekitar Rp176,5 triliun.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tulang punggung pembiayaan banyak sektor publik. Jika negara mampu menarik dana sebesar itu dari perokok, mengapa negara begitu pelit menyediakan fasilitas dasar bagi mereka?
Untuk membangun smoking area yang layak di ruang-ruang publik, negara tidak membutuhkan anggaran besar. Nol koma sekian persen saja dari total cukai rokok yang notabene berasal dari kantong perokok sendiri. Sudah cukup untuk membangun ribuan area merokok yang bersih, tertib, dan bermartabat.
Di titik inilah gerakan antirokok layak dikritisi. Ketika kampanye kesehatan berubah menjadi praktik eksklusi sosial, ketika edukasi digantikan oleh pengucilan, dan ketika negara lebih sibuk melarang ketimbang mengatur, maka yang tampak bukan keberhasilan pendidikan publik, melainkan kegagalannya.
Pendidikan yang berhasil seharusnya melahirkan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan perilaku secara rasional dan beradab. Bukan masyarakat yang merasa paling bermoral dengan cara menyingkirkan yang lain. Dalam isu rokok, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka konsumsi, tetapi membangun kebijakan yang adil, manusiawi, dan jujur terhadap realitas sosial.
Tanpa itu semua, gerakan antirokok berisiko hanya menjadi simbol moral kosong. Keras di permukaan, rapuh dalam substansi.