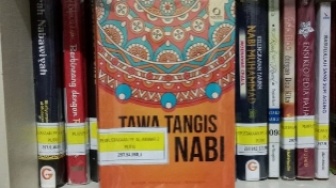Bagi siapa saja yang belajar ilmu politik pasti memahami bahwa politik akan selalu menyangkut soal-soal dan tujuan-tujuan masyarakat (public goals). Solusi terhadap persoalan dan upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat itu hanya dapat dicapai bila politik memiliki dasar moral dan norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku politik.
Analisa terhadap fenomena dan fakta politik yang tidak mempersoalkan nilai dan norma (non-valuational) acapkali tidak mewariskan pendidikan politik bagi publik. Lebih jauh lagi, para agen politik bisa kehilangan nurani dan daya kritisnya dalam menjalakan kekuasaan. Sebagai contoh, krisis politik yang saat ini terjadi di Belarusia berakar pada masalah perlindungan hak asasi manusia, praktik demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Juga krisis presidensial di Venezuela yang salah satunya ditengarai oleh korupsi akut di bidang sumber daya alam.
Bukti faktual itu menunjukkan bahwa nilai dan norma di dalam politik harus menjadi arus utama guna mencapai tujuan masyarakat. Pada saat yang sama, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai wilayah di Indonesia tahun ini sebagai fenomena politik juga mesti tegak lurus dengan nilai-nilai keadaban. Tulisan ini pada dasarnya hendak menguraikan moral publik yang sejatinya terkandung pada variabel-variabel sistem politik.
Fondasi Moral Politik
Jonathan Haidt dalam pembacaan Yudi Latif (2019) menjelaskan bahwa sistem moral merupakan seperangkat nilai, kebajikan, norma, praktik-praktik, identitas, institusi, teknologi, dan mekanisme psikologis yang terkiat dan bekerja secara bersamaan untuk menekan dan mengatur kepentingan pribadi yang memungkinkan terbentuknya masyarakat kooperatif.
Definisi tersebut sejalan dengan masyarakat sebagai konsep politik. Miriam Budiardjo (1983) menguraikan bahwa manusia memiliki naluri untuk berkawan, membentuk kelompok atau asosiasi, demi mencapai kebutuhan dan kepentingan bersama. Di dalam menjadi relasi antara manusia itulah nilai dan norma dibutuhkan.
Maka, dalam konteks moralitas politik termasuk dalam hal ini kehidupan publik, Haidt mengargumentasikan ada lima fondasi moral yang menjadi basis politik. Masing-masing adalah (i) care, (ii) fairness, (iii) loyalty, (iv) authority, dan (v) sancity.
Care berkaitan dengan respons dan sensitifitas adaptif seseorang terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain. Fairness merupakan fondasi moral dalam merespons hasrat atas penghargaan kolektif tanpa mengeksploitasi orang lain. Selanjutnya, loyalty dapat diapahami sebagai respons untuk menjaga soliditas kelompok melalu kepercayaan dan keberpihakan.
Authority adalah sikap positif untuk mewujudkan relasi yang akan bermanfaat dalam hirarki sosial. Yang terakhir adalah sancity berkaitan dengan respons terhadap dilema, ketidakpastian, dan tantangan hidup di dunia yang bersifat patogenis-parasit. Sehingga, lebih mudah untuk menginvestasikan keobjektifan pada irrationalitas dan nilai dalam rangka mengikat integrasi kelompok.
Kelima fondasi moral itu harus bisa dipastikan mendapat kedudukan di dalam sistem politik kita. Sistem politik ini kemudian perlu diterjemahkan ke dalam empat variabel: kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik (Budiardjo, 1983).
Pilkada, Moral, dan Sistem Politik
Dalam konteks Pilkada, pihak yang berkontestasi dituntut untuk menghadirkan moralitas publik tersebut dalam variabel sistem politik itu. Pertama, kekuasaan menyimpan makna terdalam yakni authority. Kekuasaan dalam pengertian ini harus didapatkan dan diupayakan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Makna ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dengan patuh pada otoritas yang berdaulat.
Sebagai ilustrasi, sejak masa pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara, sikap positif kontestan semestinya dapat dilacak pada komitmen mereka terhadap politik anti-korupsi, politik uang, kampanye negatif, bahkan pada pendidikan politik bagi publik. Bila terindikasi adanya pelanggaran atas norma Pilkada, semisal tindak pidana pemilu, maka publik patut mempertimbangkan hak suaranya agar tiba pada kontestan yang tepat.
Masih dalam batasan yang sama, melaksanakan kekuasaan juga tidak bisa dipisahkan dari cara politik mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui distribusi sumber daya demi mencapai kesejahteraan bersama. Artinya, pemimpin daerah harus menginventarisir segala sumber daya daerah (sektor pendidikan, pariwisata, industri, dan institusi keagamaan) untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan daerah.
Kedua, kepentingan senapas dengan loyalty. Kepentingan kemudian bermakna tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam ide ini, tujuan-tujuan privat dan partikulatitas individu diangkat ke dalam level ada bersama. Tujuan itu mestilah berdimensi publik. Itulah mengapa loyalitas pemimpin daerah harus nampak pada realisasi program kerja yang memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Bukan sebatas pada jumlah suara atau kepentingan partai dalam Pilkada semata.
Agar publik dapat memastikan loyalitas pemimpin daerah dalam mewujudkan tujuan masyarakat itu, prinsip yang paling krusial adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena memungkinkan pengawasan masyarakat dilakukan. Partai politik juga tak kalah penting perannya dalam memastikan pendidikan politik ke masyarakat. Sehingga, masyarakat terdidik (educated society) bertemu dengan prinsip transparansi akan semakin menguatkan sistem politik kita.
Sayangnya, kedua modal sosial itu tak kunjung menjadi. Selain karena pragmatisme dalam berpolitik, publik juga menjadi korban oleh ketidakakuran elit penguasa dalam merespons krisis terkini. Sehingga, perhatian dan fokus pemerintahan yang direalisasikan melalui kepentingan politik kian mandek dan tak mampu menyentuh akar masalah. Maka, Pilkada kali ini sebenarnya dapat menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kepercayaan dan keberpihakan masyarakat pada tawaran program yang berkemanfaatan.
Ketiga, fairness merupakan intisari dari kebijakan politik. Kebijakan yang mengandung ide ini bertugas menjadi penghubung antara kekuasaan dan kepentingan. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang bersumber dari otoritas kekuasaan yang sah yang digunakan untuk memecahkan persoalan hidup bermasyarakat dengan memanfaatkan sarana hukum sebagai dasar berlakunya.
Pilkada sebenarnya menyediakan arena untuk mempertukarkan dan mempertemukan beragam ide kebijakan demi kepentingan publik. Pilkada memeras seluruh energi dan pemikiran kontestan untuk menyusun program-program yang bukan hanya menarik ketika kampanye, tetapi juga program dengan visi jauh ke depan.
Kontestan politik bertarung argumen, mempertimbangkan potensi daerah, mengerahkan kemampuan agitasi kapital politiknya, semata-mata untuk kesejahteraan publik. Maka, pada kesempatan ini pula masyarakat harusnya bisa tercerdaskan. Dalam pengertian, masyarakat memahami isu yang tengah mendera pemerintahan daerah, peluang dan kekuarangan daerah, dan koleksi kebijakan-kebijakan yang pada saatnya nanti perlu diputuskan.
Momentum Pembuktian
Keempat, budaya politik mesti hidup dalam ide care dan sancity. Ide ini menuntut politik praktis dilakukan dengan mengedepankan rasa empati, kebersamaan, gotong-royong, dan kolaborasi. Lebih dalam lagi, politik harus berlandaskan pada nilai suci berupa nilai religiusitas maupun nilai yang dianggap penting (Yudi Latif, 2019).
Pilkada pun demikian, setiap kontestan dinilai pada sejauh mana kepeduliaannya terhadap penderitaan dan kebutuhan rakyat, pengejewantahan pada nilai-nilai religiusistas dan kesucian, serta pada komitmennya membangun kebersamaan dalam kemajemukan. Pada tiap-tiap poin itulah, budaya politik yang unggul dapat kita harapkan.
Akhirnya, Pilkada di Indonesia adalah momentum pembuktian apakah dasar moral dan norma-norma politik masih dapat bertahan hidup dalam iklim politik Indonesia. Jika iya, maka pembangunan daerah dapat kita lihat dalam pandangan penuh optimisme. Jika tidak, inilah alarm bahaya bagi pemenuhan tujuan-tujuan masyarakat.