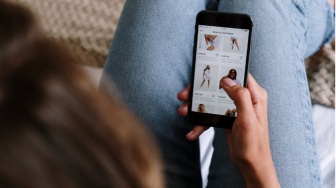Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah garapan Sutradara Kuntz Agus di bawah naungan Rapi Films, menghadirkan satu potret yang begitu familiar sekaligus memilukan. Yakni, seorang ibu yang berdiri teguh di tengah segala problematika.
Dalam trailer-nya, tampak Wulan, sosok ibu yang diperankan Sha Ine Febriyanti, menjemur pakaian laundry di bawah terik, mengayuh sepeda dengan wajah lelah, bahkan harus naik ke atap rumah yang bocor di tengah hujan deras. Semua dilakukan tanpa bantuan suami yang padahal ada.
Adegan-adegan itu mungkin hanya potongan singkat di layar, tapi rasanya seperti cermin besar yang diarahkan ke kehidupan nyata banyak keluarga di Indonesia.
Perjuangan Ibu

Betapa sering kita mendengar kisah ibu yang mengurus segalanya seorang diri. Bekerja, mengasuh anak, membetulkan rumah, hingga menjadi penopang emosional bagi semua orang, sementara sosok ayah hanya jadi nama yang nyaris nggak terdengar.
Film ini seolah-olah ingin berkata, “Lihatlah! Inilah kenyataan yang sering disembunyikan. Bahwa menjadi ibu bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga soal menanggung beban fisik, mental, dan ekonomi.”
Anehnya, masyarakat sering menganggap itu biasa saja. Seolah-olah memang sudah tugas ibu untuk kuat, untuk tahan banting, untuk nggak ngeluh meski tubuhnya nyaris roboh.
Di titik ini, aku merasa Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah melakukan sesuatu yang penting, yakni ngasih panggung pada ‘lelahnya seorang ibu’.
Bukan ibu versi iklan televisi yang selalu tersenyum dengan apron bersih di dapur, bukan ibu versi sinetron yang sabar tanpa cela, tapi ibu yang keringatnya menetes, yang tangannya kapalan, yang matanya sayu karena tidur nggak pernah cukup. Potret itu terasa jujur, dan karena kejujuran itulah kisahnya begitu menusuk hati.
Yang makin menyentuh adalah kenyataannya, bahwa semua itu dilakukan bukan hanya demi dirinya, melainkan demi anak-anaknya yang diabaikan sosok Ayah.
Ada tiga anak perempuan yang ibu besarkan, dan satu laki-laki. Dia tahu betul kalau dirinya menyerah, rumah itu akan runtuh. Maka ibu memilih tetap berdiri, meski sendirian. Ini semacam gambaran dari ketangguhan seorang ibu, yang bisa runtuh berkali-kali di dalam hati, tapi tetap bangkit setiap pagi karena tahu ada hidup lain yang bergantung padanya.
Namun, di balik ketangguhan dan perjuangannya itu, aku benar-benar merasakan getirnya. Entah mengapa, banyak dari kita, sebagai anak atau orang terdekat, (mungkin) menormalisasi kesendirian dan kelelahan mereka (ibu)? Seolah-olah ibu memang ditakdirkan untuk menderita tanpa keluhan, padahal mereka juga manusia yang berhak merasa lemah, berhak ditopang, berhak diistirahatkan.
Di sinilah film ini memaksa diriku maupun dirimu buat merenung. Film yang nggak hanya bercerita tentang perjuangan Wulan sebagai karakter, tapi juga mewakili ribuan bahkan jutaan wajah ibu di luar sana. Ibu-ibu yang mungkin kita kenal, mungkin tinggal di rumah sebelah, atau mungkin ibu kita sendiri. Ibu yang tetap mengurus dapur meski tubuhnya sakit, ibu yang pulang larut dari kerja lalu masih sempat menyiapkan sarapan, ibu yang berusaha menutupi kesedihan supaya anak-anaknya nggak ikut merasa hancur.
Saat nonton adegan Wulan memanjat atap sendirian di tengah hujan, aku merasa dada sesak. Karena itu terasa nggak sebatas akting di layar. Itu kenyataan yang bisa saja terjadi di mana pun. Dan yang paling menyakitkan, sering kali pengorbanan itu justru nggak dianggap. Anak-anak kadang lupa, ayah sering kali abai, dan masyarakat lebih sibuk mengagungkan gambaran ideal tentang ibu tanpa benar-benar menengok letih yang nyata.
Mungkin di sinilah letak keindahan pahit film ini. Yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menatap ibu bukan hanya sebagai sosok yang ‘pantas kuat’, tapi sebagai manusia yang selama ini terlalu sering dipaksa kuat.
Dari sini seharusnya kita paham, tulang punggung pun bisa retak, dan sebelum itu terjadi, kita harus belajar menopang balik mereka, meski dengan hal-hal kecil. Misalnya ngasih pelukan, ucapan terima kasih, sebagai pengakuan bahwa kita melihat apa yang mereka perjuangkan.
Dan mungkin, saat film ini tayang pada 4 September 2025, kita akan keluar dari bioskop lalu menatap ibu di rumah dan berkata, “Aku lihat perjuanganmu. Aku tahu kamu lelah. Dan aku berterima kasih.”
Karena kadang, pengakuan kecil seperti itu bisa lebih berarti daripada apa pun.
Sobat Yoursay, jangan lupa tonton filmnya!