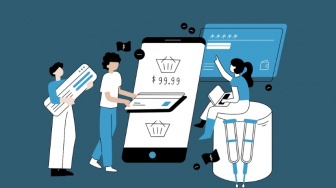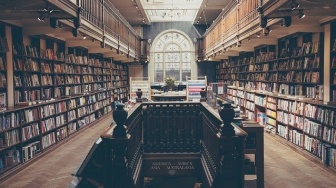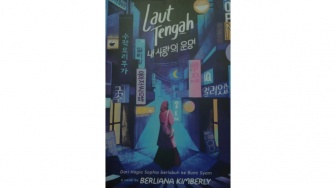Fenomena masif penyebaran hoaks di era digital telah mencapai titik kritis, berfungsi sebagai indikator kelemahan struktural dalam ekosistem informasi nasional, khususnya yang berkaitan dengan literasi digital di kalangan pelajar.
Hoaks, yang didefinisikan sebagai informasi palsu yang dimanipulasi dengan tujuan memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah, membawa dampak buruk yang signifikan. Konsekuensi psikologis dan sosial yang ditimbulkan meliputi kesalahpahaman publik, meningkatnya kebingungan, dan memicu kecemasan yang meluas.
Penyebaran hoaks, yang kini didominasi oleh platform media sosial, menjadi sangat mudah dan cepat, menciptakan siklus disinformasi yang sulit diputus.
Jejak Historis dan Percepatan Digital
Meskipun penyebaran berita bohong bukanlah fenomena baru, yang pada masa lampau dikenal sebagai "surat kaleng" atau pesan anonim, perkembangan teknologi telah mengubah kecepatan dan jangkauan penyebarannya secara drastis.
Jika dahulu penyebaran isu membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu melalui surat fisik, kini hoaks dapat menyebar ke jutaan pengguna dalam hitungan detik. Dengan estimasi sekitar 800 ribu situs yang terindikasi menyebarkan hoaks, kerentanan masyarakat terhadap informasi palsu telah meningkat tajam.
Data Kritis: Jurang Literasi di ASEAN
Kerentanan ini sangat terasa di kalangan pelajar. Penggunaan ponsel pribadi yang meluas di kalangan remaja, di mana data pada tahun 2017 menunjukkan sekitar 18% pengguna media sosial berusia 13–17 tahun adalah pelajar, membuat mereka rentan menjadi target dan konsumen hoaks.
Ironisnya, tingkat literasi digital Indonesia hanya mencapai 62%. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi terendah di antara negara-negara ASEAN, yang rata-rata tingkat literasinya mencapai 70%.
Rendahnya skor ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, di antaranya adalah kesenjangan sarana prasarana digital antara wilayah urban dan rural, kualitas pelatihan guru dan kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya efektif mengintegrasikan keterampilan digital dan berpikir kritis, serta adanya pengaruh langsung dari kemudahan akses teknologi canggih seperti ponsel dan televisi yang tidak diimbangi dengan filter mandiri.
Oleh karena itu, percepatan yang signifikan untuk mengejar tingkat literasi digital sangat dibutuhkan, baik bagi pelajar maupun masyarakat dewasa.
Minimnya literasi digital berdampak negatif ganda. Selain membuat pelajar mudah terjerumus berita hoaks, hal ini secara langsung mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis, sebuah keterampilan penting dalam menyaring dan mengevaluasi informasi. Kegagalan dalam memelihara kemampuan berpikir kritis ini pada akhirnya akan menghambat kemajuan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.
Walaupun Katadata melaporkan adanya peningkatan tipis dalam tingkat literasi pada tahun 2021, dari 3,46 poin menjadi 3,49 poin, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih harus ditingkatkan skalanya.
Studi Kasus: Pelajar sebagai Pelaku dan Korban
Salah satu kasus konkret adalah penyebaran hoaks mengenai insiden pembacokan dua remaja SMA di Denpasar, Bali. Informasi tersebut disebarkan melalui pesan berantai di WhatsApp, yang berisi imbauan waspada kepada masyarakat yang melintasi beberapa jalan utama.
epala Kepolisian Sektor Denpasar Barat, Kompol I Made Hendra Agustina, dengan tegas membantah kebenaran pesan tersebut. Pihak kepolisian bahkan memverifikasi dengan menghubungi berbagai rumah sakit, klinik, dan puskesmas di sekitar Denpasar, dan tidak ditemukan adanya penanganan kasus penusukan atau pembacokan seperti yang diklaim dalam pesan tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa pelajar tidak selalu menjadi korban; mereka juga dapat menjadi pelaku penyebaran hoaks karena minimnya pemahaman literasi digital dan kecenderungan mempercayai berita tanpa memverifikasi fakta. Ini merupakan dampak langsung dari kurangnya literasi masyarakat Indonesia yang terlalu cepat percaya pada berita yang disajikan tanpa mencari kebenaran di baliknya terlebih dahulu.
Respons Pemerintah dan Upaya Komprehensif
Mantan Menkominfo, Rudiantara, pernah menekankan bahaya hoaks yang dapat memicu aksi massa dengan konsekuensi fatal. Sebagai respons, pemerintah berupaya mengurangi dampak hoaks dengan mengambil tiga langkah yang disesuaikan berdasarkan tingkat kegentingan peredarannya, dimulai dari langkah paling ringan, yaitu penutupan akses tautan atau akun yang terbukti menyebarkan hoaks.
Untuk mengatasi masalah ini secara akar, peran kolektif dari sekolah, lembaga, dan orang tua sangat dibutuhkan. Upaya komprehensif yang dapat dilakukan meliputi:
- Peningkatan Minat: Menerapkan kegiatan literasi yang menarik perhatian pelajar, bukan sekadar tugas formal.
- Penyediaan Sarana: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan literasi.
- Edukasi Kritis: Melakukan kampanye publik anti-hoaks dan kunjungan edukasi ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis.
- Keterlibatan Orang Tua: Orang tua harus berkolaborasi dengan sekolah dan secara aktif mengawasi konsumsi berita digital anak.
Menurunkan tingkat penyebaran hoaks harus diiringi dengan peningkatan minat literasi digital yang berkelanjutan. Kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, orang tua, dan individu, adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan minimnya literasi digital di kalangan generasi muda Indonesia.