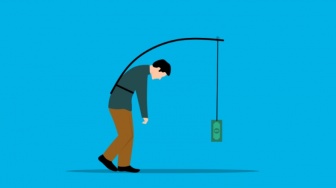News
Prof. Zainal Arifin Mochtar: Menjaga Akal Sehat di Tengah Kemunduran Demokrasi

Pengukuhan Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bukan sekadar seremoni akademik, melainkan peristiwa simbolik yang penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Di tengah menguatnya konservatisme politik dan kian melemahnya independensi lembaga negara, pidato ilmiah yang disampaikannya tampil sebagai penanda bahwa Republik ini masih memiliki intelektual yang bersedia menjaga akal sehat publik dan nadi demokrasi secara konsisten, meskipun sikap tersebut kerap berhadap-hadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Sejak awal kiprah akademiknya, Prof. Zainal Arifin Mochtar menempatkan hukum tata negara bukan sebagai disiplin yang steril dari realitas, melainkan sebagai ruang etik untuk menguji dan membatasi kekuasaan. Konsistensinya terlihat dari keberanian mengkritik pelemahan lembaga-lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi. Kritik tersebut tidak lahir dari kepentingan politik jangka pendek, melainkan dari kesadaran konstitusional bahwa demokrasi hanya dapat hidup jika mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dijaga secara serius.
Ketika banyak akademisi memilih bersikap aman dan kompromistis, Prof. Zainal justru menunjukkan bahwa posisi intelektual menuntut keberanian moral. Dalam pidato pengukuhannya, ia kembali menegaskan bahwa pelemahan independensi lembaga negara sering dilakukan secara sistematis melalui perubahan regulasi, desain kelembagaan, dan praktik politik yang menormalisasi dominasi eksekutif. Dalam kondisi seperti ini, diamnya kaum terdidik justru mempercepat keruntuhan rasionalitas publik dan membuka jalan bagi kemunduran demokrasi.
Yang membedakan Prof. Zainal dari banyak akademisi lainnya adalah posisinya sebagai intelektual organik yang lahir dari pengalaman aktivisme. Ia tidak tumbuh di "menara gading" yang terpisah dari denyut sosial, melainkan dibentuk oleh tradisi kritis gerakan mahasiswa, advokasi konstitusional, dan keterlibatan langsung dalam isu-isu publik.
Dalam kerangka ini, keilmuan yang ia bangun tidak berhenti pada produksi wacana, melainkan hadir sebagai alat emansipasi untuk membela prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Sebagai intelektual organik, Prof. Zainal menjembatani dunia akademik dan ruang publik dengan konsistensi argumen serta integritas sikap. Ia tidak menjadikan gelar akademik sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai basis moral untuk mengoreksi kekuasaan. Dalam lanskap politik yang semakin emosional dan sarat manipulasi informasi, kehadiran intelektual semacam ini berfungsi menjaga rasionalitas publik agar diskursus politik tetap berpijak pada konstitusi, bukan pada loyalitas sempit atau kepentingan sesaat.
Konsistensi tersebut juga tercermin dalam cara Prof. Zainal menyampaikan kritik. Ia tidak membangun narasi konfrontatif yang kosong, melainkan menyusun argumentasi berbasis prinsip hukum, sejarah ketatanegaraan, dan etika demokrasi. Sikap ini menunjukkan bahwa aktivisme tidak harus kehilangan kedalaman intelektual, dan sebaliknya, akademisi tidak harus tercerabut dari keberpihakan normatif pada keadilan dan konstitusi. Di sinilah letak keteladanan yang penting bagi generasi akademisi muda.
Dimensi personal yang muncul dalam pengukuhannya, ketika ia mengenang janji kepada almarhum ayahnya, justru memperlihatkan bahwa integritas intelektual dibangun melalui kesetiaan jangka panjang terhadap nilai, bukan melalui jalan pintas.
Gelar guru besar dalam konteks ini bukan puncak pencapaian, melainkan penegasan tanggung jawab untuk terus berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik, meskipun sikap tersebut tidak selalu populer.
Dalam situasi demokrasi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penyempitan ruang partisipasi hingga normalisasi praktik kekuasaan yang eksesif, keteladanan Prof. Zainal Arifin Mochtar menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak mati secara tiba-tiba, tetapi perlahan terkikis ketika akal sehat ditinggalkan dan intelektual memilih diam. Merawat nadi demokrasi berarti merawat keberanian untuk berpikir kritis, bersuara jujur, dan bertindak konsisten.
Pada akhirnya, meneladani Prof. Zainal Arifin Mochtar berarti meneladani keberanian seorang intelektual organik yang setia pada aktivisme, konstitusi, dan akal sehat Republik. Di tengah arus pragmatisme politik, konsistensinya menjadi pengingat bahwa masa depan demokrasi sangat ditentukan oleh keberanian kaum terdidik untuk tidak tunduk pada kenyamanan, melainkan berpihak pada nilai-nilai dasar Republik.
Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.
Komentar
Baca Juga
Rekomendasi
Artikel Lainnya
Diskusi Geopolitik, UPN Veteran Jakarta Gelar Program Adjunct Professor Bersama Akademisi Malaysia
 Lintang Siltya Utami
Lintang Siltya Utami