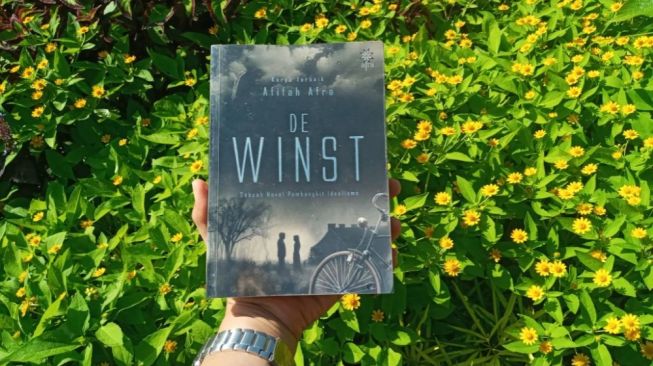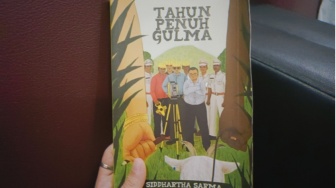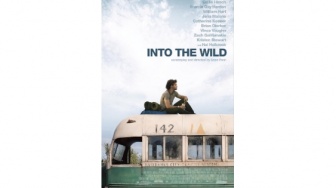De Winst merupakan bagian pertama dari caturlogi De Winst. Tiga novel di belakangnya; De Liefde, Da Conspiracao, dan De Hoop Eiland. Keempat novel sejarah berlatar waktu 1930-an ini dianggit Afifah Afra, diterbitkan di bawah bendera Indiva Media Kreasi.
Sekadar info, novel ini termasuk salah satu karya laris Afifah Afra. Tidak sampai sebulan setelah cetakan pertama dipasarkan, 3.000 eksemplar ludes terjual (padahal, waktu itu, novel ini belum masuk toko buku). Hingga kini, novel ini telah dicetak berulang kali. Terakhir, Maret 2022, dicetak ulang mengiringi keluarnya sekuel pamungkas; De Hoop Eiland.
De Winst menceritakan kehidupan setidaknya, tiga tokoh utama. Pertama, Rangga Puruhita, bangsawan Surakarta yang baru saja menamatkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Leiden, Belanda.
Dia kemudian pulang ke tanah asal, mencoba mengejawantahkan ilmu yang didapatkan dengan bekerja di pabrik gula De Winst. Namun, ketidakcocokan dengan pimpinan, membuat dia hengkang, lalu mendirikan pabrik gula bersama kawan-kawan sekancah. Pabrik gula ini diinisiasi tokoh nasionalis cum islamis-reformis.
Tokoh kedua, Sekar Prembayun, sepupu Rangga, yang gemar menabrak konstruksi moral-sosial mengenai “kehalusan budi perempuan bangsawan keraton”. Dia lebih suka berlatih memanah, menombak, berkuda daripada menekuni “bidang kewanitaan pada umumnya”. Dia juga suka keluyuran keluar keraton untuk membantu pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat jelata.
Celakanya, Rangga dan Sekar dijodohkan oleh keluarga mereka. Keduanya sama-sama menolak.
Rangga telah jatuh cinta kepada Everdine Kareen Spinoza, tokoh ketiga, berlatar belakang Belanda totok, dari kalangan keluarga kaya serta berpendidikan tinggi. Keduanya bertemu dalam pelayaran kapal dari Belanda menuju Nusantara.
Namun, jalinan asmara Rangga-Everdine dipaksa rantas karena jurang perbedaan. Everdine kemudian dinikahi Jan Thijsse, petinggi pabrik gula De Winst.
Sementara Sekar, tidak tertarik (belum?) mengurusi soal jodoh. Dia fokus dalam pemberdayaan anak-anak miskin papa, terlibat dalam aktivitas Partai Rakyat (yang berafiliasi dengan ideologi komunisme), dan giat menganggit tulisan-tulisan pedas untuk mengkritisi Pemerintah Hindia Belanda.
Sekar memandang Rangga sebagai pemuda manja yang senantiasa dilumuri serba fasilitas. Rangga dianggap menganut paham kapitalisme, menilik kampus tempatnya berkuliah dan aktivitas keluarga intinya yang banyak bergaul dengan golongan kulit putih.
Tambah lagi, Rangga jatuh hati dengan Everdine, yang keluarganya dianggap merepresentasikan golongan kolonialis-kapitalis. Dengan itu, Rangga dikira tidak bakal peduli dengan nasib pribumi papa yang diinjak-injak para penjajah.
Rangga pun memiliki pendapat tersendiri mengenai sosok Sekar. Sepupunya itu dianggap terlalu kekiri-kirian, melihat lingkaran pertemanan, buku-buku, serta aktivitas yang dijalaninya. Dan tanpa Sekar ketahui, Rangga turut memikirkan nasib para pribumi yang dibelit kemelaratan serta kebodohan. Dia berpikir-pikir, kontribusi apa yang dapat dilakukan guna memberantas kedua hal tersebut?
Sedangkan Everdine, merasakan hidup kembang-kempis lantaran berumah tangga dengan lelaki kejam yang tidak pernah dicintainya. Suami Everdine bahkan memperkosa adik tiri Rangga, yang membuatnya kian didera lara.
Topik utama yang diusung novel ini adalah ghazwul fikr atau perang pemikiran. Sekurang-kurangnya ada tiga ideologi yang berbenturan di dalamnya, yakni kapitalisme, komunisme, dan islamisme. Rangga terombang-ambing di antaranya.
Seperti kata Sekar, dia memang punya kecenderungan “manja” karena senantiasa ditimang gelimang fasilitas. Akibatnya, Rangga kurang punya ketegasan; kepada ideologi mana dia hendak merapat? Lingkaran perkawanan dengan golongan kyai-santri yang kemudian mempengaruhi Rangga untuk menentukan pilihan.
Sekar yang memiliki jiwa welas asih kepada kaum melarat, memang bersimpati kepada komunisme yang mengusung ide pemerataan sosial-ekonomi. Namun, ideologi itulah yang justru menjerumuskannya. Semata-mata memanfaatkannya saja.
Everdine, sebagai perempuan Belanda berpendidikan Barat murni, entah kenapa tampak kurang menunjukkan greget sebagai perempuan educated. Sehari-hari, dia tampak kerap dibelenggu perasaan nglangut, nelangsa, kurang berdaya.
Berbeda betul dengan Sekar yang tangguh, gigih, dan meradang-terjang.
Mungkinkah Afra sengaja menciptakan demikian guna menjungkir-balikkan stigma: bahwa dulu, pada zaman kolonial, perempuan Barat adalah perempuan mandiri dan berdaya. Sebaliknya, perempuan pribumi lemah dan senantiasa tersandera dalam tetek bengek urusan belakang rumah tangga (sama sekali tidak punya kiprah dalam masyarakat)?
Jika memang benar, maka kesengajaan Afra, berhasil. Sebab, dari ketiga tokoh utama, sosok Sekar-lah yang paling menonjol, paling superior dibanding yang lain.
Novel ini diakhiri secara terbuka, dengan gelaran realita getir, namun tetap membersitkan semangat dan optimisme. Apa itu? Baca sendiri dan temukan kandungan manfaat di dalam novel De Winst ini.