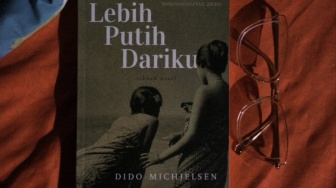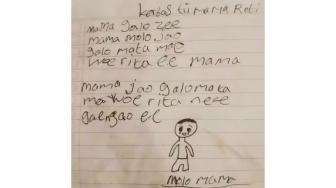Dunia sastra Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan terus berevolusi hingga kini. Mulai dari perkembangannya yang tidak lepas dari perpaduan bahasa dan budaya etnis-etnis beragam di Nusantara dengan Melayu sebagai akar yang menumbuhkan bahasa Indonesia. Perjalanan sastra Indonesia bukan sekadar perjalanan linguistik, tetapi ia juga merupakan perjalanan kesejarahan. Fragmen-fragmen peristiwa masa lampau diabadikan dengan ciamik lewat gores aksara sastra.
Salah satu fragmen masa lampau yang jejaknya begitu menyejarah dalam perjalanan sastra Indonesia adalah masa-masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sangat menggelora. Kita tentu ingat bagaimana rakyat di seluruh penjuru Nusantara berada di garda terdepan perjuangan untuk memukul mundur penjajah dan memiliki kedaulatan sendiri yang kemudian berhasil didapat secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang melibatkan seluruh rakyat tersebut tentunya mengambil bentuk beragam, mulai dari angkat senjata hingga berkesenian.
Seni berperan penting dalam membangkitkan gelora rakyat yang tengah melawan. Salah satu cabang seni yang berperan tersebut adalah seni kesusastraan. Angkatan ’45 menjadi angkatan sastra yang paling mencolok perannya dalam linimasa perjuangan Indonesia karena gayanya yang kuat, realistik, dan lantang. Angkatan sastra yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan tahun-tahun berikutnya ini berbeda dengan angkatan sastra sekarang yang banyak melahirkan karya dengan nuansa romantik-idealis. Beberapa tokoh sastra yang masuk kedalam angkatan’45 adalah Chairil Anwar, Usmar Ismail, Asrul Sani, Pramoedya Ananta Toer, Idrus, Ida Nasution, dan J.E. Tutengkeng.
Pengalaman ketubuhan para penulis sastra Generasi 45 yang dihadapkan pada pendudukan, peperangan, dan pasang-surut revolusi memberikan kekhasan sendiri terhadap karakteristik sastra pada masa tersebut. Salah satunya dan yang paling utama adalah napas keberanian dan kebebasan yang terselip pada tiap aksaranya. Menurut Andri Wicaksono dalam Kajian Prosa Fiksi (2017), para pujangga angkatan ’45 tidak terlalu memperdulikan estetika dalam penulisan karya sastra dan lebih mementingkan substansinya.
Selain jujur dan berani, karya sastra Angkatan ’45 juga jauh lebih ekspresif. Hal ini dipengaruhi oleh aliran seni ekspresionisme yang berkembang pada penghujung abad ke-19 di Eropa dan mendasari lahirnya sastra Angkatan’45 itu sendiri. Contoh ekspresionisme dalam karya sastra Angkatan ’45 dapat kita lihat pada potongan bait puisi Chairil Anwar berikut yang berjudul ‘Puisi Karawang Bekasi’ (1948):
Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati?
Dalam puisi tersebut, Chairil menggambarkan rakyat yang gugur dalam peperangan dan terbaring antara jalan Karawang-Bekasi dengan menambahkan efek emosional pada kalimat ‘Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan mendegap hati?’ yang menekankan bahwa meski para pejuang telah gugur, teriakkan mereka atas kemerdekaan tidak pernah surut dan akan terus bergaung.
Sastrawan angkatan ’45 didominasi oleh individu-individu yang lebih menonjol, dinamis, dan kritis terlihat dari karya-karyanya yang banyak mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang. Salah satu sastrawan yang terkenal karena karya-karya kritisnya adalah Pramoedya Ananta Toer. Berkali-kali ia dijebloskan ke dalam penjara karena karyanya yang subversif, misalnya Hoakiau di Indonesia (1960) yang mengkritisi PP No. 10 Tahun 1959 yang melarang pedagang Tionghoa berjualan di pedesaan membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi pada masa pemerintahan Orde Lama.
Angkatan ’45 membuktikan kepada kita bahwa karya sastra dapat menjadi katalis perubahan di tengah masa-masa penuh gejolak. Bagi generasi ’45, pena adalah senjata dan kertas adalah medan perangnya. Semoga semangat para pujangga angkatan ’45 dapat terus membekas dan dilanjutkan oleh kita – generasi muda – sebagai penerusnya.