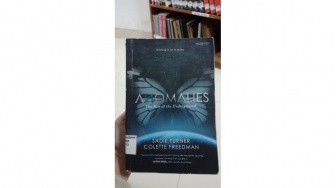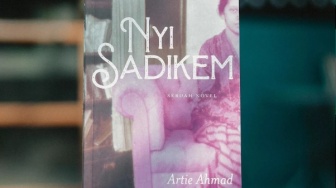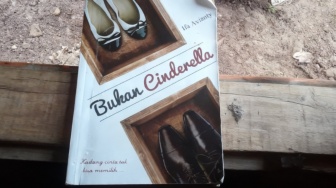Bagaimana jika hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia justru menjadi titik terkelam dalam hidupmu? Dan bagaimana jika takdir mempertemukan dua jiwa yang patah, hanya untuk saling menyembuhkan?
Dalam novel An Eternal Vow karya Iyesari, kita diajak menyelami keheningan yang nyaring—kisah tentang kehilangan, penerimaan, dan bagaimana cinta tumbuh perlahan dari reruntuhan harapan. Ini bukan hanya cerita cinta; ini adalah kisah tentang bertahan, tentang belajar mempercayai kembali, dan tentang bagaimana seseorang bisa menjadi rumah bagi yang lain.
Kisah ini dimulai dengan adegan penuh luka: Almira, masih mengenakan kebaya putih dan riasan pengantin, ditinggalkan di hari pernikahannya. Sang calon suami tak pernah datang. Ia tak marah, tak menangis, hanya duduk dalam diam—seolah tubuhnya mengerti bahwa duka yang besar tidak perlu banyak suara. Peristiwa itu memutus keyakinannya akan cinta, dan untuk waktu yang lama, ia berjalan tanpa tujuan. Ia menjauh dari kehidupan yang dikenalnya, memutus relasi sosial, dan membangun tembok tinggi terhadap siapa pun yang mencoba mendekat. Duka yang ia rasakan tidak meledak dalam amarah, tetapi menyerapnya dalam kesepian yang perlahan mengikis kepercayaan diri.
Namun, hidup membawa Almira kembali ke jalur yang membuatnya berarti: menjadi guru. Ia mengajar di SD Pelita, sebuah sekolah dasar biasa yang kelak akan menjadi tempat ia bertemu dengan seseorang yang juga menyimpan luka. Di sekolah inilah Almira pertama kali bertemu dengan Abigail—siswi kecil yang unik, tertutup, dan berbeda dari anak-anak lain. Abigail bukan anak yang mudah didekati. Ia jarang berbicara, sensitif terhadap lingkungan, dan memiliki pola pikir yang dominan pada otak kanan, yang membuatnya memiliki cara pandang dunia yang berbeda. Banyak guru kesulitan berinteraksi dengannya, tapi Almira menangkap sesuatu yang lain. Ada dunia kecil di dalam diri Abigail yang butuh dijaga, bukan diperbaiki.
Edgar, ayah Abigail, adalah seorang duda yang kehilangan istrinya tak lama setelah Abigail lahir. Sejak itu, hidupnya berputar pada satu poros: membesarkan putrinya dengan penuh kasih, sekaligus menjaga jarak dari dunia luar yang terlalu cepat menghakimi. Banyak perempuan yang mencoba masuk ke hidupnya, namun semua mundur ketika mengetahui kondisi Abigail. Edgar pun menyerah pada ide tentang cinta baru—hingga ia melihat cara Almira memperlakukan putrinya.
Hubungan mereka tumbuh bukan dalam kilatan atau kata manis, melainkan dalam percakapan singkat di ruang guru, dalam tatapan yang penuh perhatian ketika Abigail menunjukkan kemajuan, dalam keheningan yang perlahan menghangat. Almira tidak hanya sabar pada Abigail, tapi juga tulus. Dan itu membuat Edgar perlahan membuka pintu. Ia menyaksikan bagaimana Almira tidak pernah memperlakukan Abigail sebagai anak “berbeda” atau “bermasalah”. Almira memandang Abigail dengan rasa hormat, dan itu menyentuh bagian terdalam dari hati Edgar yang selama ini merasa harus menjadi pelindung sekaligus perisai.
Iyesari membangun cerita ini dengan tempo yang tenang, seolah mengajak kita merenung di tengah halaman. Tidak ada ledakan emosi atau konflik besar yang dibuat-buat. Setiap perkembangan hubungan antara Almira dan Edgar ditulis dengan ketelatenan, dengan nuansa. Bahkan kehadiran Abigail bukan hanya sebagai perantara naratif, tapi sebagai tokoh penuh makna. Ia adalah cermin dari trauma masa lalu, sekaligus jembatan menuju masa depan.
Abigail bukan tokoh yang dikasihani dalam narasi ini. Ia ditulis sebagai anak dengan dunia yang utuh, dengan caranya sendiri dalam merespons kasih sayang dan rasa takut. Di titik inilah kekuatan novel ini terasa: Iyesari tak hanya ingin menyampaikan kisah cinta, tapi juga menyuarakan keberanian untuk menerima perbedaan, dan merayakan keunikan setiap pribadi, bahkan yang dianggap "tidak biasa" oleh masyarakat.
Narasi Iyesari nyaris puitik dalam banyak bagian. Ia piawai merangkai kalimat-kalimat kontemplatif yang menusuk hati, membuat pembaca tidak hanya terhubung dengan tokoh-tokohnya, tetapi juga dengan perenungan-perenungan pribadi. Tentang bagaimana kehilangan bisa membentuk ulang seseorang, tentang bagaimana kesendirian bisa menjadi ruang penyembuhan, dan bagaimana cinta yang tidak terburu-buru bisa menjadi tempat berlabuh yang paling menenangkan.
Meski bagi sebagian pembaca alurnya mungkin terasa lambat, justru di sanalah letak kekuatan novel ini. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin kita duduk, diam, dan ikut menyembuhkan luka bersama tokoh-tokohnya. Seperti Almira yang menyusun kembali hatinya, dan seperti Edgar yang akhirnya mengizinkan cinta masuk lagi. Ia seperti novel yang harus dibaca pelan-pelan, seperti menyeduh teh panas saat hujan turun perlahan—ditemani hening, ditemani kenangan.
An Eternal Vow adalah novel yang penuh kelembutan. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang menyelamatkan, melainkan tentang menemani proses penyembuhan. Bahwa cinta tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang ia hadir seperti embun—diam-diam menghapus luka. Novel ini membisikkan pesan bahwa kita boleh saja patah, tapi bukan berarti kita tak layak dicintai. Bahwa kebahagiaan mungkin tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi ia selalu menemukan jalannya dalam bentuk yang tak terduga.
Untuk kamu yang pernah merasa hancur, yang sedang belajar menerima masa lalu, atau yang diam-diam masih menunggu seseorang yang bisa melihatmu utuh—bacalah novel ini. Ia tidak hanya menyentuh hati, tapi juga merangkul jiwamu. Dalam sunyi, ia berbicara; dalam diam, ia memeluk.