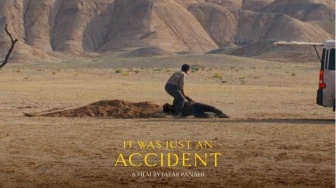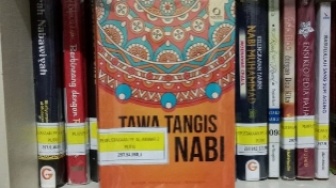Di tengah banjir film-film fiksi berlebihan dan efek spesial yang bombastis, 13 Days, 13 Nights (2025) hadir sebagai tamparan keras yang mengembalikan kita ke realitas pahit dunia nyata.
Disutradarai Martin Bourboulon, yang sebelumnya meraih sukses besar lewat adaptasi The Three Musketeers (2023), film ini merekonstruksi kisah nyata operasi evakuasi heroik Kedutaan Besar Prancis di Kabul pada Agustus 2021, tepat saat Taliban kembali berkuasa.
Berlatar belakang penarikan pasukan Amerika Serikat dan ambruknya pemerintahan Afghanistan secara dramatis, karya ini bukan hanya thriller aksi biasa, melainkan refleksi mendalam tentang nilai kemanusiaan di ujung jurang kehancuran. Berdurasi 112 menit, film ini pertama kali diputar di Festival Cannes 2025 dan kini menjadi salah satu produksi Prancis paling ramai diperbincangkan, walaupun tetap membawa aroma gaya Hollywood khas Luc Besson.
Misi Mustahil Evakuasi Kabul di Tangan Satu Komandan

Sinopsis film ini berpusat pada Commandant Mohamed "Mo" Bida (diperankan brilian oleh Roschdy Zem), kepala polisi elite Kedutaan Prancis di Kabul. Pada 15 Agustus 2021, saat Taliban mendobrak gerbang kota, Mo dan timnya dihadapkan pada misi mustahil: mengevakuasi sekitar 500 orang, termasuk warga Prancis, penerjemah Afghan yang setia, dan warga sipil yang berlindung, menuju Bandara Internasional Hamid Karzai.
Kekacauan merebak: jalanan dipenuhi demonstran panik, Taliban mendirikan pos pemeriksaan bersenjata, dan waktu semakin menipis sebelum pesawat evakuasi terakhir lepas landas.
Mo, seorang pria berlatar belakang campuran Prancis-Aljazair, harus menyeimbangkan protokol birokrasi yang kaku dengan naluri kemanusiaannya yang membara. Ia memerintahkan pembukaan gerbang kedutaan untuk melindungi massa yang mengungsi, meski itu berarti menantang atasan seperti kepala keamanan Martin (Christophe Montenez) yang ragu-ragu.
Di tengahnya, muncul karakter pendukung seperti Eva (Lyna Khoudri), pekerja NGO yang fasih berbahasa Pashtu dan menjadi juru bicara negosiasi dengan Taliban, serta jurnalis Inggris Kate (Sidse Babett Knudsen) yang menyusup untuk menyuarakan suara korban.
Bourboulon, dengan skenario bersama Alexandre Smia, membangun narasi yang linier namun mendebarkan, terinspirasi dari kisah nyata Mo Bida, seorang perwira asli yang menjadi simbol ketabahan Prancis.
Film ini bukan dokumenter; ini lebih mirip rekonstruksi dramatis yang memadukan elemen biografi dengan ketegangan thriller. Adegan pembuka, di mana Mo melompat ke jip untuk menyelamatkan perwira intelijen Afghan yang terluka, langsung menjerat penonton dalam ritme cepat.
Ketegangan mencapai puncak saat konvoi evakuasi terjebak di terowongan bawah jalan yang gelap, dikelilingi unit Taliban nakal di bawah cahaya natrium yang suram, momen yang benar-benar membuat jantung berdegup kencang. Soundtrack orkestra penuh oleh Guillaume Roussel menambah lapisan urgensi, meski kadang terasa berlebihan seperti film aksi Amerika era 90-an.
Tema utama film ini adalah kemanusiaan di zona perang: bagaimana satu keputusan bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga menimbulkan dilema etis. Ini mengkritik kegagalan Barat di Afghanistan secara halus, melalui tatapan Mo yang penuh penyesalan atas janji-janji kosong.
Di era pasca-2021, di mana evakuasi Kabul masih membekas, 13 Days, 13 Nights relevan sebagai panggilan untuk solidaritas global, bisa dibilang intensitas emosional dan performa Zem menjadi bukti meskipun ada beberapa bagian memiliki dramatisasi berlebih.
Review Film 13 Days, 13 Nights

Keunggulan utama 13 Days, 13 Nights terletak pada departemen akting yang benar-benar luar biasa. Roschdy Zem—aktor keturunan Maroko yang meninggal dunia secara tragis pada 2024—menghidupkan sosok Commandant Mohamed “Mo” Bida dengan intensitas yang menyayat hati.
Tatapan matanya yang redup dan suara seraknya berhasil menyampaikan beban psikologis seorang prajurit yang terjepit antara perintah resmi dan dorongan hati nurani. Zem tidak hanya memerankan pahlawan karismatik biasa; ia mewakili suara diaspora Muslim di Eropa yang kerap dipinggirkan, sehingga memberi dimensi tambahan yang kaya pada narasi kebanggaan nasional Prancis.
Lyna Khoudri sebagai Eva tampil segar dan meyakinkan—karakternya bukan sekadar perempuan yang perlu diselamatkan, melainkan figur cerdas dan berani yang menjadi penutur bahasa sekaligus penengah krusial, meski sedikit terjebak klise “satu-satunya orang yang bisa”.
Sidse Babett Knudsen (yang kita kenal dari Borgen) kembali menunjukkan kelasnya sebagai jurnalis Kate, membawa bobot moral tentang pertarungan antara kepentingan negara dan tanggung jawab jurnalistik global. Para pemeran pendukung asal Afghanistan seperti Sina Parvaneh (Sediqi) dan Masuod Fanayee (Qari) memberikan sentuhan autentik, walaupun beberapa dialog mereka terasa agak kaku karena terjemahan yang terlalu literal.
Dari sisi teknis, film ini sangat kuat di bidang sinematografi. Kameraman berhasil merekam kekacauan Kabul yang ambruk dengan cara yang sangat hidup dan nyaris dokumenter: debu beterbangan, kerumunan yang panik, kilauan laras senjata di bawah terik matahari Afghanistan—semuanya terasa mentah tanpa perlu mengandalkan CGI berlebihan. Editingnya juga rapi dan tegas, menjaga tempo tetap kencang meski sebagian besar adegan berlangsung di dalam gedung kedutaan yang penuh dialog.
Akan tetapi, di situlah letak kelemahannya bagi sebagian penonton: jika kamu datang mengharapkan aksi tembak-menembak tanpa henti ala Hollywood, paruh pertama film ini akan terasa “terlalu banyak bicara” dan lambat.
Skripnya memang dipenuhi trope klasik—pahlawan berhati panas versus birokrat beku, negosiasi tegang dengan penutup wajah Taliban yang digambarkan agak karikatural, serta nada nasionalis Prancis yang cukup kentara (seolah-olah hanya Paris yang berjuang sendirian menyelamatkan dunia).
Bagi penonton di luar Prancis, elemen-elemen itu bisa terasa agak manipulatif dan terlalu membanggakan diri. Jika dibandingkan dengan Warfare (2025) karya Alex Garland yang jauh lebih inovatif dan brutal dalam pendekatan visualnya, 13 Days, 13 Nights memang terasa agak kuno dan konvensional.
Tapi justru di sinilah kekuatannya: film ini tidak berpura-pura menjadi mahakarya sinematik mutakhir. Ini hanya ingin menjadi pengingat yang tulus, emosional, dan manusiawi tentang harga kemanusiaan di tengah kekacauan perang—dan tugas itu dilakoninya dengan sangat baik.
Intinya, 13 Days, 13 Nights menghadirkan thriller yang mantap dan kokoh, meski bukan yang bakal mengubah wajah perfilman selamanya—tapi pasti bikin kamu nggak bisa lepas mata dari layar sepanjang durasinya. Skor dariku: 7.5/10. Kalau kamu termasuk maniak film-film berbasis kisah nyata seperti Argo atau Zero Dark Thirty, ini wajib banget masuk watchlist sih.
Di tanah air, film Prancis garapan Martin Bourboulon ini udah resmi rilis sejak 5 Desember 2025, dan bisa kamu tonton di berbagai jaringan bioskop nasional seperti XXI, CGV, dan Hollywood. Jangan lupa cek update jadwal lengkap di situs resmi seperti 21cineplex.com atau cgv.id untuk lokasi terdekatmu—siapa tahu ada promo spesial akhir pekan. Serius, jangan sampai kelewatan sensasi mencekamnya detak jantung Kabul di tengah hiruk-pikuk Taliban; pengalaman ini bakal bikin kamu mikir ulang soal perang dan kemanusiaan, langsung di kursi bioskop yang empuk itu.